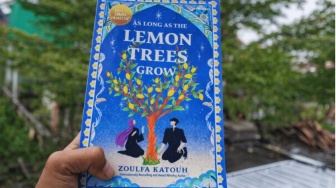Gas air mata seharusnya jadi opsi terakhir untuk meredam kericuhan, tapi beberapa hari terakhir justru jadi semacam senjata pembuka. Begitu ada kerumunan, pssshhht!—awan putih menyebar, membuat bukan hanya pendemo, tapi juga pedagang kaki lima, pengemudi ojek online, bahkan warga sekitar ikut merasakan imbasnya.
Yang lebih aneh, aparat yang mestinya hadir untuk melindungi justru tampak seperti pasukan yang siap “menghajar mundur.” Pemandangan orang-orang berlarian dikejar tameng dan pentungan bukan lagi adegan film dokumenter, tapi kenyataan di jalanan ibu kota Jakarta.
![Suasana di depan Gedung DPR dan Tol Dalam Kota saat aksi di Jakarta, Jumat (29/8/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/08/30/46844-demo-29-agustus-2025-di-jakarta-kerusuhan-29-agustus-di-jakarta-halte-pasar-senen-dibakar.jpg)
Padahal, undang-undang jelas mengatur demonstrasi sebagai hak menyampaikan pendapat. Lalu mengapa menyampaikan pendapat harus dibalas dengan pukulan? Bukankah polisi seharusnya jadi penjaga demokrasi?
Belum lagi aksi penangkapan massal. Ratusan orang ditahan polisi, sebagian bahkan bukan provokator, melainkan mahasiswa atau warga biasa. Ada laporan dari beberapa organisasi bantuan hukum yang menyebut banyak yang ditangkap tanpa alasan jelas dan tanpa pendampingan hukum.
Logikanya, kalau setiap kali ikut demo risikonya adalah ditangkap semaunya, bukankah itu sama saja dengan melarang demo secara tidak langsung? Bukankah itu menciptakan efek jera bukan pada pelanggar hukum, tapi pada hak dasar warga negara?
Lalu tragedi yang paling memilukan ketika seorang pengemudi ojek online kehilangan nyawa setelah dilindas mobil Brimob. Orang itu bukan demonstran, bukan provokator, hanya seorang pekerja yang mencari nafkah. Tapi ujung hidupnya ditentukan oleh roda kendaraan aparat. Dan apa yang terjadi setelahnya? Pernyataan resmi sering kali terdengar lebih seperti kalimat pembelaan ketimbang penyesalan.
![Massa dari berbabagai elemen masyarakat saat aksi unjuk rasa di depan Markas Komando (Mako) Brimob Polda Metro Jaya, Kwitang, Jakarta, Jumat (29/8/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/08/29/74296-kerusuhan-di-mako-brimob-kwitang-mako-brimob-kwitang.jpg)
Kita sering mendengar jargon kalau polisi adalah pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Tapi, apa artinya pelindung, kalau warga sipil malah merasa harus melindungi diri dari polisi? Apa artinya pengayom, kalau setiap kali ada aksi, yang terasa justru ancaman? Apa artinya pelayan, kalau demokrasi dianggap sebagai klien yang merepotkan?
Ironinya, publik makin lama makin sulit membedakan mana polisi yang benar-benar mengamankan, dan mana yang bertindak layaknya preman berseragam.
Kasus-kasus kekerasan aparat ini bukan yang pertama. Lembaga-lembaga seperti Komnas HAM sudah berulang kali mengingatkan bahwa penggunaan kekuatan harus proporsional, dan ada standar internasional yang mengatur penanganan demonstrasi.
Yang paling berbahaya dari semua ini bukan hanya korban fisik, tapi juga korban psikologis, yaitu rasa takut.
Bayangkan mahasiswa yang semula bersemangat turun ke jalan, kini berpikir dua kali karena khawatir ditangkap semaunya. Bayangkan pedagang yang mendengar kabar gas air mata, lalu memilih tak berjualan meski butuh pemasukan harian. Bayangkan keluarga korban ojol yang mendadak kehilangan tulang punggung.
Mungkin sebagian orang akan berkata, “Tapi kan ada demonstran yang anarkis.” Benar, selalu ada oknum yang melempar batu atau merusak fasilitas. Tapi, apakah solusi dari oknum anarkis adalah membuat semua massa jadi sasaran? Apakah logis membalas segelintir provokator dengan menembaki gas ke seluruh kerumunan? Analoginya, kalau ada maling di pasar, apakah pasar harus dibakar habis-habisan?
Polisi sering meminta masyarakat percaya pada institusi mereka, tapi bagaimana caranya percaya kalau tiap kali ada aksi, yang tertinggal hanyalah gambar orang berlarian, teriak kesakitan, dan berita orang meninggal?
Bagaimana caranya percaya kalau aparat lebih cepat mengarahkan moncong gas air mata daripada membuka dialog? Demokrasi tidak tumbuh dari rasa takut. Demokrasi tumbuh dari keberanian berbicara dan jaminan bahwa suara itu didengar, bukan dipukul mundur.
Sampai kapan kekerasan dijadikan bahasa utama negara dalam menghadapi warganya sendiri? Kalau suara rakyat terus dijawab dengan gas, pentungan, dan roda kendaraan, bukankah itu tanda bahwa negara mulai lupa siapa yang seharusnya ia lindungi?