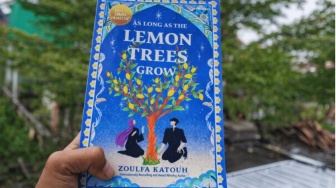Ketika politik negara sedang panas, mungkin kita sering denger teman kita bilang, “Aku netral aja, nggak mau ikut ribut-ribut.” Kalimat ini memang terdengar aman, bahkan bijak. Netral seakan-akan menempatkan seseorang di posisi paling suci, tidak terseret arus politik, dan tidak ikut memperkeruh keadaan. Tapi dalam konteks krisis demokrasi hari ini, diam berarti memihak pada kekuasaan.
Demo demi demo telah berlangsung di berbagai kota Indonesia—Jakarta, Bandung, Makassar, Yogyakarta, hingga Kupang. Video dari jalanan ramai diunggah di media sosial, memperlihatkan massa turun dengan spanduk, suara serak-serak menuntut keadilan, dan aparat berdiri berbaris dengan tameng.
Media asing pun meliput, dari Reuters sampai Al Jazeera, seolah ingin mengingatkan dunia bahwa Indonesia sedang retak di dalam. Tapi anehnya, di tengah riuh itu, masih banyak anak muda yang memilih cuek dan apatis.
Alasannya macam-macam. Ada yang bilang, “demo nggak ngaruh apa-apa, toh kebijakan tetap jalan.” Ada juga yang merasa, “urusan politik ribet, lebih baik fokus kerja atau kuliah.” Ada pula yang sinis, “mereka turun ke jalan paling juga ujung-ujungnya capek sendiri.” Tapi mari coba balikkan pertanyaan, kalau semua orang memilih diam, siapa yang tersisa untuk bicara?
Sejarah sering mengajarkan bahwa kekuasaan paling senang pada masyarakat yang diam. Pemerintah tidak pernah takut pada rakyat yang ribut, karena yang ribut bisa ditertibkan dengan gas air mata atau dibungkam lewat regulasi.
Yang mereka takuti adalah rakyat yang berani bersuara terus-menerus, yang tidak bisa dipadamkan hanya dengan satu-dua intimidasi. Justru masyarakat yang apatis, sibuk pada urusan masing-masing, itulah yang paling memudahkan kekuasaan melanggengkan diri.
Ada kutipan terkenal dari Desmond Tutu, seorang aktivis anti-apartheid di Afrika Selatan, “If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor.” Jika kita netral dalam situasi ketidakadilan, sebenarnya kita sudah memilih berpihak pada penindas. Kalimat ini terasa relevan di Indonesia saat ini.
Mari lihat kenyataan di lapangan. Kebijakan kontroversial seperti UU ITE, UU Cipta Kerja, hingga revisi KUHP, semua lahir di tengah penolakan publik—tapi tetap melenggang mulus, karena sebagian besar masyarakat memilih bungkam setelah lelah sebentar teriak di jalan.
Sikap netral juga sering jadi tameng untuk merasa aman secara sosial. Anak muda takut dicap terlalu vokal, takut beasiswanya dicabut, atau takut jadi bahan gosip keluarga besar. Tapi kalau dipikir lagi, apa artinya kenyamanan pribadi di tengah kerusakan sistemik?
Demokrasi yang mati perlahan-lahan tidak akan peduli pada nilai IPK ataupun prestasi kerja kita. Ketika ruang kebebasan dibatasi, semua orang akan merasakan dampaknya—bahkan yang selama ini merasa aman dengan diamnya.
Bicara soal netral, kita juga harus bedakan antara “netralitas” dan “objektivitas.” Netral artinya menolak berpihak. Objektif artinya melihat fakta apa adanya.
Dalam konteks demokrasi Indonesia sekarang, faktanya jelas, kebebasan sipil makin tertekan, protes sering dihadapi dengan kekerasan, dan suara rakyat makin dipinggirkan. Menjadi objektif berarti berani mengakui ini semua. Sedangkan menjadi “netral” justru sering berarti menutup mata, berpura-pura tidak melihat ada yang salah.
Lalu, apa artinya tidak diam? Tidak selalu harus turun ke jalan, meski itu pilihan yang sah. Anak muda bisa mulai dengan hal sederhana, seperti rajin membaca berita dari berbagai sumber, membicarakan isu-isu penting di lingkaran pertemanan, mengkritisi informasi yang menyesatkan, atau sekadar menolak ikut-ikutan menyebarkan narasi “lebih baik diam biar aman.”
Di era digital, speak up bisa dilakukan lewat banyak cara, dari thread Twitter, video TikTok, podcast, atau tulisan opini seperti ini. Jangan remehkan suara kecil, karena kalau dikumpulkan, ia bisa mengguncang.
Bayangkan kalau generasi muda hari ini semua memilih diam. Demo hanya akan diisi oleh segelintir orang yang terus dianggap minoritas berisik. Pemerintah akan dengan mudah melabeli mereka sebagai pengganggu stabilitas.
Media akan lebih gampang memelintir narasi, karena tidak ada arus kontra yang kuat. Akhirnya, demokrasi mati bukan karena ditembak mati secara brutal, tapi karena kita semua membiarkannya sekarat perlahan.
Pertanyaannya, mau sampai kapan kita pura-pura netral? Demokrasi tidak mati dalam sekali tikaman; ia mati sedikit demi sedikit, setiap kali ada orang yang bilang, “biarlah, bukan urusan saya.”
Netral bukan solusi. Diam itu bukan posisi aman. Diam adalah keberpihakan—dan sayangnya, keberpihakan pada mereka yang sudah terlalu lama berkuasa.