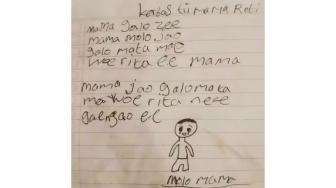Di era serba cepat sekarang, kayaknya semua orang punya obsesi sama kata viral. Nulis di Twitter, bikin caption di Instagram, atau bahkan sekadar status WhatsApp, yang dicari bukan cuma “udah posting”, tapi “berapa banyak yang lihat, like, dan share?”. Rasanya karya yang nggak viral itu sia-sia, padahal nulis kan bukan sekadar tentang engagement.
Aku sering mikir, kenapa kita jadi gampang banget mengukur kualitas tulisan dari seberapa banyak orang yang klik tombol hati? Seolah-olah kalau tulisan kita cuma dibaca segelintir orang, itu artinya gagal. Padahal, tulisan itu punya fungsi yang jauh lebih luas, bisa jadi medium ekspresi, alat refleksi, bahkan kadang jadi terapi personal.
Coba bayangin kalau penulis besar kayak Pramoedya Ananta Toer dulu berpikir, “Ah, kalau naskah ini nggak viral ya udahlah, nggak usah ditulis.” Kita mungkin nggak akan pernah punya Bumi Manusia yang sekarang jadi bacaan wajib banyak orang. Pramoedya nulis di zaman tanpa algoritma, tanpa media sosial, tapi karyanya tetap hidup sampai sekarang.
Kalau dipikir-pikir, viral itu lebih semacam bonus, bukan tujuan utama. Sama kayak masak indomie malem-malem. Tujuannya biar kenyang, bukan biar difoto terus masuk FYP TikTok. Kalau kebetulan fotonya estetik dan rame yang share, ya syukur. Tapi kalau nggak? Tetap aja kenyang kan?
Nulis juga gitu. Kadang kita butuh nulis buat ngeluarin unek-unek, kadang buat mengarsipkan pikiran, kadang sekadar biar ada sesuatu yang bisa dibaca diri kita sendiri beberapa tahun ke depan. Bahkan tulisan yang nggak viral bisa jadi harta karun buat orang-orang tertentu.
Bayangin ada satu orang asing yang baca tulisanmu, terus dia bilang, “Tulisan ini bikin aku ngerasa nggak sendirian.” Cuma satu orang, tapi impact-nya gede banget, dan itu lebih nyata daripada ratusan like yang hilang dalam sehari.
Masalahnya, sekarang kita memang hidup di dunia di mana algoritma punya kuasa gede. Tulisan sebagus apapun bisa terkubur kalau nggak sesuai selera mesin. Sebaliknya, tulisan receh bisa naik ke permukaan kalau kebetulan cocok sama tren.
Akhirnya, kita sering lupa kalau nilai tulisan tuh nggak bisa ditentukan sama algoritma. Nilai tulisan muncul dari isi, konteks, dan resonansi personal.
Ada tulisan panjang yang cuma dibaca serius oleh segelintir orang, tapi mereka rela menghabiskan waktu berjam-jam untuk merenungkan isinya. Ada juga tulisan singkat viral yang dibaca ribuan orang, tapi langsung dilupain begitu aja.
Aku percaya menulis itu soal membuka percakapan. Walaupun kadang percakapannya kecil, personal, bahkan cuma antara penulis dengan dirinya sendiri. Kadang juga bisa melebar, jadi obrolan publik yang ramai.
Kalau semua tulisan harus viral, maka nanti yang muncul cuma tulisan dengan gaya tertentu yang “aman buat algoritma”, sementara suara-suara lain tenggelam. Padahal, justru tulisan kecil, personal, dan sepi pembaca itu yang sering kali membuka perspektif baru.
Ada kalimat bagus dari Ursula K. Le Guin, penulis fiksi ilmiah legendaris, “The unread story is not a story; it is little black marks on wood pulp. The reader, reading it, makes it live: a live thing, a story.” (cerita yang tidak dibaca memang hanya coretan tinta, tapi begitu ada satu pembaca, barulah ia hidup). Jadi, kalau ada satu aja pembaca yang nyambung, tulisanmu udah layak banget.
Jadi, masih layakkah nulis kalau nggak viral? Menurutku, jawabannya iya, seribu kali iya. Tulisan yang nggak viral tetap punya nilai. Bahkan kadang justru lebih jujur, lebih tulus, dan lebih relevan buat pembaca tertentu. Kita cuma perlu geser sedikit cara pandang dari “berapa banyak orang baca” ke “seberapa dalam tulisan ini nyambung sama orang yang baca.”
Karena viral itu sementara, tapi kata-kata bisa abadi.