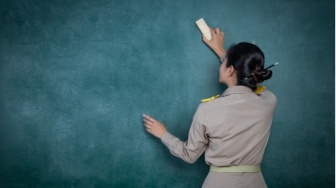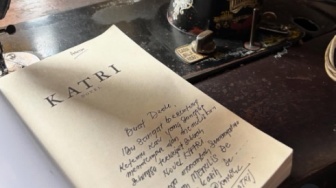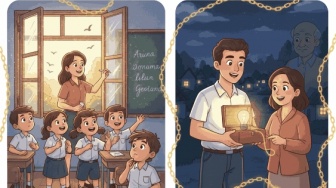Satu kalimat yang seharusnya kita ingat baik-baik sejak Reformasi 1998, adalah tentara harus kembali ke barak. Kalimat ini adalah slogan sekaligus hasil perjuangan panjang masyarakat sipil yang muak melihat militer mengurusi segala hal, dari politik, bisnis, hingga mengintai warganya sendiri.
Namun, ketika Komandan Satuan Siber TNI, Brigjen Juinta Omboh Sembiring, menyebut adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan influencer Ferry Irwandi, rasanya kalimat itu perlu diulang lagi dengan nada yang lebih tegas bahwa tentara seharusnya tidak mengurus pidana sipil.
![Kolase foto Ferry Irwandi (kiri) dan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Freddy Ardianzah (kanan). [Suara.com]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/09/11/60028-ferry-irwandi-kapuspen-tni-freddy-ardianzah.jpg)
Masalahnya bukan semata siapa Ferry Irwandi. Boleh jadi ada pernyataannya yang kontroversial, boleh jadi ada orang yang tak setuju dengan kritik-kritiknya.
Tapi, ketika TNI turun tangan, publik pun mempertanyakan sejak kapan urusan algoritma, opini publik, atau bahkan kritik sosial masuk ke wilayah pertahanan negara? Apakah semua yang menyinggung penguasa bisa dianggap ancaman nasional?
Dulu, narasi back to barrack lahir karena pengalaman pahit di era Orde Baru. TNI saat itu bukan hanya menguasai ranah pertahanan, tetapi juga politik praktis lewat dwifungsi. Akibatnya, demokrasi Indonesia jalan di tempat, karena ruang sipil selalu diawasi aparat berseragam.
Reformasi mencoba membalik keadaan, TNI fokus pada pertahanan negara, sementara urusan sipil, hukum, dan keamanan dalam negeri dipegang Polri. Itu sebabnya pemisahan TNI–Polri pada 1999 dianggap tonggak penting.
Namun dua dekade kemudian, garis pemisah itu makin kabur. Patroli siber TNI awalnya bisa kita pahami dalam konteks pertahanan, misalnya menjaga data strategis negara, melawan serangan siber dari luar negeri, atau memproteksi infrastruktur vital.
Tapi yang kita lihat belakangan, fungsi itu kian melebar. Dari yang seharusnya melawan hacker asing, kini bergeser ke membidik aktivis lokal. Dari yang semestinya fokus pada kedaulatan digital, malah sibuk mengurus cuitan dan video kritik.
Lalu, apa bedanya patroli siber untuk pertahanan dengan patroli siber untuk membungkam sipil? Mungkin jawabannya ada pada tujuan. Pertahanan berarti melindungi negara dari ancaman luar, membangun kedaulatan digital, hingga menjaga infrastruktur strategis agar tak lumpuh.
Membungkam sipil berarti melabeli kritik sebagai ancaman, mengkriminalisasi aktivis dengan dalih hukum, dan akhirnya mempersempit kebebasan berekspresi. Yang satu menjaga negara tetap berdiri, yang satu justru bisa membuat demokrasi roboh pelan-pelan.
Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, sudah menegaskan kalau TNI bukan lembaga penegak hukum pidana. Jika pun bicara urusan siber, itu harus terkait langsung dengan pertahanan negara, bukan mengawasi semua percakapan di dunia maya.
Pernyataan ini adalah kritik sekaligus pengingat agar kita tidak kembali ke masa dimana militer merasa punya hak untuk ikut campur dalam segala urusan.
Kekhawatiran ini semakin relevan karena kasus Ferry bukan yang pertama. Beberapa tahun terakhir, selalu ada upaya untuk memperluas peran TNI di ranah sipil—mulai dari rencana pengerahan TNI dalam pengamanan demo, keterlibatan mereka dalam urusan pembangunan infrastruktur, hingga kini patroli siber yang menjerat influencer. Semua peristiwa ini mengindikasikan bahwa pagar back to barrack makin sering dilompati.
Jika aparat ingin serius menertibkan dunia digital, ada banyak PR yang jauh lebih penting. Judi online misalnya, yang nilainya menurut Menko Polhukam sudah mencapai ratusan triliun per tahun, justru bergerak lebih leluasa.
Begitu juga penipuan digital lintas negara yang merugikan rakyat kecil tiap hari. Kenapa yang lebih cepat ditindak justru kritik dan diskusi soal algoritma? Jangan-jangan algoritma internet dianggap lebih berbahaya daripada praktik judi online yang nyata-nyata bikin ekonomi keluarga ambruk.
Demokrasi hanya bisa berjalan jika ada pembagian peran yang jelas. TNI punya mandat menjaga pertahanan, Polri mengurus keamanan dalam negeri, sementara hukum pidana sipil seharusnya jadi domain aparat penegak hukum.
Begitu pembagian itu dilanggar, risikonya bukan sekadar kasus Ferry, tapi siapa pun yang kritis bisa dianggap musuh negara. Kita pun kembali ke masa di mana rakyat dicekam politik ketakutan.
Satu hal yang perlu diingat adalah ancaman terhadap demokrasi tidak selalu datang dari kudeta atau tank di jalanan. Kadang ia datang dengan cara yang lebih halus, seperti patroli siber, tuduhan tindak pidana, dan kriminalisasi yang dibungkus rapi dengan kata penegakan hukum.
Maka, pertanyaannya bukan lagi apakah Ferry bersalah atau tidak, tapi sampai sejauh mana kita rela memberi ruang pada TNI untuk ikut campur di ranah sipil?