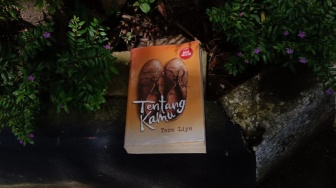Pernah nggak, kamu baru posting story, lalu lima menit kemudian buka Instagram cuma buat lihat siapa yang sudah melihat? Sebenarnya bukan karena penting, tapi entah kenapa ada rasanya senang saat orang lain melihat apa yang baru kita bagikan. Saya pun sering mengaitkan rasa puas dengan tanda-tanda digital seperti like, komentar, share, atau view. Namun, beberapa penelitian ternyata menyimpulkan kalau rasa senang itu sebenarnya bersumber dari reaksi kimia di otak.
Menurut penjelasan di Steve Rose PhD, tanda “like” di media sosial bersifat adiktif karena memengaruhi otak dengan cara yang mirip zat kimia pemicu rasa senang. Setiap “like” memberi sensasi seperti peningkatan reputasi sosial, yang tanpa sadar membuat kita terus membandingkan diri dengan orang lain. Masalahnya, perasaan negatif bisa sering mendorong kita untuk mencari lebih banyak “like” agar merasa lebih baik. Padahal itu cuma solusi jangka pendek karena dalam jangka panjang, bisa menciptakan kecanduan validasi.
Saya pun mengalaminya. Beberapa waktu belakangan saat saya rajin ngonten di tiktok, saya awalnya tidak berekspektasi tinggi bahwa unggahan saya akan FYP tau banyak yang memberi interaksi like, komen, dan sebagainya. Tapi saat itu muncul, dan bahkan beberapa video mencapai views tertentu hingga banyak sekali yang menyukai, mengomentari dan membagikannya, rasa senang yang tak terduga muncul dan saya jadi ketagihan. Standar untuk selalu mendapatkan respon yang sama setiap saya posting video jadi tinggi. Padahal, awalnya tidak ada ekspektasi apa pun.
Ternyata Polk (2015) telah menjelaskan bahwa kecanduan dimulai dari kesalahan prediksi di otak. Ketika bagian otak bernama nucleus accumbens menerima rangsangan lebih kuat dari yang diharapkan, ventral tegmental area (VTA) melepaskan dopamin, zat kimia yang menimbulkan rasa senang sekaligus mendorong otak untuk “belajar mengulangi” pengalaman itu. Inilah mengapa kita terus mengejar notifikasi, bahkan tanpa sadar.
Di media sosial seperti Facebook, TikTok, atau Instagram, “hadiah” itu hadir dalam bentuk jumlah likes, komentar, atau share yang tak terduga. Setiap kali unggahan kita disukai banyak orang, otak menafsirkan itu sebagai “kenaikan reputasi yang tak terduga”, lalu melepaskan dopamin. Lama-kelamaan, otak beradaptasi dan jadi kurang responsif, sehingga kita butuh stimulasi lebih besar, lebih banyak likes, lebih banyak notifikasi, lebih lama scroll.
Hal yang serupa juga dibahas Psikology Today bahwa notifikasi bekerja seperti “hadiah acak” yang kita tidak tahu kapan muncul, sehingga efek kejutan itu membuat kita merasa senang berlebihan. Setiap kali notifikasi muncul, otak kita langsung bereaksi dengan pelepasan dopamin. Maka, wajar jika kita refleks membuka ponsel begitu mendengar ting! dari layar.
Penulis Ranjani di Medium pernah melakukan wawancara kecil pada pengguna Instagram. Hasilnya menarik: ada yang mengaku menunggu siapa saja yang menyukai unggahannya, ada yang langsung menonton live selebriti karena takut tertinggal, dan ada yang merasa percaya diri tiap kali mendapat notifikasi “followed you”. Semua ini memperkuat satu hal bahwa notifikasi menciptakan rasa diterima secara sosial, meski hanya semu.
Fenomena ini bahkan sudah dianggap serius di beberapa negara, sampai muncul undang-undang larangan menggunakan ponsel saat mengemudi, karena meningkatnya kecanduan digital. Tapi di luar soal bahaya fisik, dampak mentalnya membuat kita jadi sulit fokus, mudah cemas, dan merasa kurang berharga kalau postingan kita “sepi.” Kalau dulu validasi datang dari teman atau keluarga, sekarang datang dari angka di layar kecil. Dan itu jauh lebih menekan kita dan membuat kebahagiaan terasa lebih rapuh dari sebelumnya.
Pada dasarnya, bukan kesalahan dari teknologi yang berkembang, juga bukan karena notifikasi yang membuat hidup kita makin tidak normal. Tapi lebih kepada setiap manusia memang punya kebutuhan dasar untuk diakui dan dianggap penting dan notifikasi membuat kita mengejar pengakuan cepat yang sifatnya semu bagaikan dopamin yang membuat kita senang sesaat tapi terus ingin lagi dan lagi.
Mungkin sudah saatnya kita mencoba puasa notifikasi seminggu sekali dengan mematikan semua alert, berhenti menunggu angka, dan belajar merasa cukup tanpa validasi digital. Sebab, bisa jadi bukan notifikasi yang membuat kita kecanduan, tapi rasa ingin dianggap penting.
Dan mungkin, pertanyaan paling jujur yang bisa kita ajukan diri sendiri sekarang adalah, apakah kita masih ingin berbagi kalau tak ada yang menanggapi? Apakah kita masih menulis, merepost, atau bercerita, semata karena ingin merasa lega, bukan karena ingin dilihat?