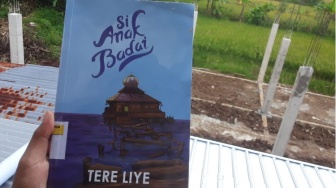Bullying sudah lama menjadi penyakit kronis di lingkungan pendidikan Indonesia. Setiap tahun kampanye anti-bullying muncul, poster ditempel, seminar digelar, dan guru mengulang nasihat yang sama. Namun ironi pahitnya tetap sama, di mana kasus bullying terus terjadi, bahkan semakin brutal dan semakin muda pelakunya. Tentu ini bukan kebetulan.
Bullying bertahan bukan karena minimnya ajakan berhenti, tetapi karena pendidikan kita gagal menyentuh akar persoalan cara kita membentuk karakter.
Meski Ada Poster, Sekolah Belum Tegas Terhadap Pembullyan
Di banyak sekolah, perilaku merendahkan masih dianggap bagian dari dinamika anak-anak. Seorang siswa diejek fisiknya, tetapi guru hanya tersenyum dan berkata, "biasalah, jangan baper". Siswa lain dipermalukan oleh temannya, tetapi justru korban yang diminta lebih sabar.
Dengan logika terbalik seperti ini, korban kehilangan keberanian untuk bersuara dan pelaku belajar bahwa kekerasan bisa dimaafkan sebagai candaan. Inilah kegagalan moral yang sering tidak disadari sekolah justru mengajarkan bahwa luka emosional itu remeh.
Budaya diam yang mengakar memperburuk situasi. Banyak siswa tahu temannya sedang dirundung, tetapi memilih diam karena takut ikut jadi sasaran atau takut disebut sok pahlawan. Guru pun tidak jarang memilih diam demi menjaga nama baik sekolah.
Diam menjadi warisan budaya yang merusak, menjadi penyubur bullying yang paling efektif tanpa perlu tindakan, cukup tidak melakukan apa-apa.
Ditambah lagi, sekolah kita terlalu mengutamakan prestasi akademik. Nilai, ranking, dan lomba menjadi standar utama. Karakter hanya menjadi pelengkap, bukan inti. Akibatnya, siswa yang pintar tetapi merundung teman bisa saja dilindungi karena dianggap membawa nama baik sekolah.
Sementara siswa yang kurang berprestasi lebih mudah disalahkan atau diabaikan. Ketidakadilan seperti ini menciptakan hierarki sosial yang membuka ruang luas bagi intimidasi.
Lebih buruk lagi, guru sering kali tidak dibekali keterampilan memahami kondisi emosional siswa. Di tengah beban administratif yang berat, mereka sulit membangun relasi yang cukup dekat untuk mendeteksi tanda-tanda bullying.
Padahal, pendidikan karakter sejatinya tidak bisa diajarkan lewat modul, melainkan melalui hubungan yang membuat siswa merasa didengar dan aman. Tanpa ruang emosional itu, pelajaran moral hanya menjadi teks, bukan nilai hidup.
Jika pendidikan karakter ingin memiliki makna, itu harus berubah dari sekadar slogan menjadi budaya. Guru harus menjadi teladan dalam tutur kata dan sikap sekolah harus menciptakan sistem yang adil dan tidak memihak dan murid harus diberi ruang untuk belajar empati, bukan sekadar memahaminya secara teori.
Pendidikan karakter yang hidup bukan berbentuk poster di dinding kelas, melainkan praktik sehari-hari yang membentuk sensitivitas, keberanian, dan kepedulian.
Karakter Tidak Lahir dari Ceramah, Tapi dari Keberanian Kita Mengubah Lingkungan
Ada miskonsepsi besar yang selama ini kita pegang bahwa karakter dapat dibangun dengan ceramah panjang atau modul yang disampaikan sekali-sekali. Padahal, karakter hanya terbentuk melalui pengalaman sosial yang diulang melalui lingkungan yang memaksa kita memilih nilai moral tertentu.
Maka, sekolah yang ingin bebas dari bullying harus menciptakan lingkungan yang mendorong empati, bukan persaingan tidak sehat keberanian, bukan kepatuhan buta dan solidaritas, bukan saling merendahkan.
Salah satu langkah penting adalah menghapus budaya diam. Di banyak negara, siswa dilatih menjadi upstander orang yang berani membantu korban atau melapor ketika melihat bullying. Di Indonesia, keberanian seperti ini sering dimatikan sejak kecil dengan nasihat jangan ikut campur dengan urusan orang lain.
Padahal, justru campur tangan sosial seperti itu yang membuat komunitas aman. Anak-anak seharusnya diajarkan bahwa membela yang lemah bukan tindakan mencari masalah, tetapi tindakan moral.
Selain itu, sekolah perlu meninggalkan kultur hukuman yang bersifat menghukum tanpa mendidik. Surat pernyataan atau skorsing memang memberi efek jera sesaat, tetapi tidak menyentuh akar perilaku.
Pendekatan restoratif yang memfokuskan pada mediasi, pemahaman dampak, dan pemulihan relasi lebih mampu membentuk empati. Pelaku tidak hanya dihukum, tetapi belajar melihat luka yang ia ciptakan. Korban tidak hanya dilindungi, tetapi diberi ruang untuk bangkit dengan harga diri yang utuh.
Lingkungan sekolah juga harus memberi ruang aman emosional. Siswa harus tahu bahwa suara mereka didengar tanpa dihakimi.
Guru harus mampu menjadi pendengar yang sabar, bukan hakim yang cepat menyalahkan. Ketika siswa merasa aman secara emosional, mereka lebih berani melapor, lebih mudah membentuk hubungan positif, dan lebih siap menghadapi tekanan sosial.
Pada akhirnya, bullying bukan hanya masalah anak-anak yang nakal. Ini adalah konsekuensi dari budaya sekolah yang gagal menanamkan empati, kelenturan emosi, dan keberanian moral.
Pendidikan karakter yang sebenarnya bukan hanya tentang mencegah suatu tindakan buruk, tetapi tentang membangun manusia yang mampu melihat manusia lain sebagai sesama, bukan sasaran.
Jika karakter tidak dibentuk melalui teladan, lingkungan, dan keberanian kolektif, maka semua slogan hanya akan menjadi dekorasi di dinding kelas.
Masa depan tanpa bullying hanya mungkin jika sekolah berhenti menunggu perubahan dari modul, seminar, atau kurikulum. Perubahan harus dimulai dari kita dari keberanian untuk tidak tertawa ketika orang lain dipermalukan, dari keberanian guru untuk menegur, dari keberanian siswa untuk membela. Karena pada akhirnya, pendidikan karakter bukan tentang apa yang kita tulis, tetapi apa yang kita lakukan setiap hari.