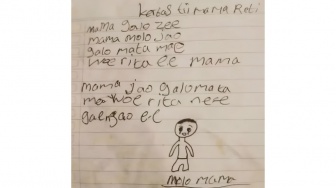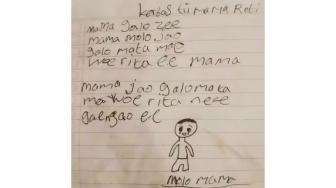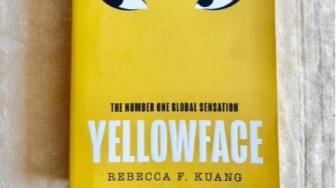Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali berjalan, kali ini bahkan tak mengenal kalender. Saat sekolah libur Natal dan Tahun Baru, dapur tetap mengepul, menu tetap disiapkan, dan anak-anak tetap dipersilakan datang ke sekolah untuk mengambil makanan.
“Jika mau, silakan ambil. Jika tidak, ya tidak dapat,” itulah yang dikatakan Nanik Sudaryati Deyang, Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi.
Memang benar, anak-anak tetap butuh gizi meski sekolah libur. Negara ingin hadir, memastikan asupan nutrisi tidak terputus hanya karena kalender akademik berhenti sejenak. Badan Gizi Nasional bahkan sudah menyiapkan pedoman resmi. Secara konsep, semuanya rapi dan terencana.
Namun, kebijakan publik harus menghadapi realitas sosial yang jauh lebih rumit.
Ketika libur sekolah, fungsi sekolah berubah total. Sekolah bukan lagi ruang belajar yang rutin didatangi murid, melainkan bangunan kosong. Meminta anak-anak datang ke sekolah saat libur bukan masalah mau atau tidaknya, tetapi soal akses, jarak, biaya transportasi, hingga izin orang tua.
Bagi anak di kota, mungkin ini hanya merepotkan sedikit. Namun, bagi anak di desa atau wilayah terpencil, ini bisa berarti perjalanan panjang yang tidak masuk akal hanya demi satu paket makanan. Di sinilah kebijakan yang terlalu administratif sering kali kehilangan empati.
Negara melihat murid sebagai angka penerima manfaat. Selama ada skema penyaluran, program dianggap berjalan. Padahal, dalam praktiknya, “dipersilakan mengambil” bisa berubah menjadi “tidak terlayani secara nyata”. Anak yang tidak datang dianggap memilih, bukan terhalang. Tanggung jawab pun seolah berpindah dari negara ke individu.
Kritik publik yang menyebut program ini terlalu memaksakan pun tidak lahir dari kebencian terhadap gizi anak. Justru sebaliknya. Banyak yang mempertanyakan, apakah ini benar-benar soal gizi, atau soal memastikan anggaran terserap sesuai rencana?
Ketika APBN sudah ketat, defisit menjadi perbincangan, dan bencana banjir serta longsor melanda Aceh dan Sumatra, sensitivitas publik terhadap prioritas anggaran menjadi sangat tinggi. Dalam konteks ini, melanjutkan MBG saat libur sekolah terasa seperti negara menutup mata terhadap situasi darurat lain yang lebih mendesak.
Yang membuat kebijakan ini terasa kaku adalah cara berpikirnya yang seragam. Anak dianggap memiliki kebutuhan yang sama, situasi yang sama, dan kemampuan yang sama untuk mengakses bantuan. Padahal, realitas sosial tidak pernah seragam.
Program yang baik seharusnya mampu menyesuaikan diri dengan konteks. Libur sekolah adalah konteks yang berbeda. Mengapa negara begitu takut menghentikan atau menjeda program, meski sementara? Apakah jeda selalu dianggap kegagalan?
Dalam banyak kebijakan publik, jeda seharusnya bisa menjadi ruang evaluasi. Terlebih, program MBG sudah berkali-kali disorot karena masalah distribusi, kualitas makanan, hingga kasus keracunan di beberapa daerah. Libur panjang ini bisa menjadi momen refleksi. Sayangnya, alih-alih berhenti sejenak dan memperbaiki, kebijakan ini memilih terus berjalan dengan skema yang setengah hati.
Tak heran jika sebagian publik mengusulkan agar anggaran MBG selama libur dialihkan sementara ke penanganan bencana. Bukan karena gizi anak tidak penting, tetapi karena skala urgensinya berbeda. Korban banjir dan longsor kehilangan rumah, akses pangan, bahkan anggota keluarga. Dalam situasi seperti itu, fleksibilitas anggaran menjadi cermin keberpihakan negara.
Kritik lain yang patut direnungkan adalah soal pesan simbolik kebijakan ini. Jika negara tetap menjalankan program dengan prinsip “yang penting program berjalan, bukan dampaknya dirasakan”, maka kebijakan yang niatnya baik justru bisa dipersepsikan sebagai proyek anggaran semata.
Lalu, apakah negara cukup berani untuk berhenti sejenak, mendengar kritik, dan menyesuaikan langkah? Atau, negara akan terus memaksakan program, meski publik semakin merasa jauh dari makna hadirnya negara itu sendiri?