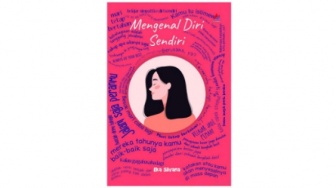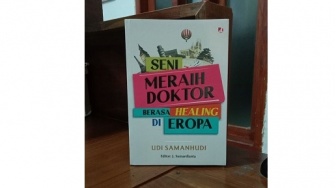Lautan selalu punya cara untuk menelan suara, namun gedung ini justru memuntahkan kengerian yang tak sanggup aku lupakan. Tragedi ini bermula saat tim dokumentasiku—lima orang yang terdiri atas aku, Mira, dan tiga rekan laki-laki—terpilih untuk menggarap proyek visual di Wisma Segara. Gedung itu adalah sebuah monumen kolonial yang di atas tebing pantai selatan, di mana deburan ombak terdengar seperti geraman binatang buas yang kelaparan. Meski sudah dibersihkan, dindingnya terlihat dipenuhi noda garam yang mengkristal akibat paparan udara laut selama puluhan tahun.
Bu Witho, penjaga gedung, mengantar kami ke aula utama. Ia memberikan instruksi singkat dengan nada dingin. "Kalian boleh menggunakan seluruh sayap bawah, tapi jangan sekali-kali menyentuh pintu balkon di lantai dua itu." Ia menunjuk sebuah pintu kayu ulin yang menghitam di ujung balkon, yang dibelenggu oleh sebuah gembok kuno berukuran besar—berkarat, namun tampak sangat kokoh.
"Kenapa pintu itu digembok begitu rapat, Bu?" tanya Mira, asisten kameraku, sambil mencoba menyesuaikan fokus lensa ke arah benda logam tersebut.
Bu Witho tidak segera menjawab. Ia hanya mengencangkan sanggulnya dan bergumam lirih, "Beberapa ruangan memang diciptakan untuk tetap tertutup. Jangan biarkan rasa penasaran membutakan kalian hingga berani melangkah ke lantai balkon itu."
Malam pertama di Wisma Segara diwarnai oleh kelembapan yang mencekik. Meski jendela sudah ditutup, bau amis laut tetap menyusup ke dalam rongga hidung. Beberapa teman mengeluh tentang suara gesekan di atas plafon, seolah ada benda berat yang ditarik perlahan melintasi ubin lantai atas. Aku mencoba bersikap skeptis, menduga itu hanyalah suara hewan atau gesekan dahan pohon yang menghantam dinding luar.
Namun pada malam kedua, kewajaran mulai runtuh. Saat kami tengah menyalin data rekaman di aula bawah, sebuah dentuman keras terdengar dari arah balkon lantai dua. Suaranya bukan seperti barang jatuh, melainkan seperti pintu yang dipukul dengan kekuatan luar biasa dari dalam.
"Ada yang mencoba mendobrak gembok itu?" bisik Olik, wajahnya pucat di bawah temaram lampu monitor.
Berbekal seberkas cahaya senter; aku, Mira, dan Olik bergegas menaiki tangga kayu yang berderit nyaring, memecah keheningan malam yang mencekam. Setibanya di sana, kami membeku. Gembok besar yang sebelumnya terkunci rapat kini tergantung terbuka dalam posisi yang mustahil, seolah-olah baru saja diputar oleh seseorang. Daun pintu itu sedikit terbuka, mengembuskan aroma melati yang sudah membusuk.
Di dalam ruangan yang hanya diterangi cahaya senter yang bergetar, tampak sebuah meja rias dengan cermin yang permukaannya sudah retak seribu. Di hadapannya, duduk sesosok pengantin dalam balutan kebaya kuno yang kainnya sudah lapuk dan dipenuhi noda cokelat. Ia sedang menyisir rambutnya yang panjang dan kusam dengan gerakan kaku. Melalui pantulan cermin yang buram, aku melihat wajahnya—pucat seperti lilin yang meleleh, dengan sepasang mata yang hanya berupa dua lubang hitam yang dalam.
"Siapa di sana?" tanya Mira dengan suara pecah.
Sosok itu tidak menoleh. Ia justru mulai memulas bibirnya yang pecah-pecah dengan gincu merah pekat, sembari melantunkan suara, "Hem... hem... hem..." dengan irama yang rendah dan menyayat hati. Suara gumaman itu terdengar sangat ritmis, seolah-olah ia sedang menidurkan kesedihannya sendiri. Saat kami nyaris lari karena ketakutan, Mira justru melangkah maju. Tubuhnya bergetar hebat, namun matanya menatap lurus ke arah sosok pengantin tersebut. Di saat itulah, Mira menunjukkan sisi dirinya yang sebenarnya.
"Dia tidak ingin menyakiti kita," bisik Mira dengan suara yang terdengar lebih berat, seolah ia sedang menerjemahkan sesuatu yang tidak bisa kami dengar. "Dia hanya terjebak dalam rasa sakit yang lalu."
Tiba-tiba, Mira jatuh berlutut. Matanya terpejam rapat, dan dari mulutnya keluar pesan yang membuat bulu kuduk kami berdiri. "Dia bilang... bawakan dia bunga melati segar setiap tahun di depan pintu ini sebagai tanda bahwa dia tidak dilupakan. Dia meminta agar pintu ini tidak lagi digembok dan memerintahkan kalian untuk segera pergi. Tempat ini bukan untuk kalian."
Kami terpaku diam. Sosok pengantin itu perlahan memudar, meninggalkan rasa dingin yang menusuk tulang. Pintu yang terbuka itu perlahan menutup sendiri. Mira tersungkur pingsan. Kami segera membawanya keluar dari lantai dua, lalu membereskan semua peralatan sebelum hal buruk lainnya terjadi.
Setelah mobil kami melaju sekitar 100 meter meninggalkan tempat itu, kami memutuskan untuk berhenti sejenak dan menghubungi Bu Witho. Meski sadar telah melanggar peringatannya untuk tidak mendekati balkon, kami merasa perlu menyampaikan apa yang baru saja terjadi.
Di luar dugaan, Bu Witho tidak marah. Sebaliknya, ia justru mengucapkan terima kasih dengan nada suara yang penuh kelegaan. Melalui kejadian ini, mereka akhirnya memahami keinginan tulus di balik teror sosok pengantin wanita tersebut—sebuah pengakuan sederhana agar kehadirannya tak dilupakan.
Di perjalanan pulang, setelah Mira perlahan sadar dari pengaruh mediumnya, ia menjelaskan dengan suara parau bahwa arwah tersebut adalah korban dari penantiannya yang hancur karena kesepian. Ia tidak meminta tumbal; ia hanya meminta pengakuan atas keberadaannya yang menyedihkan.
Kejadian ini menyadarkan kami bahwa menolong sesama tidak terbatas pada mereka yang masih bernapas. Terkadang, sebuah jiwa hanya butuh didengar dan diberi empati agar dendamnya luruh. Menolong mereka yang menderita, meski hanya lewat doa atau seikat bunga, adalah bentuk tertinggi dari kemanusiaan yang sering kali kita lupakan.