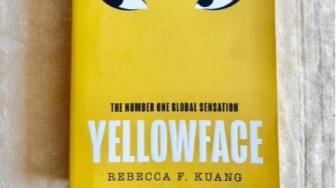Kebijakan Gerakan Ayah Mengambil Rapor yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Dr. H. Wihaji, S.Ag., M.Pd., menjadi sorotan publik menjelang berakhirnya semester ganjil.
Imbauan ini dimaksudkan untuk mendorong keterlibatan ayah dalam pendidikan anak, sekaligus merespons meningkatnya fenomena fatherless yang dinilai berdampak pada tumbuh kembang anak.
Tujuan tersebut patut diapresiasi. Peran ayah memang kerap terpinggirkan dalam praktik pengasuhan, sementara beban emosional dan domestik lebih banyak dipikul ibu.
Namun, di lapangan, kebijakan ini justru memunculkan sejumlah persoalan yang menunjukkan bahwa pendekatan yang diambil belum sepenuhnya menyentuh akar masalah.
Alih-alih memperkuat kualitas relasi ayah dan anak, gerakan ini berpotensi terlalu masuk ke ranah privat keluarga.
Fokus kebijakan tereduksi pada kehadiran fisik saat pengambilan rapor, bukan pada keterlibatan emosional dan konsistensi peran ayah dalam kehidupan anak sehari-hari. Akibatnya, kebijakan ini terkesan seremonial dan belum menyentuh kompleksitas persoalan pengasuhan.
Masalah juga muncul dari minimnya sinkronisasi lintas sektor. Banyak ayah berada dalam posisi dilematis karena harus memilih antara kewajiban pekerjaan dan imbauan kebijakan. Meski surat edaran menyebutkan adanya dispensasi keterlambatan kerja, implementasinya belum merata.
Tidak semua instansi atau tempat kerja memberikan izin, sehingga sebagian ayah terpaksa mengambil cuti atau akhirnya tidak hadir sama sekali. Dalam kondisi tersebut, peran pengambilan rapor kembali dilakukan oleh ibu, yang justru bertolak belakang dengan semangat awal kebijakan.
Dampak kebijakan ini juga perlu dilihat dari sisi anak, khususnya mereka yang masih berada di usia sekolah dasar. Ketidakhadiran ayah dalam momen pembagian rapor berpotensi menimbulkan perasaan kecewa, sedih, bahkan rasa bersalah.
Anak dapat menafsirkan absennya ayah sebagai bentuk kurangnya perhatian, meskipun kenyataannya ayah terikat oleh tuntutan pekerjaan dan kondisi ekonomi keluarga.
Situasi ini bisa diperparah oleh perbandingan sosial. Anak-anak yang melihat ayah teman-temannya hadir berpotensi merasa iri, minder, atau merasa dirinya kurang diperhatikan.
Tanpa disadari, kebijakan yang bertujuan memperkuat relasi keluarga justru dapat menimbulkan tekanan psikologis baru bagi anak dan orang tua.
Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan fatherless tidak bisa diselesaikan dengan imbauan satu kali atau kebijakan simbolik. Pemerintah perlu melihat data, laporan, dan pengaduan masyarakat secara lebih komprehensif untuk merumuskan langkah lanjutan yang berkelanjutan.
Tumbuh kembang anak sangat dipengaruhi oleh kehadiran emosional, komunikasi yang sehat, dan kualitas relasi dengan kedua orang tua, bukan semata kehadiran dalam satu momen formal.
Alih-alih berhenti pada surat edaran, pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang lebih substantif.
Penyediaan layanan konseling keluarga, kelas parenting yang inklusif, serta akses konsultasi psikologi gratis yang mudah dijangkau akan jauh lebih berdampak dalam jangka panjang. Edukasi berkelanjutan juga diperlukan agar orang tua memahami peran pengasuhan secara utuh, bukan sebatas simbol kehadiran.
Pada akhirnya, meningkatkan keterlibatan ayah dalam pendidikan anak adalah tujuan yang penting dan relevan. Namun, tanpa mempertimbangkan realitas sosial, kondisi kerja, dan dampak psikologis anak, kebijakan berisiko melahirkan masalah baru.
Pemerintah dituntut menghadirkan pendekatan yang lebih fleksibel, inklusif, dan berkelanjutan agar peran ayah benar-benar hadir secara substansial, bukan sekadar formalitas kebijakan.