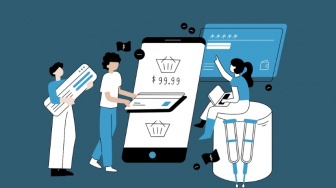Ruang publik Indonesia hari ini dipenuhi suara. Komentar mengalir deras di media sosial, kolom berita, hingga forum daring. Setiap isu segera direspons, ditanggapi, dan diperdebatkan. Namun, di balik keramaian itu, ada satu proses yang justru makin tersisih: membaca. Opini lahir dengan cepat, tetapi pemahaman tertinggal jauh di belakang.
Fenomena ini bukan sekadar soal malas membaca, melainkan telah menjadi budaya. Banyak orang merasa cukup membaca judul, potongan kutipan, atau ringkasan singkat sebelum menyampaikan pendapat. Isi tulisan, konteks, dan argumen utuh kerap diabaikan. Akibatnya, komentar tidak lagi berdiri di atas pemahaman, melainkan di atas asumsi.
Media sosial mempercepat proses ini. Algoritma mendorong kecepatan reaksi, bukan kedalaman refleksi. Konten yang memancing emosi lebih cepat menyebar dibandingkan tulisan yang mengajak berpikir. Dalam iklim seperti ini, membaca dianggap sebagai aktivitas yang lambat dan tidak praktis. Sebaliknya, berkomentar menjadi simbol partisipasi.
Masalahnya, partisipasi tanpa pemahaman justru merusak kualitas ruang publik. Diskusi berubah menjadi adu reaksi. Argumen digantikan oleh serangan personal. Perbedaan pendapat tidak lagi dianggap sebagai ruang belajar, melainkan sebagai ancaman. Ketika membaca ditinggalkan, dialog kehilangan fondasinya.
Budaya komentar ini juga melahirkan ilusi pengetahuan. Seseorang merasa telah “tahu isu” hanya karena mengikuti perbincangan daring. Padahal, yang dikonsumsi sering kali hanyalah fragmen informasi. Opini dibangun di atas potongan-potongan yang terlepas dari konteks. Akibatnya, kesimpulan yang dihasilkan rapuh, tetapi disampaikan dengan keyakinan penuh.
Dalam situasi ini, membaca bukan lagi kebiasaan dasar dalam berpendapat, melainkan pilihan yang sering diabaikan. Padahal, membaca adalah proses penting untuk menimbang, meragukan, dan memahami kompleksitas persoalan. Tanpa membaca, opini kehilangan kedalaman. Ia menjadi sekadar reaksi emosional yang mudah diprovokasi.
Dampaknya tidak berhenti pada percakapan daring. Budaya komentar tanpa membaca merembes ke kehidupan sosial yang lebih luas. Polarisasi menguat karena orang berbicara dari asumsi masing-masing. Kesalahpahaman mudah terjadi karena argumen tidak pernah benar-benar dipahami. Ruang publik menjadi bising, tetapi miskin makna.
Ironisnya, kondisi ini terjadi di tengah akses informasi yang makin luas. Artikel, jurnal, laporan, dan data tersedia dengan mudah. Namun, ketersediaan informasi tidak otomatis melahirkan budaya membaca. Justru sebaliknya, banjir informasi sering membuat orang memilih jalan pintas: bereaksi cepat agar tidak tertinggal arus.
Budaya komentar juga sering diberi legitimasi moral. Berpendapat dianggap sebagai hak yang harus selalu digunakan. Namun, hak berpendapat seharusnya berjalan seiring dengan tanggung jawab untuk memahami. Ketika opini dilepaskan dari proses membaca, hak itu berubah menjadi kebisingan yang menutup ruang dialog.
Masalah ini bukan semata-mata kesalahan individu. Ia berkaitan erat dengan ekosistem digital yang memberi penghargaan pada kecepatan, bukan kedalaman. Platform digital jarang mendorong orang untuk membaca tuntas. Sebaliknya, mereka memberi panggung pada komentar cepat dan respons emosional. Dalam sistem seperti ini, membaca kalah bersaing.
Jika dibiarkan, budaya komentar tanpa membaca akan terus melemahkan kualitas berpikir publik. Kebijakan publik diperdebatkan tanpa pemahaman utuh. Isu sosial dipersempit menjadi slogan. Kritik kehilangan substansi. Pada akhirnya, ruang publik gagal menjalankan fungsinya sebagai tempat bertukar gagasan secara rasional.
Menghidupkan kembali budaya membaca bukan perkara sederhana, tetapi ia adalah prasyarat bagi ruang publik yang sehat. Membaca bukan berarti setuju, melainkan memahami sebelum menilai. Tanpa proses itu, opini hanya akan menjadi gema kosong yang saling bertabrakan.
Dalam masyarakat yang makin kompleks, kecepatan berpendapat tidak bisa menggantikan kedalaman memahami. Jika membaca terus dianggap sebagai beban, sementara komentar dianggap sebagai kewajiban, maka yang mati bukan hanya proses membaca, melainkan juga kualitas dialog itu sendiri.