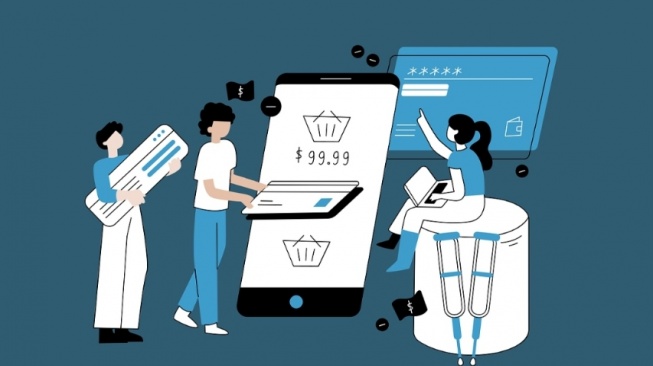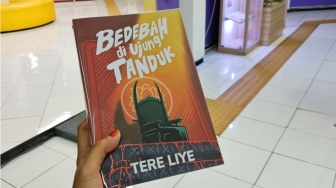Datang ke tempat makan dengan perut lapar, harapannya sederhana: pesan, makan, bayar, lalu pulang. Namun belakangan, urusan "bayar" malah menjadi episode tersendiri.
Bukan soal harga yang mahal, melainkan karena tulisan kecil yang sering luput dibaca: cashless only. Uang tunai yang rapi di dompet mendadak tidak punya kuasa apa-apa. Mau tidak mau, konsumen harus memiliki dompet digital, kartu debit, atau minimal aplikasi yang sinyalnya sedang bersahabat.
Fenomena tempat makan yang menolak pembayaran tunai ini kerap dibungkus dengan narasi modernisasi. Katanya lebih praktis, efisien, cepat, dan kekinian. Semua serba digital, serba scan, dan serba notifikasi. Dunia usaha seolah-olah ingin melompat jauh ke masa depan, sementara sebagian konsumennya masih tertinggal di masa kini, atau malah ditinggal di depan pintu kasir.
Tidak Semua Orang Hidup Sepenuhnya Digital
Masalahnya sederhana tetapi krusial: tidak semua orang hidupnya sepenuhnya digital. Lansia, orang tua, hingga masyarakat yang terbiasa memegang uang tunai sering kali menjadi korban kebijakan cashless only. Mereka datang sebagai konsumen yang sah, memiliki uang yang sah, tetapi tetap tidak bisa membeli hanya karena uangnya tidak berbentuk saldo aplikasi.
Jika ditarik ke ranah hukum, sebenarnya uang tunai bukan benda ilegal. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dengan tegas menyebut rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Bahkan, menolak rupiah sebagai alat pembayaran bisa berujung sanksi pidana. Artinya, secara prinsip, uang tunai memiliki legitimasi penuh untuk digunakan dalam transaksi apa pun.
Aspek Hukum dan Transparansi Informasi
Di sisi lain, pembayaran nontunai juga bukan barang haram. Selama menggunakan denominasi rupiah dan berada dalam sistem yang diakui otoritas, pembayaran digital sah secara hukum. Di sinilah letak abu-abunya. Undang-undang memang tidak secara eksplisit melarang praktik cashless only.
Namun, berhenti di sini saja jelas kurang adil karena urusan ini bukan cuma soal sah atau tidaknya alat bayar, melainkan juga soal hak konsumen.
Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengingatkan bahwa pelaku usaha wajib beritikad baik. Masalahnya, dalam praktik, konsumen sering kali baru mengetahui sistem cashless only setelah memesan, atau lebih parah lagi, setelah selesai makan. Di titik itu, konsumen praktis tidak punya pilihan. Mau protes sudah telanjur, mau batal pun makanan sudah di perut. Situasi seperti ini jelas bukan relasi yang setara.
Pentingnya Transparansi dan Akses yang Inklusif
Konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas, jujur, dan sejak awal. Jika memang tidak menerima pembayaran tunai, sampaikanlah dari depan pintu, dari papan menu, atau dari kasir sebelum pesanan dibuat, bukan melalui pengumuman mendadak yang datang di akhir transaksi. Transparansi ini bukan basa-basi, melainkan hak konsumen.
Kebijakan cashless only juga memiliki potensi diskriminatif. Ketika satu metode pembayaran dijadikan satu-satunya pintu masuk, kelompok tertentu otomatis tersingkir.
Lansia yang tidak akrab dengan aplikasi, masyarakat yang tidak memiliki rekening bank, atau orang yang sekadar ingin membayar dengan uang tunai menjadi tidak bisa mengakses layanan. Padahal, esensi usaha adalah melayani, bukan menyaring konsumen berdasarkan teknologi.
Menuju Modernisasi yang Mengajak, Bukan Mempaksa
Kenyamanan konsumen bukan cuma soal kursi empuk atau makanan enak, melainkan juga rasa aman dan bebas dalam bertransaksi. Dipaksa membayar dengan metode yang tidak dikuasai jelas bukan pengalaman yang nyaman. Modern bagi pelaku usaha bisa jadi merepotkan bagi konsumen.
Padahal, solusinya tidak serumit jargon digitalisasi. Pelaku usaha cukup jujur sejak awal dan tetap menyediakan opsi pembayaran tunai sebagai alternatif. Tidak harus dominan dan tidak harus rumit, tetapi setidaknya ada pilihan. Modernisasi semestinya memperluas akses, bukan justru menyempitkannya.
Pada akhirnya, pembayaran nontunai memang bagian dari kemajuan zaman. Namun, kemajuan yang baik adalah kemajuan yang mengajak, bukan memaksa. Jika modernisasi malah membuat sebagian konsumen tersingkir, mungkin yang perlu dipertanyakan bukan konsumennya, melainkan cara kita memahami kata "maju" itu sendiri.