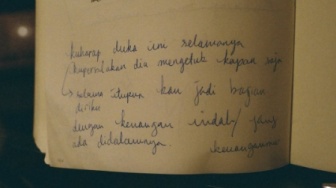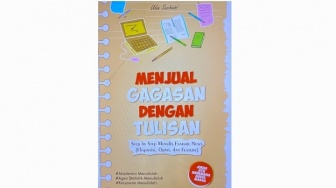Beberapa tahun lalu, fenomena unik dalam bersosial media terjadi, yaitu ramai-ramai menebak isi hati seseorang saat teman kita menulis status galau di Facebook atau mengunggah foto dengan caption puitis di Instagram. Namun sekarang, cara mengintip "isi hati" seseorang tampaknya menjadi jauh lebih praktis sekaligus misterius: cukup lihat apa yang mereka posting ulang (repost).
Fitur repost di TikTok atau Instagram yang awalnya diciptakan untuk membagikan konten menarik, kini telah bermutasi menjadi ajang curhat terselubung. Sebuah video singkat tentang "pengkhianatan", "lelah bekerja", atau "ketidakadilan dalam rumah tangga" yang muncul di tab posting ulang seseorang, kini dianggap sebagai proklamasi kondisi mental mereka yang sebenarnya. Sebenarnya, apa yang terjadi?
Antara Relatability dan Validasi
Secara psikologis, manusia memang memiliki kecenderungan untuk mencari validasi atas apa yang mereka rasakan. Ketika kita melihat sebuah konten yang "gue banget", jari kita secara otomatis menekan tombol repost. Ini adalah cara instan untuk berkata, "Ini yang aku rasakan, tapi aku tidak punya kata-kata untuk menyampaikannya."
Masalahnya, di era di mana privasi semakin menipis, postingan ulang ini menjadi umpan bagi para "detektif amatir" di internet. Begitu seorang artis me-repost konten tentang perselingkuhan, kolom komentar langsung meledak dengan spekulasi: "Ada apa dengan rumah tangganya?", "Wah, kode mau cerai ya?", hingga "Curhat terselubung nih!"
Kode Morse yang Disalahartikan
Sebagai pengguna sosial media juga, saya melihat fenomena ini sebagai pedang bermata dua. Di satu sisi, repost adalah katarsis. Ruang bagi mereka yang mungkin terlalu lelah untuk bercerita secara langsung, namun butuh dunia tahu bahwa mereka sedang tidak baik-baik saja.
Namun di sisi lain, kita sedang terjebak dalam budaya interpretasi liar. Kita sering lupa bahwa tidak semua yang di-repost adalah cerminan hidup. Bisa jadi seseorang membagikan video tentang "mertua jahat" hanya karena dia setuju dengan cara penyampaian videonya, bukan karena dia sedang berperang dengan mertuanya. Kita seolah-olah sedang membaca buku harian orang yang kuncinya sengaja diletakkan di depan pintu.
Bahaya dari "Mengintip" Postingan Ulang
Secara kritis, tren menjadikan daftar repost sebagai indikasi kehidupan asli seseorang adalah perilaku yang melelahkan. Ini menciptakan tekanan baru dalam bersosial media. Kita jadi takut membagikan konten yang benar-benar kita sukai karena khawatir akan dianggap "sedang curhat".
Fenomena ini juga mencerminkan betapa malasnya kita berkomunikasi secara langsung. Alih-alih bertanya "Are you okay?" secara privat, kita lebih memilih memantau tab repost mereka berhari-hari, lalu menyimpulkan nasib hidup mereka dari sana.
Dilema: Menjadi Bijak atau Masa Bodoh?
Lantas, sebagai pengguna media sosial, bagaimana kita harus bersikap? Di sinilah muncul perdebatan antara menjaga citra atau bersikap apa adanya.
Ada argumen yang mengatakan kita harus lebih bijak dan berhati-hati. Kita perlu sadar bahwa setiap jejak digital, termasuk repost adalah pernyataan publik. Jika kita tahu bahwa postingan ulang tentang "toxic parents" akan memicu konflik di grup keluarga besar, mungkin menahan diri adalah pilihan yang dewasa. Kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan orang lain yang salah paham jika kita sendiri yang memberi "umpan" tanpa penjelasan.
Namun, di sisi lain, bukankah media sosial seharusnya menjadi ruang berekspresi? Ada kalanya kita ingin berteriak, "Ya sudah, terserah orang mau anggap apa!" Bersikap masa bodoh atau cuek terhadap asumsi orang lain adalah bentuk kemerdekaan mental. Jika kita terus-menerus memikirkan "Nanti kalau aku repost ini, mereka pikir aku lagi galau nggak ya?", maka media sosial bukan lagi tempat hiburan, melainkan penjara pikiran.
Menyeimbangkan Jempol dan Logika
Kita telah menciptakan sebuah lingkungan di mana orang-orang merasa perlu membedah setiap gerakan jempol orang lain. Padahal, komunikasi yang sehat adalah saat kita ngobrol langsung, berkomunikasi dua arah, bukan melalui malah terjebak dalam tebak-tebakan algoritma.
Sebagai pemilik akun, mungkin kita perlu menyeimbangkan antara kejujuran berekspresi dengan kesadaran akan konsekuensi. Tidak perlu terlalu paranoid, tapi jangan juga terlalu naif. Sementara bagi kita yang hobi mengintip, sudah saatnya kita berhenti menjadi "detektif perasaan" dan kembali memperlakukan media sosial sebagai apa adanya: sebuah panggung, bukan rekam medis.
Sebab pada akhirnya, sebuah repost hanyalah sebuah repost. Terkadang ia memang bermakna, namun sering kali ia hanya lewat karena kita merasa videonya lucu saat dilihat sambil rebahan. Mari berhenti mencocoklogi hidup orang dari satu tombol "posting ulang".