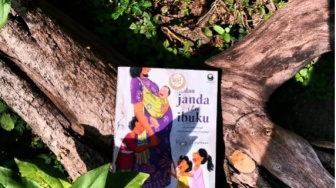Koperasi itu ibarat perempuan baik-baik yang tidak pernah dilirik. Padahal, ia setia, jujur, dan tahan banting. Namun, karena penampilannya sederhana dan cara bicaranya tidak gaul, ia kalah saing dengan mereka yang berdandanan menor dan memiliki jumlah follower jutaan.
Begitu pulalah nasib koperasi di Indonesia.
Dulu, waktu kecil, saya mengira koperasi hanyalah tempat simpan pinjam guru atau tempat ibu-ibu PKK membeli sabun dan gula. Sesekali digunakan saat ingin meminjam uang darurat dengan bunga yang tidak membuat sesak napas. Lalu saya tumbuh dewasa, dan persepsi itu tidak pernah berubah.
Mengapa? Karena koperasi juga tidak pernah berusaha untuk berubah.
Coba tanya anak-anak muda sekarang: “Mau kerja di mana?” Pasti jawabannya: bank, startup, BUMN, kementerian, atau minimal e-commerce. Tidak ada yang menjawab: “Saya mau kerja di koperasi.” Padahal jika dipikir-pikir, mengapa bisa demikian?
Siapa yang Salah?
Bisa dibilang, semuanya salah.
Masyarakat salah karena menganggap koperasi itu ‘kecil’, ‘kampung’, dan ‘tidak keren’. Pemerintah juga salah karena selama dua dekade ini koperasi hanya menjadi embel-embel program, bukan aktor utama ekonomi. Ada Kementerian Koperasi, tetapi yang diurus hanya itu-itu saja: UMKM, pelatihan, dan bantuan sosial.
Koperasi sendiri juga salah. Serius. Banyak koperasi yang manajemennya buruk, tidak transparan, dan dijalankan seperti arisan RT. Ada yang hanya menjual nama, bahkan ada yang isinya koperasi simpan pinjam yang nyaris menyerupai rentenir bersertifikat.
Padahal… di negara lain, koperasi itu keren.
Di Belanda, para petani membentuk koperasi susu bernama FrieslandCampina. Sekarang merek susunya ada di mana-mana, termasuk Indonesia. Di Jepang, koperasi pertanian memegang kendali harga pangan nasional. Di Kanada dan Jerman, koperasi energi angin dan matahari tumbuh pesat. Orang-orang biasa—bukan konglomerat—memiliki pembangkit listrik sendiri. Di Amerika, ada koperasi kredit (credit union) yang bahkan lebih dipercaya daripada bank.
Pegawai di sana pun digaji secara layak, bekerja secara profesional, dan bangga menjadi bagian dari lembaga yang bukan hanya mencari untung, melainkan juga menjaga nilai-nilai sosial.
Lalu, Mengapa di Indonesia Tidak Demikian?
Sebab, koperasi di Indonesia tidak diberi kesempatan untuk naik kelas. Koperasi masih dianggap sebagai ‘tempat pelatihan’, bukan tempat profesional. Masih dikelola dengan sistem kuno dan jauh dari dunia digital.
Padahal, koperasi bisa menjadi lembaga keuangan yang demokratis. Bayangkan jika kita memiliki koperasi keuangan digital yang melayani jutaan petani, nelayan, dan UMKM, lengkap dengan aplikasi, e-wallet, dan sistem akuntansi modern. Kita bisa memiliki koperasi pangan yang mengelola gudang, logistik, dan bahkan masuk ke pasar e-commerce sendiri.
Bayangkan pula koperasi pekerja di sektor kreatif: desainer, penulis, editor, dan pemrogram (programmer) yang tidak bergantung pada marketplace global. Anak muda akan bekerja di situ dengan gaji kompetitif, mendapatkan porsi kepemilikan, dan bangga karena bekerja di tempat yang mereka miliki sendiri. Keren, bukan?
Bagaimana Caranya?
Pertama-tama, kita harus membereskan soal citra. Kita harus mengubah persepsi publik bahwa koperasi:
- Bukan tempat berkumpulnya orang susah, melainkan lembaga bisnis kolektif yang sehat.
- Bukan pekerjaan cadangan, melainkan karier strategis di bidang keuangan, pangan, dan digital.
Kita juga perlu melakukan rebranding. Nama-nama koperasi jangan lagi sepanjang “Koperasi Serba Usaha Makmur Jaya Sejahtera Bersatu”. Ganti dengan nama yang pendek, kuat, dan modern. Misalnya: “Rakyat,” “Tumbuh,” atau “Kolektif.”
Kedua, kita perlu pemimpin yang mengerti perkembangan zaman. Koperasi jangan hanya diisi oleh pensiunan. Isi dengan anak muda, profesional, teknokrat, dan aktivis yang mampu mengelola organisasi, membaca laporan keuangan, membangun aplikasi, dan mengerti strategi marketing.
Bayangkan jika Gojek dahulu dibentuk sebagai koperasi. Sekarang para driver itu bukan sekadar mitra, melainkan pemilik. Keuntungan perusahaan pun dibagi rata, bukan hanya berupa diskon.
Lalu, Peran Negara?
Tentu negara harus hadir, tetapi jangan hanya saat rapat atau sekadar membuat pelatihan. Negara harus:
- Mengeluarkan insentif fiskal untuk koperasi yang serius.
- Membantu koperasi masuk ke dalam rantai pasok pangan nasional.
- Mendorong koperasi digital: koperasi fintech, koperasi logistik, dan koperasi energi.
- Menghapus birokrasi yang berbelit.
Koperasi harus dimudahkan, bukan dibebani laporan rumit seperti perusahaan multinasional, padahal skala operasinya masih kecil.
Terakhir: Maukan Kita Mengubah Pola Pikir?
Kita sering kali terlalu cepat memutuskan bahwa sesuatu itu “tidak mungkin”, termasuk soal masa depan koperasi. Padahal, bank, BUMN, dan startup semuanya dibangun di atas kepercayaan. Koperasi—secara struktur—justru lebih unggul di titik itu.
Jika kita bisa membuat anak muda percaya lagi pada ide koperasi; jika kita bisa membuat lulusan ekonomi, hukum, dan IT mau bekerja di sana; jika kita bisa membuat koperasi tampil setara dengan bank dan perusahaan besar; maka kita akan melihat koperasi bukan sebagai warisan masa lalu, melainkan sebagai masa depan.
Mau? Harusnya, iya.