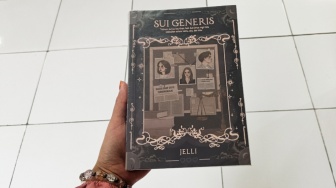Sering kali kita melihat produk kecantikan yang menawarkan janji kulit putih. Dalam iklannya, hampir selalu ditampilkan sosok perempuan dengan kulit putih, bening, dan tampak menawan. Ia digambarkan sebagai pusat perhatian, dikagumi banyak orang, seolah kecantikan membuatnya otomatis lebih bernilai.
Iklan semacam ini hadir di mana-mana: di televisi, media sosial, hingga papan iklan di pinggir jalan. Tanpa disadari, paparan yang berulang itu perlahan membentuk cara pandang tentang standar kecantikan. Banyak perempuan akhirnya dibuat percaya bahwa kulit putih adalah tren kecantikan yang ideal, bahkan sesuatu yang harus dikejar.
Dari situ saya mulai merenung dan bertanya pada diri sendiri: memangnya seseorang harus memiliki kulit putih terlebih dahulu agar bisa disukai dan diterima banyak orang?
Standar Cantik yang Terus Diwariskan
Sejak lama, standar kecantikan sering direpresentasikan lewat sosok perempuan yang tinggi, muda, berkulit putih, dan bertubuh langsing. Gambaran ini terus diulang, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, hingga akhirnya diterima sebagai sesuatu yang wajar.
Tanpa sadar, masyarakat diajarkan untuk percaya bahwa kulit putih adalah simbol kecantikan. Tanda bahwa seseorang bersih, cerah, dan layak dikagumi. Sementara itu, kulit gelap sering kali ditempatkan pada sisi sebaliknya, dilekatkan dengan stigma kusam, kurang terawat, bahkan dianggap tidak memenuhi standar.
Padahal, warna kulit bukanlah hasil pilihan, melainkan bagian dari identitas yang dibawa sejak lahir. Secara genetika, manusia memang terlahir dengan warna kulit yang beragam, dipengaruhi oleh gen dan kadar melanin dalam tubuh. Ada yang berkulit putih cerah, ada pula yang memiliki warna kulit lebih cokelat. Perbedaan ini seharusnya menjadi sesuatu yang normal dan diterima, bukan alasan untuk membuat seseorang merasa kurang, apalagi harus berusaha mengubah dirinya demi terlihat pantas.
Peran Iklan, Sejarah, dan Luka yang Berulang
Sejarah mencatat sebuah kenyataan yang pahit, ketika kulit putih pernah ditempatkan sebagai simbol superioritas, sementara kulit gelap dianggap berada di posisi yang lebih rendah. Jejak pemikiran inilah yang tidak benar-benar hilang, melainkan bertransformasi dalam bentuk yang lebih halus dan modern.
Berangkat dari warisan sejarah tersebut, industri kecantikan seolah menemukan celah untuk memperluas pengaruhnya. Lewat iklan yang terus diulang, banyak perempuan perlahan dibuat merasa tidak menyukai dengan warna kulitnya sendiri. Rasa percaya diri terkikis, digantikan oleh perasaan kurang dan tidak pernah cukup. Perempuan didorong untuk terus membandingkan diri dengan gambaran ideal yang ditampilkan, hingga akhirnya merasa perlu “memperbaiki” apa yang sebenarnya tidak rusak.
Setelah rasa tidak puas itu tumbuh, barulah produk ditawarkan sebagai solusi. Dari sini terlihat bahwa di balik janji kulit cerah dan tampilan menawan, ada sisi gelap industri yang hidup dari keraguan dan ketidakpuasan perempuan terhadap tubuhnya sendiri.
Ketika Standar Cantik Melukai Perempuan
Dampak dari standar kecantikan ini bukanlah sesuatu yang abstrak, melainkan sangat nyata dirasakan oleh perempuan. Banyak yang akhirnya terobsesi membeli berbagai produk kecantikan demi terlihat lebih menarik dan mendekati gambaran ideal yang terus ditampilkan.
Ketika hasilnya dirasa belum cukup, sebagian bahkan rela menempuh jalan yang lebih ekstrem, seperti operasi plastik, demi mendapatkan pengakuan dan menghindari pandangan meremehkan dari sekitar.
Tekanan ini semakin diperparah oleh media sosial yang setiap hari menampilkan wajah dan tubuh “sempurna” versi iklan. Tak sedikit perempuan yang merasa insecure karena tidak mampu terlihat seperti model yang mereka lihat di layar.
Belum lagi komentar-komentar jahat dari lingkungan sekitar yang sering dilontarkan tanpa empati. Komentar-komentar ini perlahan berubah menjadi belenggu, mengikat perasaan dan menggerus kepercayaan diri. Hingga akhirnya, sebagian perempuan merasa kurang layak dicintai hanya karena tidak memiliki kulit yang dianggap ideal.
Perempuan Berhak Dicintai Apa Adanya
Mungkin sudah saatnya kita berhenti sejenak, menarik napas, lalu bertanya dengan jujur pada diri sendiri: siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari standar kecantikan ini? Mengikuti tren yang terus berubah sering kali terasa melelahkan, seolah kita selalu dikejar untuk menjadi versi lain dari diri sendiri.
Padahal, cantik tidak pernah hadir dalam satu warna saja. Setiap perempuan memiliki keindahannya masing-masing, terlepas dari apa pun warna kulit yang ia miliki.
Kabar baiknya, semakin banyak perempuan yang mulai menyadari hal ini dan berani berdamai dengan dirinya sendiri. Bahkan, perlahan muncul iklan-iklan yang tidak lagi memaksa perempuan untuk berubah, melainkan mengajak mereka menghargai apa yang sudah dimiliki saat ini.
Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan, juga kepada diri saya sendiri, bahwa perempuan berhak dicintai apa adanya, tanpa harus diukur oleh standar mana pun.