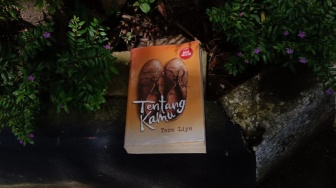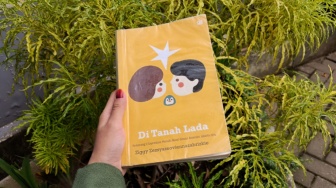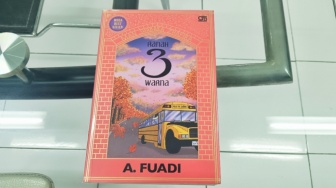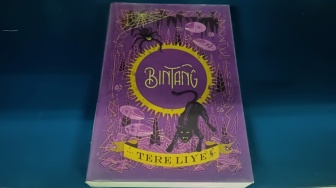Fenomena berbagi kebahagiaan di ruang publik, khususnya melalui media sosial telah menjadi praktik yang lazim dalam kehidupan modern. Unggahan tentang momen liburan, pencapaian pribadi, relasi romantis, maupun aktivitas sehari-hari kerap dimaknai sebagai bentuk ekspresi diri dan kebutuhan untuk terhubung dengan orang lain.
Namun, tidak jarang setelah kebahagiaan tersebut dibagikan, individu justru mengalami perasaan hampa, kecewa, atau bahkan cemas. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar. Mengapa kebahagiaan yang dibagikan tidak selalu berujung pada perasaan yang menguatkan secara emosional?
Secara psikologis, berbagi kebahagiaan melibatkan proses pertukaran emosional. Ketika seseorang menceritakan pengalaman positif, otak secara otomatis membentuk ekspektasi terhadap respons sosial, seperti penerimaan, pengakuan, atau validasi.
Respons ini berperan sebagai penguat emosi positif. Namun, apabila respons yang diterima bersifat netral, meremehkan, atau negatif, maka proses penguatan tersebut gagal terjadi. Akibatnya, emosi positif yang semula dirasakan dapat menurun intensitasnya atau bahkan berubah menjadi emosi negatif.
Fenomena ini berkaitan erat dengan konsep external validation, yaitu kecenderungan individu menggantungkan penilaian diri dan kebahagiaannya pada respons orang lain. Ketika kebahagiaan terlalu bergantung pada validasi eksternal, individu menjadi rentan terhadap fluktuasi emosi yang dipicu oleh faktor di luar kendalinya.
Komentar bernada membandingkan, menyindir, atau meremehkan yang sering muncul dalam interaksi daring, dapat secara signifikan memengaruhi persepsi diri dan kesejahteraan psikologis seseorang.
Selain itu, praktik berbagi berlebihan atau oversharing juga memiliki implikasi emosional yang tidak dapat diabaikan. Dalam psikologi, oversharing sering dikaitkan dengan lemahnya batasan emosional (emotional boundaries).
Ketika individu membagikan detail kehidupan personal kepada audiens yang luas atau kepada orang-orang yang tidak memiliki kapasitas empatik yang memadai, informasi emosional tersebut menjadi rentan disalahartikan, direspons secara tidak sensitif, atau bahkan dimanfaatkan.
Pada situasi tertentu, respons negatif dari orang lain dapat memicu apa yang dikenal sebagai vulnerability hangover, yakni perasaan menyesal, tidak nyaman, atau terkuras secara emosional setelah membuka diri terlalu jauh.
Kondisi ini sering muncul ketika individu menyadari bahwa keterbukaan yang ia berikan tidak diimbangi dengan empati atau dukungan yang diharapkan. Alih-alih merasa didukung, individu justru harus memproses emosi tambahan berupa kekecewaan, rasa malu, atau kemarahan.
Lebih lanjut, berbagi kebahagiaan kepada individu yang sedang berada dalam kondisi emosional tidak stabil—seperti merasa iri, terancam, atau tidak aman—dapat memicu respons Schadenfreude, yaitu kecenderungan menikmati atau merasa puas atas berkurangnya kebahagiaan orang lain. Respons semacam ini, meskipun sering terselubung, dapat mengikis makna kebahagiaan yang semula ingin dibagikan.
Dari sudut pandang neuropsikologis, setiap interaksi sosial memerlukan proses kognitif dan afektif. Saat menunggu dan menafsirkan respons orang lain, otak bekerja untuk menyesuaikan emosi dengan umpan balik yang diterima.
Apabila umpan balik tersebut tidak selaras dengan harapan, individu cenderung melakukan penyesuaian emosional secara tidak sadar, seperti mengecilkan pencapaian diri, merasionalisasi perasaan, atau bahkan menekan emosi positif agar lebih dapat diterima secara sosial.
Dalam jangka panjang, pola ini dapat mengganggu keautentikan emosi dan memperkuat ketergantungan pada penilaian eksternal.
Oleh karena itu, keberadaan batasan emosional menjadi aspek krusial dalam menjaga kesehatan mental. Batasan bukan dimaksudkan untuk mengisolasi diri, melainkan untuk mengatur kepada siapa, sejauh mana, dan dalam konteks apa pengalaman emosional dibagikan. Dengan batasan yang sehat, individu dapat tetap berbagi tanpa mengorbankan integritas emosinya.
Pada akhirnya, kebahagiaan yang berkelanjutan tidak semata-mata bergantung pada pengakuan sosial, melainkan pada kemampuan individu untuk merasakan, memaknai, dan menjaga kebahagiaan tersebut secara internal.
Tidak semua pengalaman positif perlu diekspose ke ruang publik. Sebagian kebahagiaan justru menemukan kekuatannya ketika ia dirawat secara pribadi, aman dari penilaian, dan bebas dari tuntutan validasi eksternal.