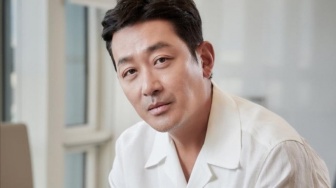Isu rasial di Amerika Serikat kembali memanas akhir-akhir ini akibat kematian George Floyd pada 25 Mei 2020; seorang pria kulit hitam keturunan Afrika, yang tewas dibekuk oleh polisi negara bagian Minnesota bernama Derek Chauvin. Hal ini menyulut kemarahan warga Amerika Serikat; tidak hanya warga kulit hitam, akan tetapi banyak juga warga kulit putih yang ikut bersimpati atas kejadian tersebut.
Tagar #BlackLivesMatter pun mulai ramai di jagat maya, menarik simpati netizen di berbagai belahan dunia dan sempat menjadi trending topic di situs Twitter. Dengan cepat, solidaritas terhadap warga kulit hitam menyebar melalui jejaring internet, dan dimana-mana di seluruh dunia mengampanyekan tagar #BlackLivesMatter.
Di Amerika, aksi solidaritas terhadap warga kulit hitam tidak hanya berlangsung di jagat maya, karena warga di berbagai negara bagian juga melakukan aksi protes turun ke jalan untuk menyerukan keadilan rasial.
Menariknya, aksi protes yang dilakukan warga Amerika ini tidak dipimpin oleh satu orang pemimpin sebagaimana aksi protes konvensional pada umumnya; jenis protes yang seperti ini kemudian dikenal dengan istilah leaderless movements.
Tentunya hal ini merupakan hal yang baru di abad ke-21, karena sarana utama yang digunakan untuk memfasilitasi dan mengoordinasikan gerakan adalah platform media sosial yang memberikan peluang bagi para demonstran untuk berkoordinasi tanpa adanya struktur kepemimpinan yang tersentralisasi (Keating, 2020).
Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah leaderless movements efektif?
Menurut Carne Ross, penulis dari The Leaderless Revolution: How Ordinary People Will Take Power and Change Politics in the 21st Century, kelebihan daripada leaderless movements adalah bahwa pemerintah, atau siapapun yang bersebrangan dengan pihak demonstran, tidak akan mudah melakukan tindakan represif mengingat kekuatan yang terdesentralisasi.
Namun apabila tindakan represif tetap dikerahkan untuk meredam gerakan, yang terjadi adalah sebaliknya; bukannya gerakan tersebut menyusut dan terhenti, akan tetapi gerakan tersebut akan semakin kokoh (Brannen, 2019).
Lebih jauh, keuntungan dari leaderless movements adalah bahwa ‘semangat’ untuk melakukan gerakan akan terus hidup selama solidaritas masih terjaga; hal ini tentu berbanding terbalik jika melihat kepada gerakan yang dipimpin oleh seorang pemimpin.
Berkaitan dengan hal ini, sudah banyak peristiwa yang menunjukkan jika seorang pemimpin tertangkap ataupun wafat, maka para ‘pengikut’nya cenderung bersikap pasif; kalaupun ada yang menggantikan posisi pemimpin tersebut, belum tentu dapat menyaingi kemampuan pemimpin sebelumnya dalam berorasi dan mengorganisir massa, yang berimplikasi pada ketidakefektifan gerakan.
Hal ini dapat terlihat dari gerakan hak-hak sipil di Amerika terdahulu, yang sebelumnya dipimpin oleh Martin Luther King Jr dan Malcolm X yang kemudian terbunuh, dan gerakan tersebut seakan-akan ‘mati suri’.
Namun seperti pepatah yang mengatakan ‘tidak ada gading yang tidak retak’, gerakan tanpa pemimpin atau leaderless movements pun sejatinya memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan yang pertama berkaitan dengan sarana yang digunakan untuk berkoordinasi; dalam hal ini, media sosial.
Walau tak dapat dipungkiri dewasa ini media sosial telah memiliki fitur keamanan yang mumpuni, namun tetap saja terdapat celah yang memungkinkan bagi pihak oposisi untuk melumpuhkan gerakan; melalui pemblokiran internet, peretasan media sosial demonstran, dan lain-lain.
Selanjutnya, tiadanya sosok pemimpin dalam mengoordinasikan gerakan secara tersentralisasi dapat menimbulkan kekacauan; apalagi di saat-saat genting nan krusial, misal apabila terjadi bentrokan dengan aparat.
Berkaitan dengan hal ini, batas yang jelas untuk melakukan kekerasan atau tidak melakukan kekerasan menjadi kabur; dan risikonya, tindakan kekerasan yang dilakukan segelintir ‘oknum’ akan menodai reputasi gerakan secara keseluruhan.
Kurangnya disiplin dan penegasan terhadap pesan yang ingin disampaikan pada barisan demonstran pada gilirannya juga menjadi kelemahan dari leaderless movements, karena dapat menghambat keberlanjutan gerakan jika terdapat kesempatan bagi para demonstran untuk menerjemahkan tuntutan mereka ke dalam perubahan kebijakan yang berkelanjutan.
Berangkat dari kelebihan dan kelemahan yang telah diuraikan sebelumnya, leaderless movements pada kenyataannya semakin populer dan menarik banyak simpati para demonstran untuk mengaplikasikannya.
Mengingat, pendekatan ini dianggap cocok dengan adanya tingkat ketidakpercayaan yang tinggi terhadap lembaga formal; baik dalam tataran politik, bisnis, ataupun media massa.
Namun berkaitan dengan efektivitasnya, hanya dapat terlihat dari hasil yang diakibatkan oleh gerakan tersebut; baik dalam bentuk kebijakan, regulasi, dan sebagainya, sesuai dengan apa yang disuarakan oleh demonstran.
Oleh karenanya, demi keadilan bagi George Floyd dan warga kulit hitam di Amerika, ada baiknya kita doakan agar leaderless movements yang sedang menggelora di Amerika membuahkan hasil yang manis.