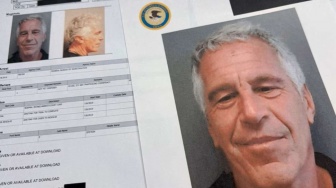Pada 7 November 2020, setelah melalui penghitungan suara yang menegangkan, akhirnya Joe Biden dan Kamala Harris diproyeksikan menjadi Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat terpilih untuk periode 2021-2025. Terlepas dari penggunaan mekanisme electoral college yang dilakukan di Amerika Serikat, secara kuantitas pemilih, kemenangan Joe Biden atas Presiden Petahana Donald J. Trump sangat tipis. Joe Biden mendapatkan sekitar 75 juta suara pemilih sedangkan Donald Trump mendapatkan 70 juta suara pemilih. Fakta miris ini seakan menyampaikan kepada kita, kelemahan terbesar dalam sebuah sistem demokrasi, yaitu para pemilih; rakyat.
Bagi yang kerap mengikuti berita di luar negeri, khususnya politik di Amerika Serikat, mungkin satu pemahaman bahwa Donald Trump mungkin bukanlah presiden terbaik yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Berbagai media massa Amerika Serikat (yang dibrand oleh Donald Trump sebagai fake news) sudah berulang kali mengabarkan masa lalunya yang penuh dengan skandal.
Ia seorang yang rasis, kampanyenya sarat muatan negatif, tidak sungkan menyerang pribadi dan keluarga lawan politiknya, memberikan janji-janji yang absurd dan menuduh sesuatu tanpa dasar yang jelas. Ia juga memimpin Amerika Serikat keluar dari perjanjian perdagangan Trans Pasific, Paris Agreement dan organisasi kesehatan dunia, WHO.
Anehnya adalah, 70 juta pemilih tetap percaya padanya, mereka begitu militan dan tidak tergoyahkan. Bahkan dari mereka mengeluarkan teori-teori konspirasi tidak berdasar yang membahayakan dan selanjutnya malah diamini oleh Donald Trump sebagai suara dari rakyat.
Menurut penulis ini karena Donald Trump memainkan strategi kampanye yang tepat, rasa takut. Rasa takut seperti pada perlindungan kesehatan universal yang dimulai Presiden Obama dan dilanjutkan Biden dianggap sangat kekekirian (komunis).
Rasa takut atas bahaya ekstrimis Islam dan imigran dari negara-negara Amerika Latin. Kampanye rasa takut ini begitu masif disampaikan, sehingga akhirnya dipercaya oleh sebagian masyarakat Amerika Serikat. Hal ini mengingatkan penulis oleh pedoman yang digunakan Menteri Proganda di Era Nazi Adolf Hitler, Joseph Goebbels “If you tell a lie big enough and keep repeating it, people will eventually come to believe it.”
Menganalogikan kepemimpinan Donald Trump dengan Adolf Hitler mungkin sedikit keterlaluan (meskipun hal ini dilakukan oleh beberapa media masa Amerika Serikat), namun tidak bisa dipungkiri ada kemiripan di antara keduanya. Adolf Hitler memberikan kampanye rasa takut pada masyarakat Jerman akan bahaya Yahudi.
Kaum Yahudi dianggap sebagai penyebab merosotnya perekonomian Jerman saat itu. Partai Komunis Jerman, partai oposisi Jerman saat itu, juga diteror oleh Nazi dan sayap militernya SA (Sturmabteilung) habis-habisan hingga akhirnya tidak berdaya. Pendukung Nazi pun sangat militan dan loyal pada pimpinannya, Adolf Hitler.
Oleh karena itu, meskipun perkembangan politik di Amerika Serikat mungkin memiliki pengaruh yang kecil bagi Indonesia, prosesnya dapat kita pelajari. Karena apa yang terjadi pada pemilu Amerika Serikat saat ini, terjadi juga pada pemilihan presiden yang kita lakukan setahun yang lalu.
Kampanye negatif dilakukan sangat gencar di media sosial, militansi antara kedua pendukung Joko Widodo dan Prabowo Subianto juga sangat kentara. Isu masuknya warga negara Cina masuk Indonesia secara ilegal juga muncul sebagai salah satu contoh kampanye “rasa takut” saat itu. Untunglah pasca pemilu, mediasi segera dilakukan oleh Joko Widodo dan Prabowo Subianto untuk mencegah perpecahan lebih lanjut.
Berdasarkan contoh kasus di atas, meskipun pemilu pemilihan presiden di Indonesia masih 4 tahun lagi, tidaklah salah untuk sedari awal menyiapkan 3 komponen yang harus dipenuhi mencegah pelaksanaan demokrasi yang tidak sehat. 3 komponen itu adalah pendidikan, ekonomi, dan calon pemimpin yang berkualitas.
Pertama adalah pendidikan, Pemerintah harus menjamin terlaksananya pendidikan yang memadai, sedari bangku sekolah yang mengajarkan untuk kerap mempertanyakan, mengkaji setiap pendapat yang dikemukakan oleh orang lain, berdasarkan tolak ukur yang jelas dan rasional. Pemerintah juga harus menjamin hak setiap warga negara untuk bebas dalam berekspresi dan mengutarakan pendapat. Media massa juga dituntut harus menyampaikan berita-berita yang dapat dipertanggungjawabkan isinya.
Kedua adalah ekonomi, sudah berulang kali kita mengetahui contoh adanya pendemo-pendemo bayaran, yang menunjukkan bahwa aspirasi politik seseorang bisa dinilai dengan uang, pemikiran rasional tidak mungkin muncul tanpa didukung oleh perut yang kenyang. Oleh karena itu kesejahteraan ekonomi penting untuk diwujudkan oleh pemerintah.
Ketiga adalah calon pemimpin yang berkualitas, yang tidak hanya menjauhkan diri dari kampanye negatif namun juga mematikan dengan cepat benih-benih kampanye negatif yang muncul dari pendukungnya. Mengacu kembali pada pemilu di Amerika Serikat pada tahun 2008, pada saat (Alm) John McCain, yang saat itu menjadi rival dari Barrack Obama dalam merebut kursi Presiden Amerika Serikat, menghentikan utaran rasis yang dikemukakan pendukungnya saat kampanye.
Saat itu ia langsung merebut mike yang dipegang oleh pendukungnya dan berkata “No, ma'am. He's a decent family-man citizen who I just happen to have disagreements with on certain fundamental issues. And that's what this campaign is all about.”
Demokrasi bukanlah sistem pemerintahan yang paling sempurna, namun yang terbaik yang kita miliki, mengutip Perdana Menteri Inggris era Perang Dunia II, Winston Churchill “Many forms of Government have been tried, and will be tried in this world of sin and woe. No one pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed, it has been said that democracy is the worst form of Government except for all those other forms that have been tried from time to time”.
Oleh karena itu, apabila kita ingin terus menggunakan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan kita, kita harus senantiasa menjaganya agar tidak menjadi sarana munculnya pemerintahan yang justru berdampak buruk bagi Indonesia.