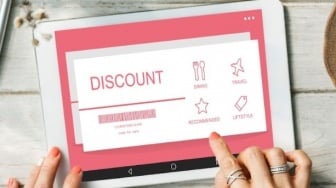Jika demokrasi Indonesia diibaratkan sebagai tubuh seorang atlet, maka penampilannya dari luar tampak sangat mengesankan. Tingkat partisipasi dalam pemilihan umum yang secara konsisten tinggi, debat-debat sengit yang mewarnai linimasa media sosial, dan kebebasan berpendapat yang relatif terjaga, semuanya seolah menunjukkan vitalitas dan kekuatan.
Namun, di balik penampilan yang penuh energi itu, tubuh demokrasi kita sebenarnya menderita sebuah kondisi defisiensi kronis. Ada satu vitamin esensial yang asupannya sangat kurang, yaitu literasi politik. Ketiadaan vitamin ini membuat tubuh demokrasi kita, meskipun tampak aktif bergerak, menjadi rentan terhadap berbagai penyakit serius yang bisa merapuhkan tulangnya dari dalam.
Partisipasi Tinggi, Pemahaman Dangkal

Gejala pertama defisiensi literasi politik terlihat dari paradoks: kuantitas partisipasi tinggi, tapi kualitas pemahaman rendah. Survei Indikator Politik Indonesia rutin menunjukkan angka partisipasi pemilih yang membanggakan dalam setiap pemilu.
Namun, studi lain membuktikan pilihan pemilih jarang berangkat dari pengetahuan soal program kerja atau rekam jejak kandidat. Faktor non-substansial seperti popularitas, kedekatan emosional, bahkan sekadar ikut-ikutan lebih menentukan. Warga memang datang ke TPS, tapi sering tanpa bekal pemahaman yang memadai.
Politik Uang: Infeksi Akibat Imunitas Lemah
Tubuh yang kekurangan vitamin mudah diserang infeksi oportunistik. Dalam demokrasi kita, infeksi itu bernama politik uang. Serangan fajar dan politik perut subur tumbuh karena rendahnya literasi politik.
Bagi warga yang tak terliterasi, suara bukan investasi jangka panjang bagi kebijakan publik, melainkan sekadar komoditas. Hak pilih yang sakral pun jatuh menjadi transaksi banal—ditukar dengan uang receh atau sembako.
Dari Kritis Menjadi Fanatis
Defisiensi literasi politik tak hanya memudahkan politik uang, tapi juga melahirkan fanatisme. Tanpa dasar pemahaman rasional, emosi jadi komoditas politik paling murah.
Alih-alih menilai pemimpin lewat kompetensi atau gagasan, banyak warga memilih berdasar identitas atau persona semu. Diskusi politik berubah jadi perang antarpendukung. Polarisasi ekstrem pun tumbuh, menumpulkan nalar publik dan mengancam persatuan.
Suplemen Literasi: Dimulai dari Sekolah
Defisiensi kronis butuh terapi jangka panjang. Literasi politik harus jadi suplemen rutin, dimulai sejak dini. Peran sekolah menjadi sentral, dengan pendidikan kewarganegaraan yang tak lagi sekadar hafalan kaku tentang struktur negara.
Sekolah seharusnya jadi laboratorium demokrasi kecil. Murid dilatih berdebat santun, menganalisis berita, riset sederhana di komunitas, hingga simulasi pemilu berbasis adu program, bukan popularitas. Inilah dosis literasi yang bisa memperkuat imun demokrasi.
Demokrasi Butuh Vitamin
Literasi politik bukan kemewahan bagi segelintir aktivis. Ia adalah vitamin dasar setiap warga negara. Tanpanya, energi partisipasi yang tampak besar hanya menutupi tubuh demokrasi yang rapuh dan berisiko gagal organ di masa depan.
Kesadaran akan pentingnya literasi politik adalah langkah awal agar demokrasi Indonesia tak sekadar hidup, tapi juga sehat, tumbuh, dan kuat.