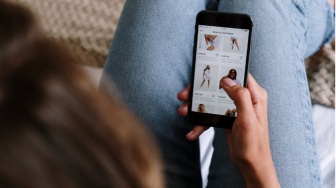Setiap kali pesta demokrasi digelar, baik pilkada maupun pemilu, ruang publik kita selalu penuh riuh. Spanduk menghiasi jalanan, lagu kampanye diputar berulang, dan media sosial dibanjiri perdebatan.
Di balik kebisingan ritualistik ini, ada hal mendasar yang sering terabaikan: literasi masyarakat. Kita terlalu sibuk menebak siapa calon terkuat, tapi jarang bertanya apakah pemilih cukup kuat bekal pengetahuannya. Padahal, kemampuan membaca kritis adalah fondasi yang menentukan kualitas demokrasi.
Literasi sebagai Sistem Imun Demokrasi
Literasi bukan sekadar bisa membaca nama calon di surat suara. Di era banjir informasi, literasi adalah sistem imun demokrasi. Hoaks, disinformasi, propaganda kebencian, dan kampanye hitam adalah virus yang setiap hari menyerang tubuh demokrasi.
Masyarakat dengan literasi tinggi punya imunitas yang kuat: mereka bisa mengenali informasi janggal, memverifikasi sumber, dan tak gampang terprovokasi. Sebaliknya, masyarakat dengan literasi rendah rapuh, mudah “terinfeksi” narasi yang melemahkan tubuh demokrasi.
Dari Literasi Teks ke Literasi Konteks
Masalahnya, definisi literasi kita sering terlalu sempit. Bisa membaca teks belum cukup. Demokrasi modern menuntut literasi konteks: kemampuan membaca udara politik di balik janji manis brosur kampanye.
Literasi konteks membuat pemilih berani bertanya: siapa yang mendanai politisi ini, apa rekam jejaknya, kenapa isu tertentu diangkat menjelang pemilu, dan siapa yang diuntungkan bila ia terpilih? Tanpa itu, masyarakat hanya jadi konsumen pencitraan, memilih berdasarkan gaya bicara, bukan integritas.
Apatisme: Gejala Rendahnya Literasi
Tingginya apatisme politik sering dipandang sebagai penyebab masalah. Padahal, ia lebih tepat disebut gejala dari literasi rendah.
Ketika politik disajikan dalam istilah rumit, data membingungkan, dan debat kusir di televisi, sikap menarik diri menjadi reaksi yang wajar. Apatisme adalah mekanisme pertahanan diri dari kebingungan. Bagaimana mungkin masyarakat peduli pada sesuatu yang tak mereka pahami?
Sekolah sebagai Kawah Candradimuka
Kalau literasi adalah fondasi demokrasi, maka sekolah adalah pondasinya. Tapi sekolah harus berubah: bukan sekadar ruang transfer pengetahuan, melainkan kawah candradimuka kewarganegaraan.
Pelajaran Bahasa Indonesia bisa diarahkan untuk membedah editorial media, mendeteksi bias berita. Sejarah bukan sekadar hafalan tahun, tapi ruang untuk mendebat keputusan politik masa lalu. Pendidikan kewarganegaraan tak boleh jadi hafalan membosankan, melainkan laboratorium demokrasi tempat siswa belajar berdebat sehat, menghargai perbedaan, dan bekerja sama dalam proyek sosial.
Penutup
Masa depan demokrasi kita tidak ditentukan di Senayan semata, melainkan di ruang-ruang kelas dari Sabang sampai Merauke. Investasi pada budaya baca dan berpikir kritis bukan hanya urusan pendidikan, tapi juga strategi keamanan nasional.
Sebab warga negara yang tidak mampu membaca dunianya dengan kritis, sejatinya tidak pernah benar-benar merdeka dalam menentukan pilihan.
Penulis: Angga Sumaris (Ketua Komunitas Pemuda Aktif Desa Yosodadi)