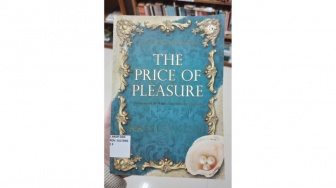Kepergian Timothy Anugerah Saputra membuka luka yang lebih dalam dari sekadar tragedi pribadi. Ia bukan hanya korban bullying, tapi juga potret mahasiswa kritis yang hidup di tengah budaya akademik yang semakin alergi terhadap perbedaan pikiran.
Di kalangan teman-temannya, Timothy dikenal bukan sebagai sosok yang mencari sorotan, melainkan seseorang yang berjuang untuk sesuatu yang ia yakini benar.
Seperti yang ditulis pada akun Instagram @frontmudarevolusioner dalam unggahan perpisahan mereka pada Kamis (16/10/2025). Mereka mengenang Timothy sebagai sosok yang jujur, tulus, dan teguh berjuang demi sosialisme.
“Ia adalah seorang yang tidak pernah mencari kemuliaan pribadi, melainkan kebenaran, keadilan, dan cinta kepada sesama,” tulis akun @frontmudarevolusioner.
Dalam kesehariannya, Timothy dikenal lembut, rendah hati, dan selalu berpikir positif. Namun ketika berbicara tentang ketimpangan dan ketidakadilan, nadanya berubah menjadi tegas.
Ia tidak pernah menutupi pandangan politiknya, dan tidak segan mengkritik kemunafikan kaum yang menurutnya hidup di atas penderitaan orang lain.
Dalam salah satu unggahan video di platform X oleh akun @allandbagus pada Kamis (16/10/2025), terlihat dua potongan video yang kini menjadi arsip berharga dari keberanian Timothy.
Di rekaman pertama, ia berdiri di tengah kerumunan dengan suara lantang dan tubuh yang tegang, berbicara tentang ketidakadilan yang menindas banyak orang.
“Saya katakan sekarang, pekerja sama kelompok politik, apakah mampu berdamai? Apakah mampu bersatu? Tidak,” ucapnya dalam orasi penuh emosi. Kalimat-kalimatnya terdengar seperti teriakan dari hati seseorang yang lelah melihat kompromi dan kepalsuan di ruang politik.
Dalam potongan kedua, Timothy berbicara dengan nada yang lebih terukur, tapi tidak kalah tajam. Ia mengulas relasi antara demokrasi liberal, militerisme, dan kapitalisme dengan kejernihan yang jarang dimiliki mahasiswa seusianya.
“Pada akhirnya, militerisme tidak dapat dipisahkan dengan apa yang kita kenali sebagai masyarakat sipil kita. Dalam demokrasi liberal kita, militerisme itu sebuah tumor. Tetapi penyakitnya itu sudah lama dalam tubuh masyarakat kita. Apa penyakit itu? Kapitalisme,” katanya.
Di akhir pidatonya, ia menyerukan perlunya gerakan yang lebih berani. “Tidak cukup kita meminta-minta. Kita harus menghentikan kerja alurnya. Kita harus melaksanakan sebuah mogok kerja.”
Menutup pidatonya, Timothy menyerukan sesuatu yang melampaui batas ruang akademik. Suaranya tak lagi hanya berbicara atas nama mahasiswa, melainkan untuk seluruh lapisan yang menopang kehidupan kampus dan masyarakat.
“Tak hanya dari sisi mahasiswa, tetapi dari dosen, dari staf, dan bahkan mungkin itu dari pekerja di luar kuliah,” tutupnya.
Orasi dan pidato itu kini beredar luas di media sosial, menjadi potret sosok Timothy yang penuh keyakinan dan kemarahan yang jujur.
Bagi banyak orang, sosialisme mungkin terdengar seperti gagasan usang. Namun bagi Timothy, itu adalah bahasa lain dari empati, sebuah cara memandang dunia yang menolak ketimpangan dan ketidakadilan yang sistemik.
Lebih jauh lagi, kepergian Timothy dan idealismenya menjadi pengingat bahwa menjadi manusia kritis di negeri yang tak suka dikritik adalah bentuk keberanian yang paling sunyi dan paling tulus.
CEK BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS