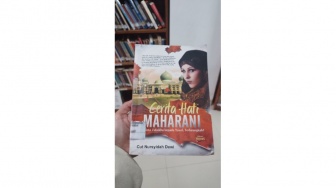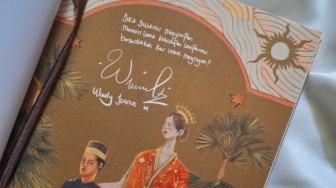Ada banyak kisah tentang cinta, kesuksesan, dan pencapaian. Namun, tak banyak cerita yang berani menyentuh sisi gelap manusia: luka, rasa kalah, dan perjuangan untuk tetap hidup ketika segalanya terasa runtuh. Lika-Liku Luka karya Seplia datang dengan berani mengetuk ruang-ruang itu, tempat di mana banyak orang menyembunyikan keletihan, rasa sakit, dan tangisan yang tak bersuara.
Novel ini tidak dimulai dengan ledakan konflik atau peristiwa dramatis. Ia dimulai dengan hal yang lebih halus, namun menghantam: sebuah rutinitas yang melelahkan, tekanan yang tak kunjung usai, dan pertanyaan dalam diri yang tak kunjung terjawab. Melati, seorang perempuan muda dari keluarga sederhana, menapaki jalan hidup dengan usaha keras, tekad, dan pengorbanan. Ia tumbuh dalam budaya di mana keberhasilan adalah satu-satunya jalan untuk hidup layak. Namun dalam perjalanan itu, ia tak menyadari bahwa pelan-pelan ia kehilangan dirinya sendiri.
Di balik ambisi dan kerja kerasnya, Melati menanggung beban mental dan emosional yang semakin berat. Tuntutan kerja yang tidak manusiawi, keluarga yang tidak memahami, serta standar sosial yang terus menghimpit menjadikannya seperti boneka yang harus terus berjalan, meski tali-tali hidupnya mulai putus
Di sisi lain, Michael, seorang pria muda dari keluarga berada, memiliki segalanya—uang, pendidikan, koneksi, dan segala hal yang membuat hidup tampak mudah. Namun Michael justru merasa kosong. Ia hidup dalam bayang-bayang harapan dan ekspektasi, bukan hanya dari orang lain, tapi juga dari dirinya sendiri. Dunia menilainya beruntung, tapi ia tahu betapa sulitnya mempertahankan kewarasan ketika hidup tak memberi ruang untuk merasa lemah.
Mereka bertemu bukan karena takdir cinta, tapi karena takdir luka. Dua jiwa yang sama-sama patah, mencari tempat bernaung, mencari seseorang yang tidak menilai mereka dari pencapaian atau latar belakang, tapi dari rasa sakit yang mereka bagi.
Yang membuat Lika-Liku Luka begitu unik dan kuat adalah keberaniannya untuk menghadirkan luka sebagai pusat cerita, bukan sekadar bumbu. Seplia menolak menjadikan luka sebagai pemanis drama, tapi menjadikannya sebagai subjek utama yang didekati dengan empati dan kejujuran.
Novel ini menyuguhkan sesuatu yang jarang: potret realistis kehidupan muda-mudi urban yang tampak "baik-baik saja" di luar, namun retak di dalam. Melati dan Michael menjadi representasi dari kita semua—orang-orang yang bertahan di tengah tekanan sosial, keluarga, dan pekerjaan, namun jarang punya ruang untuk mengakui bahwa kita lelah, bahkan terluka.
Tidak ada romantisasi tentang sukses di sini. Tidak ada mimpi besar yang ditawarkan dengan mudah. Yang ada justru penggambaran keras tentang dunia kerja yang menuntut produktivitas tanpa peduli pada kesehatan mental, tentang keluarga yang hanya tahu menuntut tanpa mau mendengar, dan tentang sistem sosial yang menjadikan manusia sebagai angka dan pencapaian.
Seplia tidak berhenti pada menggambarkan luka. Ia membawa pembaca masuk ke proses penyembuhan yang tidak instan, yang penuh keraguan, kemarahan, dan kesedihan. Melati tidak serta-merta menemukan kedamaian karena hadirnya Michael, dan sebaliknya, Michael tidak serta-merta bahagia karena memahami Melati. Mereka saling mendampingi, saling membantu, dan kadang saling menyakiti. Karena begitulah hubungan antarmanusia: kompleks, tidak linear, dan penuh kejutan.
Dalam novel ini, Seplia juga menyajikan kritik sosial yang tajam namun tidak menggurui. Ia mengajak pembaca merenungkan bagaimana sistem kita hari ini menciptakan manusia-manusia yang lelah, terasing, dan penuh beban. Ia membuka mata kita bahwa kesuksesan sering kali dibangun di atas tumpukan kelelahan dan rasa kehilangan akan diri sendiri. Bahwa dalam mengejar "hidup ideal", banyak yang justru kehilangan kebahagiaan dan ketenangan.
Gaya penulisan Seplia patut diapresiasi. Ia tidak berusaha menjadi puitis berlebihan, namun kalimat-kalimatnya punya getaran yang dalam dan mengena. Ia tahu kapan harus menahan diri, kapan harus membiarkan pembaca tenggelam dalam renungan. Tidak ada bagian yang terasa dipaksakan; semuanya mengalir, seperti luka yang perlahan mengering, namun meninggalkan bekas yang tak mudah hilang.
Yang membuat novel ini sangat menarik adalah pengalamannya yang personal bagi setiap pembaca. Ini bukan hanya kisah Melati dan Michael, tapi bisa menjadi kisah siapa saja—tentang bagaimana kita mencoba bertahan di dunia yang kerap tidak ramah. Novel ini menjadi semacam cermin, yang merefleksikan luka-luka yang selama ini kita anggap biasa, tapi sebenarnya terus menyiksa.
Lika-Liku Luka tidak menawarkan akhir bahagia yang klise. Ia tidak menjanjikan bahwa semua akan baik-baik saja. Tapi ia memberi harapan, bahwa dalam luka, ada kekuatan. Dalam kerentanan, ada kejujuran. Dan dalam upaya pulih, ada nilai menjadi manusia yang utuh.
Membaca novel ini seperti berjalan dalam hujan tanpa payung, namun tahu bahwa kita tidak sendiri. Ada Melati, ada Michael, dan ada kita—yang terus berjuang, terus mencari arti hidup, di tengah luka yang tak kasat mata.
Akhirnya, Lika-Liku Luka bukan sekadar novel. Ia adalah teman, pengingat, dan pelipur lara. Ia mengajak kita berdamai dengan luka, dengan perjalanan hidup yang penuh liku, dan dengan kenyataan bahwa menjadi manusia adalah proses panjang untuk memahami bahwa luka adalah bagian dari kita—bukan untuk disembunyikan, tapi untuk dipeluk.