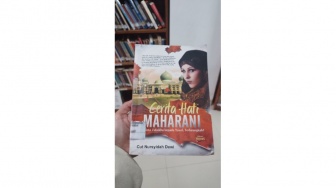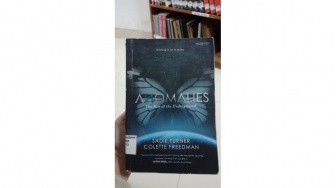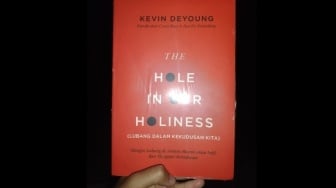Ada satu momen dalam hidup ketika kita merasa sedang jatuh cinta sepenuh-penuhnya. Rasanya nyata, berdebar, bahkan meyakinkan. Namun, bagaimana jika semua itu ternyata hanya ilusi? Bagaimana jika yang kita cintai bukan orangnya, melainkan bayangan yang kita ciptakan sendiri?
Lewat Perfect Illusion, Flara Deviana seperti sengaja melempar pertanyaan itu ke wajah pembaca secara pelan, tetapi menohok. Novel yang terbit pada 2019 ini memang dipasarkan sebagai romance. Namun, begitu masuk ke dalamnya, kita sadar bahwa ini bukan sekadar kisah dua orang yang saling jatuh cinta. Ini tentang persepsi, tentang luka, dan tentang bagaimana otak serta hati sering kali tidak berada di frekuensi yang sama. Percayalah, setelah menutup halaman terakhirnya, Anda mungkin akan terdiam sebentar.
Cinta yang Selalu Kalah atau Memang Tidak Pernah Ada?
Tokoh utama kita, Alby, bukan tipikal pria romantis yang percaya pada takdir. Justru sebaliknya. Ia tumbuh dengan pengalaman pahit: setiap kali ia menyukai seseorang, perempuan itu selalu berakhir bersama orang lain, bahkan kakaknya sendiri. Dari situ lahir keyakinan dalam dirinya bahwa cinta itu ilusi.
Bukan karena ia tidak pernah merasakan, tetapi justru karena ia terlalu sering merasakan dan selalu kalah. Ada pola yang berulang, dan pola itu membentuk cara berpikirnya. Secara psikologis, hal ini menarik. Seseorang yang berkali-kali mengalami kekecewaan cenderung membangun mekanisme pertahanan. Dalam kasus Alby, pertahanannya adalah sinisme. Ia lebih mudah menyebut cinta sebagai tipuan daripada mengakui bahwa ia takut terluka lagi. Lalu hadir Kania. Dan seperti kebanyakan cerita cinta, pertemuan ini mengubah segalanya. Atau setidaknya, tampak seperti itu.
Realitas yang Tidak Sepenuhnya Bisa Dipercaya
Salah satu kekuatan Perfect Illusion ada pada cara Flara Deviana memainkan sudut pandang. Pembaca tidak selalu diberi pijakan yang stabil. Ada bagian-bagian yang membuat kita bertanya: ini benar terjadi atau hanya interpretasi Alby? Di sinilah sisi psikologisnya terasa kuat.
Manusia sering kali hidup dalam narasi yang ia bangun sendiri. Kita menafsirkan sikap orang lain sesuai dengan pengalaman dan luka kita. Jika kita pernah dikhianati, kita cenderung curiga. Jika kita pernah ditinggalkan, kita cenderung takut ditinggalkan lagi. Alby adalah representasi dari itu. Ia tidak hanya melihat dunia apa adanya, melainkan melalui kacamata trauma kecil yang menumpuk. Tanpa sadar, pembaca ikut masuk ke dalam sudut pandangnya. Kita diajak memercayai apa yang ia yakini sampai pada suatu titik kita mulai meragukannya.
Tentang Luka yang Membentuk Cara Mencintai
Ada satu hal yang terasa cukup realistis dalam novel ini: luka tidak hilang hanya karena hadir orang baru. Kania mungkin berbeda. Kania mungkin tulus. Namun, hal itu tidak otomatis menyembuhkan pola pikir Alby. Dalam psikologi, ada yang disebut self-fulfilling prophecy, yaitu ketika seseorang begitu yakin akan satu hal negatif sampai tanpa sadar ia menciptakan kondisi yang membuat hal itu benar-benar terjadi.
Alby percaya cinta adalah ilusi. Maka, setiap tanda kecil yang mengarah pada kemungkinan kehilangan ia tangkap sebagai bukti bahwa ia benar. Bukankah dalam kehidupan nyata kita juga sering seperti itu? Kita berkata, "Aku pasti ditinggalkan," lalu bersikap defensif, dingin, atau posesif, dan akhirnya benar-benar ditinggalkan. Flara Deviana tidak menuliskan teori psikologi secara gamblang, tetapi lewat dinamika emosi Alby, pembaca bisa merasakannya.
Antara Cinta dan Proyeksi
Pertanyaan terbesar yang diam-diam menggantung sepanjang novel ini adalah: apakah Alby mencintai Kania, atau ia hanya mencintai versi ideal tentang Kania yang ia butuhkan? Ini bukan pertanyaan sederhana. Sering kali kita jatuh cinta bukan pada orangnya, melainkan pada rasa aman, validasi, atau harapan yang ia wakili. Ketika realitas tidak sesuai dengan ekspektasi, kita menyebutnya pengkhianatan, padahal mungkin sejak awal kita yang terlalu banyak berimajinasi.
Di titik ini, Perfect Illusion terasa seperti cermin. Ia tidak berteriak, tidak menggurui, tetapi perlahan memaksa kita melihat diri sendiri. Pernahkah Anda merasa sangat yakin seseorang adalah the one, padahal sebenarnya Anda hanya takut sendirian? Novel ini seperti mengajak pembaca untuk jujur menjawab hal tersebut.
Akhir yang Mengganggu dalam Arti Baik
Tanpa membocorkan detail, bagian akhir novel ini bukan tipe yang sepenuhnya nyaman. Ada rasa ganjil dan ada ruang kosong yang sengaja tidak diisi terlalu rapi. Mungkin itu memang maksudnya. Sebab, hidup pun tidak selalu memberi penutup yang bersih. Terkadang kita hanya diberi pemahaman bahwa tidak semua yang terasa nyata benar-benar nyata.
Tidak semua yang indah akan bertahan dan tidak semua rasa harus dimiliki. Flara Deviana cukup berani untuk tidak memanjakan pembaca dengan kepastian mutlak. Ia memilih meninggalkan sedikit kabut seolah ingin berkata, "Silakan Anda tafsirkan sendiri."
Layak Dibaca atau Tidak?
Jika Anda mencari romance ringan yang manis dan membuat tersenyum sendiri, mungkin novel ini akan terasa sedikit berat. Namun, jika Anda suka cerita cinta yang mengajak berpikir serta membuat Anda berhenti sejenak dan merenung, Perfect Illusion punya sesuatu untuk ditawarkan. Ia bukan hanya tentang dua orang yang bertemu. Ia tentang bagaimana pikiran kita bisa menciptakan kenyataan sendiri, tentang luka yang diam-diam mengatur arah hidup, dan tentang cinta yang terasa sempurna padahal mungkin hanya ilusi yang kita pertahankan mati-matian.
Setelah selesai membaca, mungkin Anda akan bertanya pada diri sendiri: selama ini, apa saja yang Anda yakini sebagai cinta dan berapa banyak di antaranya yang sebenarnya hanya perfect illusion?