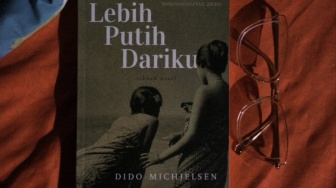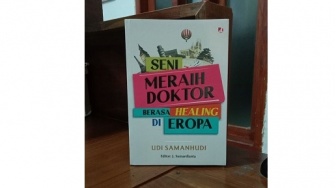Ada hal yang nggak pernah berhenti mengusik pikiran setiap kali nonton film tentang orang yang bermimpi besar, tapi harus berhadapan dengan dunia yang keras. Film In the Nguyen Kitchen jadi salah satu contohnya. Bukan hanya karena film ini punya musik yang indah atau warna-warna yang memanjakan mata, tapi karena mengajakku merenung lebih jauh tentang arti mimpi, perjuangan, dan bagaimana dunia seringkali nggak ngasih ruang untuk keduanya.
Kadang kita suka lupa, mimpi itu bukan soal seberapa tinggi atau seberapa spektakuler. Mimpi sering lahir dari hal yang sangat manusiawi, yakni keinginan untuk dilihat, didengar, dan dianggap berarti.
Namun, kenyataan pahitnya, dunia nggak selalu peduli. Dunia punya selera sendiri, punya kotak-kotak yang harus kita masuki, punya label yang dilekatkan bahkan sebelum kita sempat memperkenalkan diri. Dan di situlah seringkali mimpi berhenti jadi sesuatu yang membebaskan, berubah jadi beban.
Aku jadi teringat pada banyak orang yang mungkin nggak pernah benar-benar gagal karena kurang usaha, tapi terhalang bias dan prasangka. Ada yang dibilang, “Kamu kurang ini,” di satu sisi, “Kamu terlalu itu.” Seolah-olah nggak pernah ada ruang aman buat jadi diri sendiri. Film ini mengingatkanku, betapa kejamnya dunia yang sibuk mendikte, tapi jarang benar-benar mau mendengar.
Namun, di tengah halangan itu, ada hal kecil yang terasa begitu indah. Saat Yvonne dan ibunya memasak, ketika suara sendok dan wajan berubah jadi musik, aku merasa adegan itu lebih dari sekadar musikal. Itu gambaran dari kebebasan yang bisa lahir dari ruang sederhana, dari kehidupan sehari-hari, dari identitas yang nggak perlu dipoles untuk menyenangkan orang lain. Yang juga seolah-olah berkata, “Kamu nggak butuh panggung megah untuk menemukan suaramu. Kamu bisa memulainya dari rumah, dari cinta, dari dirimu sendiri.”
Dan bukankah itu juga yang sering kita alami? Banyak dari kita yang merasa dunia nggak memberi panggung, tapi tetap mencoba menciptakan ruang sendiri. Ada yang menulis, ada yang bernyanyi di kamar, ada yang masak sambil bersenandung. Bukan untuk didengar orang banyak, tapi untuk mengingatkan diri bahwa kita masih hidup, masih punya suara, masih punya mimpi.
Nah, ‘In the Nguyen Kitchen’ buatku akhirnya bukan lagi sebatas film musikal diaspora. Ini jadi semacam gambaran tentang betapa sulitnya menjadi diri sendiri di dunia yang sibuk menuntut. Tentang bagaimana cinta bisa hadir dalam bentuk yang keras, tapi tetap cinta yang ingin melindungi. Tentang bagaimana mimpi nggak harus sempurna, nggak harus sesuai standar industri, tapi cukup jadi milik kita yang paling jujur.
Aku merasa film ini menawarkan perayaan kecil untuk kita semua yang pernah dianggap ‘nggak cukup’. Perayaan bagi mereka yang suaranya pernah diabaikan, bagi mereka yang mimpinya dianggap nggak layak, dan buat mereka yang harus berkali-kali menabrak tembok sebelum menemukan celah. Film ini jelas mengingatkan, yang bikin mimpi berharga justru bukan karena mudah diraih, tapi karena diperjuangkan.
Akhir kata, ‘In the Nguyen Kitchen’ menyadarkan diriku. Dunia mungkin akan terus menutup telinga, tapi itu bukan alasan untuk berhenti bernyanyi. Dunia mungkin sibuk menempelkan label, tapi itu bukan alasan untuk berhenti jadi diri sendiri. Karena kemanusiaan kita ada di sana, dalam keberanian untuk bermimpi meski jalannya penuh liku, dalam kekuatan untuk bersuara meski panggungnya kecil, dan dalam keteguhan untuk tetap hidup sesuai irama kita sendiri.
Sobat Yoursay sudah nonton Film In the Nguyen Kitchen? Jika belum, kamu bisa tonton film gini di KlikFilm dalam rangkaian Jakarta World Cinema 2025 yang bisa ditonton online mulai 4 September - 4 Oktober. Selamat nonton, ya!