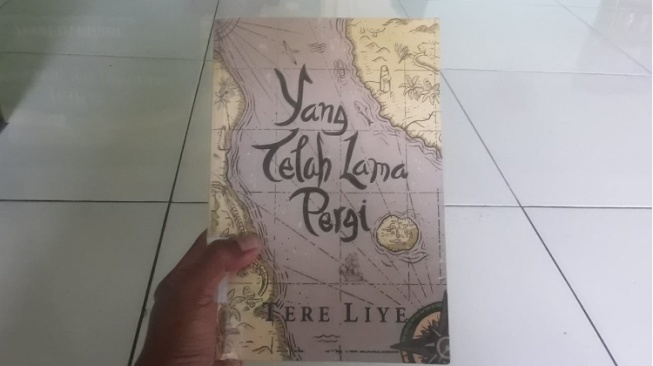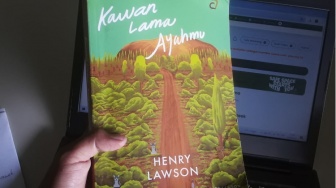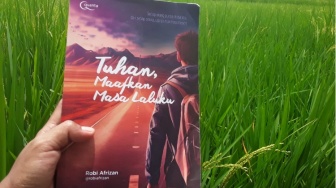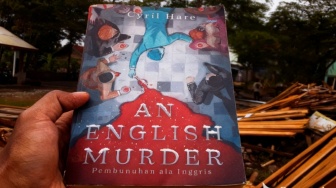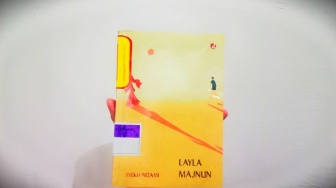Selama ini, melalui buku sejarah, kita mengenal bahwa runtuhnya Kerajaan Sriwijaya kerap dikaitkan dengan invasi maritim besar dari Chola. Namun melalui riset panjang dan pendekatan fiksi historis, Tere Liye menghadirkan kemungkinan lain melalui novel Yang Telah Lama Pergi: sejarah yang tidak tercatat tentang persatuan para perompak yang turut berperan dalam mengguncang Sriwijaya—berangkat dari sakit hati, dendam, dan pengkhianatan.
Kisah berpusat pada Mas’ud al-Baghdadi, kartografer terbaik dari Baghdad tahun 1200 M. Ia datang ke Selat Malaka demi menuntaskan wasiat ayahnya menyempurnakan peta Swarna Dwipa (Sumatra), meninggalkan kehidupan bangsawan dan istrinya yang tengah hamil enam bulan. Namun setibanya di Nusantara, ia justru ditangkap bajak laut dan hampir dihukum mati karena dituduh mata-mata kerajaan. Seorang biksu bijaksana menyelamatkannya dan membawanya menghadap Raja Perompak, Remasut.
Remasut bukan pemimpin bajak laut biasa. Ia menyatukan berbagai kelompok perompak dan mengubah budaya mereka—tidak lagi sekadar menjarah dan membunuh, melainkan membangun organisasi terstruktur dengan penasihat perang, biksu, koki, dan tenaga medis. Bahkan berdiri pulau terapung sepanjang empat kilometer dengan tiruan Bait al-Hikmah di dalamnya, simbol pengetahuan dan kemajuan teknologi pada zamannya.
Mas’ud kemudian menjadi otak strategi. Armada utara yang berjumlah seribu kapal ditaklukkan tanpa pertempuran terbuka, berkat infiltrasi dan penyusupan yang dirancang berbulan-bulan. Benteng Bukit Batu yang tak tertembus selama dua abad runtuh setelah Mas’ud menemukan patahan tanah sebagai titik lemah melalui ilmu geologi. Di Kepulauan Riau, armada timur dijebak di selat sempit dengan memanfaatkan arus dan badai yang telah ia perhitungkan. Ia dianggap dukun, padahal semua itu adalah ilmu membaca alam yang dipelajari di Baghdad.
Pada hari H, bertepatan dengan perayaan ulang tahun Paduka Srirama, ratusan kapal bajak laut berhasil memasuki jalur Sungai Musi dengan penyamaran rapi. Berkat kemampuan “Sang Seribu Wajah”, armada itu tampil seolah-olah sebagai iring-iringan utusan dari Jambi, Kuala Kedah, Palembang, hingga Sunda Kelapa—padahal wilayah-wilayah tersebut telah lebih dahulu ditaklukkan.
Meski menghadapi banyak rintangan, mereka akhirnya berhasil menembus istana, meruntuhkan pasukan kerajaan, para bangsawan yang tak bermoral, hingga sang raja. Sementara itu, rakyat biasa justru dihujani koin emas oleh para perompak—harta rampasan yang dikumpulkan bertahun-tahun sebagai imbalan atas kerasnya hidup mereka di bawah bayang-bayang kerajaan yang selama ini tampak jaya.
Namun inti novel ini bukan hanya perang. Tere Liye menyoroti tujuh tahun musim paceklik yang membuat rakyat Sriwijaya menderita, sementara istana tetap berpesta, menerima peti-peti emas upeti, dan membangun istana baru.
Sementara beras impor dari Champa dan India ditimbun dan dijual mahal. Bahkan ketika Paduka Sri Rama hendak melewati desa penduduk lagi lagi harus lulus tes kesehatan seharga sekeping perak. Rakyat pun tetap memuja-muja kedermawanan pejabat kerajaan dari sumbangan beberapa keping perak yang tidak imbang dengan besarnya upeti hasil panen. Para biksu pun menjadi perpanjang tangan dari kerajaan untuk menenagkan rakyat yang kelaparan.
Ketika sungai Musi dilanda banjir bandang yang mengakibatkan gagal panen, rakyat kecil yang disalahkan. Dalam laporan kerajaan tertulis pembukaan lahan baru oleh rakyat di sekitar hulu sungai. Padalah ini adalah kerjaan menteri yang meminta tambahan tanah konsesi untuk menanam segala jenis rempah seperti kayumanis, kapulaga, cengkih, dan pala yang snagat dimintai di Eropa untuk menambah pundi-pundi emas atas nama kerajaan.
Menariknya, Tere Liye bahkan menyelipkan detail kecil yang terasa satir: nama bangsawan korup “Luh-hut” disebut sebagai tokoh yang bertanggung jawab atas kebijakan pembukaan lahan yang memicu banjir bandang di Sungai Musi. Sentilan ini terasa jenaka sekaligus tajam—seolah menyiratkan bahwa praktik korupsi, nepotisme, dan kerakusan elite bukan hanya milik masa lampau, tetapi bisa saja berulang di masa depan.
Akhir cerita terasa memuaskan tanpa menggantung. Konflik disajikan seimbang antara kegagalan dan kemenangan, dengan plot twist yang masuk akal dan tidak dipaksakan. Pesan moralnya kuat: keruntuhan sebuah peradaban bukan hanya akibat serangan dari luar, melainkan karena keserakahan dan kebusukan dari dalam. Novel ini bukan sekadar kisah petualangan dan perang, tetapi juga cermin sosial yang relevan lintas zaman.
Identitas Buku
Judul: Yang Telah Lama Pergi
Penulis: Tere Liye
Penerbit: PT Sabak Grip Nusantara
Kota Terbit: Depok, Jawa Barat
ISBN: 978-623-88296-0-6