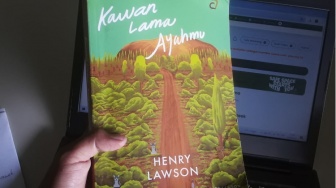Masjid itu tidak besar. Cat hijaunya sudah memudar, beberapa sudut tembok retak, dan kipas anginnya sering berbunyi aneh.
Tapi pintunya hampir tak pernah tertutup. Bahkan malam hari, ketika kampung sudah sunyi, lampunya tetap menyala—seperti sengaja ditinggal untuk siapa saja yang ingin pulang.
Aku pertama kali singgah di sana karena kelelahan.
Motor tuaku mogok di tengah perjalanan. Dompet tipis. Perut kosong sejak siang. Aku menuntun motor pelan-pelan sampai melihat kubah kecil di ujung jalan.
Masjid.
Aku ragu masuk. Bajuku kotor, wajahku kusut. Tapi pintunya terbuka lebar.
“Mas, masuk aja,” suara itu datang dari seorang bapak tua yang sedang menyapu halaman. “Musafir ya?”
Aku mengangguk.
“Silakan. Air ada di dalam. Kalau mau istirahat, tikarnya diambil aja.”
Tak ada pertanyaan lanjutan. Tak ada tatapan curiga. Aku masuk, duduk bersila, dan entah kenapa dada langsung terasa longgar. Seperti baru saja melepaskan beban yang terlalu lama dipikul.
Di luar, beberapa pedagang menggelar dagangan. Ada tukang kopi, penjual gorengan, dan ibu tua dengan termos besar.
“Minum dulu, Nak,” kata ibu itu sambil menuangkan teh hangat ke gelas plastik.
“Bayar nanti aja. Atau nggak usah.”
Aku tercekat. “Terima kasih, Bu.”
Menjelang magrib, masjid makin ramai. Anak-anak berlarian, bapak-bapak datang dengan sandal jepit, ibu-ibu duduk di serambi sambil membawa makanan dari rumah.
Seorang pemuda datang tergopoh. Wajahnya cemas.
“Pak, boleh numpang tidur?”
“Boleh,” jawab pengurus masjid tanpa ragu. “Mandi dulu sana.”
Tak ada yang bertanya latar belakang. Tak ada yang menilai penampilan. Semua diperlakukan sama: sebagai tamu.
Setelah salat, nasi dibagikan. Sederhana. Tapi hangat.
Aku duduk di samping seorang kakek.
“Masjid ini enak ya,” kataku.
Kakek itu tersenyum. “Iya. Di sini nggak ada yang disuruh jadi siapa-siapa. Cukup jadi manusia.”
Aku terdiam.
Aku pernah melihat masjid yang megah tapi terkunci rapat. Masjid yang lantangnya memaki, sibuk menghakimi, sibuk merasa paling benar. Tapi masjid ini tidak. Masjid ini lebih mirip rumah.
Malam itu hujan turun pelan. Seorang pengendara motor berhenti di depan masjid. Basah kuyup.
“Masuk, Pak,” kata seseorang dari dalam.
“Silakan. Minuman hangat dulu.”
Aku melihat wajah pengendara itu berubah. Lega. Seperti aku tadi sore.
Di sudut masjid, ada tulisan kecil di papan kayu:
"Masjid ini milik Allah. Semua yang datang adalah tamu-Nya."
Aku mengusap mata. Hangat. Perih.
Aku sadar, Islam yang aku rindukan ada di sini. Bukan yang berteriak-teriak. Tapi yang membuka pintu. Yang memberi makan tanpa bertanya. Yang menolong tanpa syarat.
Masjid ini tak pernah bertanya kamu siapa.
Masjid ini hanya bertanya:
“Kamu capek ya? Mari singgah.”
Dan entah kenapa, itu cukup untuk membuatku menangis pelan di sajadah lusuh—merasa akhirnya, aku pulang.