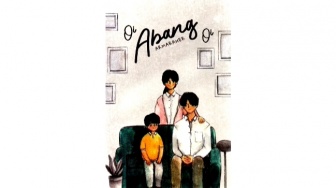Pagi di Pondok Pesantren Putri Misbahatul Huda selalu dimulai dengan suara ayat-ayat suci yang mengambang di udara seperti embun. Namun pagi itu, bagi Azkiya, suara itu terdengar berbeda—lebih berat, lebih berdebar, seolah setiap huruf yang meluncur dari bibir santri lain ikut mengetuk dadanya.
Hari ini tasmi.
Tiga juz Al-Qur'an yang ia rangkai pelan-pelan selama berbulan-bulan akan diuji. Bukan hanya hafalannya, tapi juga kesabarannya, imannya, dan harga dirinya.
Azkiya merapikan jilbab cokelat tua yang warnanya sudah pudar. Jilbab itu bukan merek apa-apa. Ia tahu. Ia selalu tahu.
“Bismillah,” bisiknya, seperti menenangkan dirinya sendiri.
Beberapa bulan lalu, ia hampir menyerah. Ia ingat betul suara-suara yang tak pernah diucapkan terang-terangan, tapi selalu berhasil menemukan jalannya ke telinga.
“Jilbabnya itu lagi.”
“Sandalnya kok gak ganti-ganti.”
“Ngapain sih, sok pinter kalau miskin?”
Pesantren—yang katanya lembaga beradab—ternyata juga menyimpan luka-luka kecil yang tak terlihat. Luka yang tak berdarah, tapi perihnya menetap.
Suatu sore, Azkiya pernah menulis di buku catatannya: Ya Allah, kalau aku miskin, apakah itu dosa?
Telepon dari wartel pesantren tiga hari lalu masih membekas di ingatannya. Saat itu, suara ayahnya, Pak Kurdi, terdengar patah-patah, bercampur desir angin sawah.
“Bapak sama Ibu bakal datang, Ki. InsyaAllah.”
Bu Lasmi bahkan tak sanggup bicara lama. Tangisnya terdengar seperti doa yang tumpah begitu saja.
Hari tasmi akhirnya tiba.
Sebuah mobil pick up tua berhenti di depan gerbang pesantren. Catnya mengelupas, baknya penuh manusia dengan senyum bahagia. Pak Kurdi meloncat turun lebih dulu, disusul Bu Lasmi dan saudara-saudara Azkiya.
Namun, bukan sambutan hangat yang mereka terima.
“Heh, itu keluarganya Azkiya?”
“Datangnya rame banget. Udik. Kampungan.”
“Kampungnya tuh ngampung banget.”
Tawa-tawa kecil beterbangan, ringan, tapi cukup tajam untuk menggores.
Azkiya berdiri kaku di kejauhan. Ia ingin berlari memeluk ibunya, tapi kakinya terasa berat. Seolah pesantren itu tiba-tiba menjadi ruangan sempit tanpa udara.
Tasmi berlangsung khidmat.
Saat Azkiya melafalkan ayat demi ayat, suaranya sempat bergetar, lalu menguat. Seperti orang yang hampir tenggelam, lalu menemukan pijakan.
Kyai Dadi menatapnya lama. “Azkiya bukan santri yang paling cepat,” ujar beliau akhirnya, “tapi dia santri yang tidak berhenti berjuang. Dan itu jauh lebih mulia.”
Tangis pecah.
Bu Lasmi menutup wajahnya dengan kerudung, bahunya berguncang. Pak Kurdi menunduk, air matanya jatuh satu-satu ke lantai pesantren.
Azkiya merasa dadanya hangat. Untuk sesaat, dunia terasa adil baginya.
Besek syukuran dibagikan setelahnya.
Isinya nasi kuning, bihun goreng, telur balado. Sederhana. Tapi setiap butir nasi adalah hasil keringat, setiap lauk adalah pengorbanan.
Namun tidak bagi semua orang. Julia dan gengnya berdiri di sudut.
“Ini doang makanannya?” Julia mendengus.
“Kirain minimal ayam crispy lah,” sahut temannya.
“Huwek, makanan hajatan kampung. Nggak selera gue.”
Azkiya menoleh. Ia melihat tangan-tangan itu—tangan yang bersih, kuku rapi—membuang nasi kuning ke tempat sampah. Utuh. Tak disentuh. Sama sekali.
Sesak. Dadanya runtuh.
Ia ingin berteriak, bahwa makanan itu adalah doa Ibunya. Makanan itu adalah hasil keringat Bapaknya. Tapi yang keluar hanya air mata.
Malam itu, Azkiya demam. Tubuhnya panas, jiwanya lebih panas lagi. Tangisnya pecah di bantal tipis, seperti anak kecil yang kehilangan rumah.
Kak Alila, pemimpin asrama putri, duduk di sampingnya.
“Ki, kamu tuh gak salah apa-apa, mereka aja yang keterlaluan.” ucapnya pelan.
Keesokan harinya, pesantren tidak diam. Nama-nama itu dipanggil. Julia dan teman-temannya berdiri tertunduk di hadapan Kyai Dadi.
“Di tempat ini,” kata beliau tegas, “iman tidak diukur dari merek. Dan makanan apapun tidak boleh dibuang ke tempat sampah.”
Hukuman dijatuhkan. Mereka harus membersihkan dapur dan tempat sampah selama sebulan. Dan satu hal yang paling berat—meminta maaf.
“Maaf, Ki,” ucap Julia lirih.
Azkiya mengangguk. Maaf itu tidak serta-merta menghapus luka, tapi cukup untuk membuatnya bernapas lagi.
Hari-hari berikutnya, Azkiya berubah. Ia tidak menjadi pendendam. Ia menjadi lebih tekun. Lebih kuat. ia belajar satu hal: luka tidak selalu harus disembuhkan—kadang cukup dijadikan pijakan.
Semester berikutnya, namanya disebut sebagai juara satu.
Azkiya menatap langit sore pesantren. Langit yang sama, tapi dirinya tidak lagi sama.
Dalam hatinya, ia berbisik, “Ya Allah, terima kasih untuk nasi kuning yang pernah terbuang. Dari sanalah aku belajar arti syukur, harga diri, dan bagaimana bangkit tanpa membenci.”
Azkiya berusaha memetik hikmah dari semuanya dan melanjutkan hidup.
Ternyata, kesenjangan sosial itu tidak hanya terjadi di sekolah-sekolah mewah. Bahkan di balik tembok pesantren, beberapa santri sibuk membandingkan merek jilbab, harga sarung atau model sandal. Padahal seharusnya para santri lebih menyibukkan diri dalam menuntut ilmu, bukan terpaku pada gaya hidup mewah, apalagi sampai melakukan perundungan terhadap kawan lain yang dianggap kurang mampu. Ya, tugas kita adalah jangan menjadi salah satu dari pelaku perundungan itu.