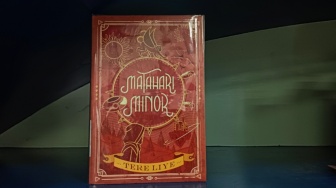Warung Kopi Demokrasi buka sejak subuh, tapi pengunjungnya paling ramai justru setelah pemilu. Di dindingnya tergantung spanduk kusam bertuliskan: “Ngopi Dulu, Berantem Belakangan.”
Tak ada yang benar-benar membaca spanduk itu, tapi semua sepakat duduk lama-lama.
Pagi itu, Pak Luber dan Mas Jurdil duduk satu meja. Keduanya sudah tua, tapi tetap rajin datang setiap lima tahun sekali.
“Aku capek, Mas,” kata Pak Luber sambil mengaduk kopi. “Setiap pemilu aku dipanggil-panggil, dielu-elukan. Begitu selesai, aku ditinggal.”
Mas Jurdil tertawa pendek. “Kita ini cuma dekorasi, Pak. Kayak bunga plastik di meja KPU.”
Di meja sebelah, Bang Bebas dan Mbak Jujur sedang berdebat kecil.
“Bebas itu artinya bebas milih tanpa tekanan,” kata Mbak Jujur sambil mengipas wajahnya dengan KTP.
“Iya bebas,” jawab Bang Bebas santai. “Bebas terima amplop, bebas pilih siapa aja.”
“Lho itu bukan bebas, Bang. Itu namanya kebablasan.”
“Ya sama aja, ujung-ujungnya coblos juga.”
Tawa pecah. Tidak ada yang merasa salah.
Datanglah Adil, paling pendiam di antara mereka. Ia duduk, memesan teh tawar.
“Kalian sadar nggak,” katanya pelan, “Setiap lima tahun kita ini diulang-ulang, tapi maknanya nggak pernah lulus ujian.”
Semua terdiam sebentar. Lalu Pak Luber berkata, “Lulus itu relatif, Dil. Yang penting sah.”
“Ya sah,” jawab Adil. “Kayak ijazah fotokopian, tetap bisa dipakai daftar.”
Tak lama kemudian, warga berdatangan. Ada yang pakai kaus partai, ada yang pakai kaus netral tapi hatinya condong. Ada pula yang masih marah meski pemilu sudah selesai berbulan-bulan lalu.
Seorang ibu menyela, “Pemilu kan udah kelar. Ngapain sih ribut terus?”
Seorang bapak menjawab cepat, “Ini bukan ribut, Bu. Ini prinsip.”
“Prinsip kok tiap hari update status?”
“Itu bagian dari perjuangan.”
Mas Jurdil menghela napas. “Perjuangan kok nggak capek-capek.”
Di sudut warung, seorang anak muda bermain ponsel sambil tertawa sendiri.
“Lucu ya,” katanya, “Kemarin katanya persatuan, hari ini saling unfollow.”
Pak Luber menepuk meja. “Nah itu! Demokrasi kita ini kayak mantan. Katanya move on, tapi masih stalking.”
Semua tertawa, kecuali satu orang yang tiba-tiba berdiri.
“Eh jangan sembarangan ngomong! Kamu pasti kubu sebelah!”
Warung hening.
Adil menoleh pelan. “Sebelah mana?”
“Pokoknya sebelah.”
“Sebelah kiri atau kanan?”
“Sebelah yang nggak sependapat sama saya.”
Mbak Jujur menggeleng. “Nah kan. Diskusi mati sebelum lahir.”
Di papan tulis warung tertulis menu hari ini:
- Kopi Hitam — pahit tapi jujur
- Teh Manis — manis tapi sering lupa gula
- Air Putih — netral tapi jarang dipesan
“Air putih satu,” kata Adil.
Pelayan mengernyit. “Serius, Mas?”
“Iya. Saya lagi belajar netral.”
Pelayan tertawa. “Netral sekarang mahal, Mas. Jarang yang mau.”
Menjelang siang, obrolan makin panas. Data dibantah dengan emosi, fakta dikalahkan asumsi.
“Pokoknya kalau kritik, pasti ada maunya!”
“Lha kalau nggak kritik, nanti dibilang penjilat.”
Pak Luber menutup wajahnya. “Dulu aku dibuat buat membebaskan rakyat. Sekarang rakyat malah saling mengurung.”
Mas Jurdil menambahkan, “Dulu aku soal kejujuran. Sekarang kejujuran kalah sama keberpihakan.”
Adil berdiri, menatap seisi warung.
“Pemilu itu cuma sehari,” katanya. “Tapi kita bawa emosinya bertahun-tahun. Padahal setelah presiden dilantik, game over. Yang ada cuma rakyat dan penguasa. Yang satu ngawasin, yang satu diawasi.”
Seorang bapak menyahut, “Tapi kalau kritik nanti dibilang nyebelin.”
“Lebih nyebelin mana,” jawab Adil, “Kritik atau hidup tanpa koreksi?”
Sunyi jatuh seperti ampas kopi.
Pak Luber tersenyum pahit. “Kalau kita cuma hidup di kertas, jangan heran kalau di lapangan kita mati.”
Mbak Jujur mengangguk. “Demokrasi tanpa kritik itu kayak kopi tanpa air. Katanya ada, tapi nggak bisa diminum.”
Warung Kopi Demokrasi tetap buka.
Setiap hari ada yang datang, berdebat, tertawa, marah, lalu pulang dengan keyakinannya masing-masing.
Sementara di sudut meja, Asas Luber Jurdil kembali duduk diam.
Menunggu lima tahun lagi untuk disebut-sebut,
lalu dilupakan lagi,
sambil berharap—
suatu hari, mereka bukan cuma dibaca,
tapi juga dipraktikkan.