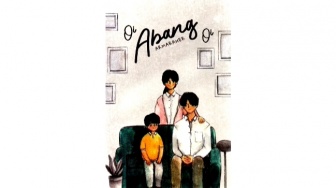Hujan baru saja berhenti. Halaman belakang rumah masih basah, tanahnya lembap, wangi lumpur bercampur daun busuk. Aroma khas setelah hujan yang entah kenapa selalu bikin orang merasa hidupnya sedikit lebih reflektif.
Aku lagi nyapu malas-malasan ketika mendadak melihat sesuatu berjalan di atas tanah. Kecil, lembek, dan berlendir.
“Eh… ini apaan sih?” Suara itu suara perempuan. Aku. Tapi versi yang sedikit panik dan sangat penasaran.
Aku jongkok. Di lantai semen yang masih basah, ada makhluk kecil, lembek, bergerak sangat pelan, meninggalkan jejak lendir mengilap seperti garis kehidupan yang terlalu jujur.
“Siput?” aku bertanya pada semesta.
Makhluk itu tidak menjawab. Dia lanjut jalan, santai, tanpa beban cicilan.
Mama keluar dari dapur sambil lap tangan. “Bukan siput.”
“Terus apa?” tanyaku penasaran.
“Itu slug.” jawab mama penuh keyakinan.
Aku mengernyit. “Slug?”
“Iya. Siput tanpa rumah.”
Aku terdiam.
Siput tanpa rumah.
Kalimat itu terasa terlalu filosofis untuk ukuran makhluk berlendir.
Aku jongkok lebih dekat. “Dia nggak punya cangkang sama sekali ya, Ma?”
“Iya. Makanya jangan dipegang.”
Aku refleks… memegang.
Mama langsung teriak. “EH!”
Aku membeku. Tanganku sudah menyentuh sesuatu yang dingin, lembek, dan… jujur saja, sangat tidak menyenangkan.
“Bahaya nggak sih, Ma?” tanyaku sambil masih memegang slug itu, seperti orang bertanya “ini aman nggak ya?” sambil berdiri di tepi jurang.
Mama menepuk jidat. “Makanya ditanya dulu sebelum dipegang.”
“Tapi aku kan penasaran.”
“Nah itu dia,” kata Mama. “Ini kenapa survival instinct perempuan suka jelek.”
Aku protes. “Eh! Jangan generalisasi.”
Mama menunjuk slug di tanganku. “Kamu tanya bahaya apa enggak, tapi tetap dipegang. Itu bukan penasaran, itu nekat.”
Aku menatap slug itu. Dia tetap pelan. Tenang. Tidak panik. Tidak peduli pada drama manusia di sekitarnya.
“Dia nggak gigit kan?” tanyaku.
“Enggak,” kata Mama. “Tapi lendirnya bisa bawa kuman atau parasit.”
Aku refleks menjauhkan tangan. “HAH?!”
“Makanya. Sekarang cuci tangan.”
Aku lari ke wastafel, gosok tangan kayak habis megang masa lalu yang toxic.
Sambil cuci tangan, aku masih mikir. “Ma, kasihan ya dia.”
“Siapa?”
“Itu slug.” tunjuk ku pada si hewan tanpa rumah itu.
Mama mengangkat alis. “Kasihan kenapa?”
“Dia homeless.”
Mama tertawa kecil. “Ya memang dia nggak punya rumah dari sananya.”
Aku menggeleng pelan. “Enggak, Ma. Aku curiga ini imbas dari tingginya biaya properti yang makin abnormal.”
Mama mendengus. “Mulai.”
“Iya coba pikir. Harga tanah naik, rumah makin nggak masuk akal, daya beli nggak ngikut. Akhirnya bahkan siput pun nggak sanggup punya rumah.”
Mama menaruh tangan di pinggang. “Siput itu dari lahir memang nggak punya cangkang.”
“Versi biologisnya iya,” kataku. “Tapi versi sosial-ekonomi? Dia korban sistem.”
Mama menahan tawa. “Kamu kebanyakan baca thread.”
Aku lanjut dengan serius yang tidak perlu. “Mungkin dia berprinsip anti-KPR.”
Mama menoleh. “Hah?”
“Pantang punya rumah dari kredit yang katanya riba,” jelasku. “Akhirnya milih hidup sederhana. Tanpa cicilan. Tanpa cangkang.”
Mama akhirnya ketawa. “Ya Allah.”
Aku menatap slug yang sekarang sudah dekat pot bunga.
“Lihat, Ma. Dia slow living. Jalan pelan. Nggak kejar-kejaran sama deadline. Nggak takut FOMO. Nggak punya rumah tapi juga nggak punya utang.”
Mama menyahut, “Tapi dia hama.”
Aku kaget. “Hah?”
“Iya,” kata Mama. “Slug itu musuh petani. Makan tanaman segar. Bahkan kalau slug dimakan ayam, ayamnya yang mati.”
Aku terdiam. “Oh.”
Berarti ini bukan sekadar korban sistem. Ini korban sistem… yang juga merugikan sistem.
Aku jongkok lagi, tapi kali ini jaga jarak. “Bahaya buat manusia nggak sih sebenernya?”
“Enggak,” jawab Mama. “Selama nggak kamu pegang sembarangan, terus cuci tangan.”
Aku mengangguk, sok paham. “Berarti bahayanya itu potensial. Kayak orang yang kelihatannya nggak jahat, tapi bikin hidup orang lain rusak pelan-pelan.”
Mama menatapku. “Obrolannya kok jadi berat.”
Aku nyengir. “Maaf. Salah topik.”
Slug itu terus bergerak, meninggalkan jejak lendir yang berkilau kena sisa cahaya sore. Jejaknya tipis, tapi nyata. Seperti keberadaannya yang sering dianggap sepele, tapi ada.
“Apa kita usir aja?” tanya Mama.
Aku menggeleng. “Kasihan. Dia lagi cari tempat lembap.”
Mama menghela napas. “Ya udah, biarin aja. Asal jangan masuk rumah.”
Aku berdiri. “Iya. Rumah kita kecil. Harga properti mahal. Kita juga harus selektif.”
Mama tertawa lagi. “Siput aja mikir begitu.”
Aku tersenyum sambil menatap slug itu untuk terakhir kali. Makhluk kecil tanpa rumah, tanpa cangkang, tanpa ambisi, tapi tetap hidup, tetap jalan, meski pelan.
Dan entah kenapa, di sore basah itu, aku merasa slug itu lebih siap menghadapi hidup dibanding manusia-manusia yang sibuk tanya “bahaya nggak?” sambil tetap nekat menyentuh apa yang seharusnya dijauhi.
Mantap.