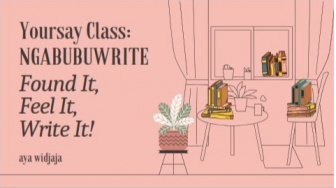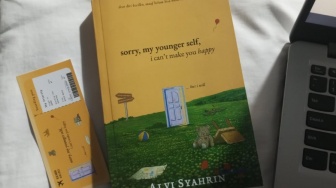Di pinggir kolam keruh yang tak pernah kering, hidup seekor katak kecil bernama Kiko. Tubuhnya hijau pudar, kakinya pendek, dan suaranya serak seperti daun kering bergesekan. Semua katak di kolam itu tahu satu aturan: lompat hanya sejauh yang kau lihat. Lebih dari itu, kau jatuh dan tenggelam.
Kiko tak pernah patuh. Setiap senja, ketika matahari tenggelam di balik bukit, ia duduk di batu tertinggi, menatap langit yang biru lalu jingga lalu hitam. “Suatu hari aku akan melompat sampai ke sana,” katanya pada dirinya sendiri.
Katak-katak lain tertawa. “Langit bukan tempat katak. Kau akan mati di udara sebelum menyentuh awan.”
Kiko diam. Tapi matanya tak pernah berhenti memandang ke atas.
Suatu musim kemarau panjang, kolam mulai menyusut. Air tinggal genangan kecil. Ikan-ikan mati. Rumput layu. Katak-katak mulai saling berebut tempat basah terakhir. Yang lemah dilempar keluar, dibiarkan mengering di lumpur retak.
Kiko melihat adiknya, Kiki, yang paling kecil, hampir tak bernapas. “Kita harus pergi,” bisik Kiki. “Ke tempat yang ada air.”
“Tapi ke mana?” tanya katak lain. “Di luar kolam hanya gurun.”
Kiko menatap bukit di seberang. Di puncaknya, kabut tipis selalu menggantung—tanda ada air. Tapi bukit itu tinggi. Jauh. Tak ada yang pernah mencoba melompat ke sana.
Malam itu, Kiko berkata pada semua katak, “Aku akan lompat ke bukit itu. Kalau aku sampai, aku kembali bawa kalian.”
Mereka menertawakan. “Kau gila. Lompatan terjauh kita cuma sepuluh batu. Bukit itu ratusan.”
Kiko tak menjawab. Ia hanya mulai melatih. Setiap pagi ia melompat dari batu ke batu, semakin jauh. Kakinya pegal. Kulitnya lecet. Tapi ia terus.
Hari ke-30, ia mencapai tepi kolam—batas yang tak pernah dilintasi siapa pun. Di depannya: tanah kering, batu tajam, angin panas. Di atasnya: langit tanpa akhir.
Kiko menarik napas dalam. Lalu melompat.
Satu lompatan. Dua. Sepuluh. Kakinya gemetar. Napasnya tersengal. Ia jatuh di tanah kering, berguling, tapi bangkit lagi. Melompat lagi.
Katak-katak di belakang menonton dari kejauhan. “Ia tak akan sampai,” kata yang tua. “Ia akan mati di tengah jalan.”
Tapi Kiko terus. Ia melompat melewati semak duri, melewati ular yang mengintai, melewati burung yang mengejek dari atas. Setiap kali ia hampir menyerah, ia ingat mata Kiki yang memudar.
Malam tiba. Kiko berhenti di lereng bukit. Tubuhnya penuh luka. Kakinya berdarah. Ia menatap puncak yang masih jauh. Air mata jatuh ke tanah kering.
“Aku tak bisa,” bisiknya.
Tapi angin malam membawa suara kecil dari kolam: “Kiko… tolong…”
Ia mengepal kaki belakangnya. “Satu lompat lagi,” katanya. “Hanya satu.”
Ia melompat.
Lompatan itu berbeda. Bukan karena lebih kuat, tapi karena ia tak lagi melompat untuk dirinya sendiri. Ia melompat untuk yang tertinggal.
Tubuhnya melayang lebih tinggi dari biasa. Angin mendorong. Bintang-bintang seolah mendekat. Untuk sesaat, ia merasa seperti terbang.
Ia mendarat di punggung bukit. Di depannya: mata air kecil, air jernih mengalir pelan. Kabut tipis membungkusnya seperti selimut.
Kiko menangis. Bukan karena lelah, tapi karena ia sampai.
Ia minum dulu, lalu mulai menggali daun-daun lebar untuk membawa air. Ia mengisi mulutnya penuh, lalu melompat kembali—turun bukit, lompat demi lompat, sampai ke kolam.
Ketika ia tiba, kolam sudah nyaris kering. Katak-katak lain terbaring lemah. Kiki hampir tak bergerak.
Kiko meludahkan air ke mulut adiknya. Lalu ke yang lain. Satu tetes demi satu tetes.
Mereka bangun perlahan. Mata mereka terbuka lebar. “Kau… sampai?” tanya yang tua, tak percaya.
Kiko mengangguk. “Bukit itu punya air. Banyak. Tapi kita harus lompat ke sana. Bersama.”
Mereka ragu. “Kita tak bisa. Kaki kita pendek.”
Kiko menatap mereka satu per satu. “Aku juga pendek. Aku juga takut. Tapi aku melompat karena kalian. Sekarang giliran kalian melompat karena yang lain.”
Malam itu, mereka mulai berlatih. Kiko mengajari cara melompat lebih jauh: tarik napas dalam, bayangkan tujuan, lepaskan rasa takut.
Hari berikutnya, satu per satu mereka melompat keluar kolam. Kiko di depan, memimpin. Yang lemah ditopang di punggung yang kuat. Mereka jatuh, bangkit, jatuh lagi, tapi terus maju.
Ketika matahari terbit di puncak bukit, ratusan katak kecil berdiri di tepi mata air. Mereka minum sampai kenyang. Mereka bernyanyi—suara serak tapi penuh sukacita.
Kiko duduk di batu tertinggi, menatap langit yang kini terasa lebih dekat.
Seekor katak muda mendekat. “Kau benar-benar melompati langit, ya?”
Kiko tersenyum tipis. “Bukan langit. Batas diriku. Dan ternyata, batas itu bisa dilompati kalau kau melompat untuk orang lain.”
Sejak hari itu, kolam tua ditinggalkan. Mereka hidup di bukit, dekat air abadi. Dan setiap senja, katak-katak muda duduk di batu, menatap langit, berbisik,
“Suatu hari aku akan melompat lebih tinggi lagi.”
Karena mereka tahu: langit tak pernah terlalu tinggi. Yang tinggi hanyalah ketakutan yang kita biarkan menetap di kaki kita.