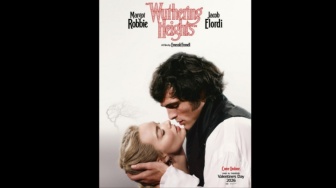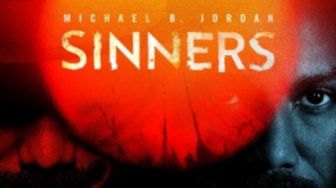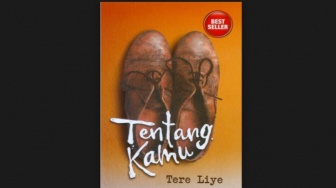"Abdullah, kau yakin ini jalan pintas ke stasiun?" tanya temannya, Riko, sambil menyeka keringat di keningnya di bawah terik matahari Jakarta siang itu.
Abdullah mengangguk, meski ragu.
"Iya, lewat gang ini lebih cepat. Aku pernah lewat dulu."
Mereka berdua berjalan menyusuri lorong sempit di antara gedung-gedung tinggi pusat kota. Suara klakson mobil dan hiruk-pikuk pedagang kaki lima terdengar samar dari jalan utama.
Abdullah, seorang pekerja kantor berusia 28 tahun, biasa melewati rute ini untuk menghindari kemacetan. Tapi hari ini, angin aneh berhembus, membawa bau tanah basah yang tak biasa di tengah beton kota.
Tiba-tiba, mereka berhenti di depan sebuah bangunan kecil yang tersembunyi di balik tembok retak. Itu musala tua, dindingnya berlumut, atapnya bocor, dan pintunya setengah terbuka. Papan nama Musala Al-Hikmah nyaris pudar. "Ini apa? Kayaknya sudah lama ditinggal," gumam Riko.
Abdullah merasa aneh. Dia ingat lokasi ini seharusnya kosong, hanya lahan parkir liar. "Aneh, aku nggak pernah lihat ini sebelumnya." Rasa penasaran mendorongnya mendekat. Riko menggeleng, "Ayo lanjut, telat nih." Tapi Abdullah sudah membuka pintu.
Di dalam, ruangan gelap dan berdebu. Sajadah usang tersebar di lantai, Al-Quran tua di rak kayu yang lapuk. Tak ada orang, tapi udara terasa berat, seperti ada bisikan tak terdengar. Abdullah menyalakan senter ponselnya. Cahaya menyapu dinding, dan dia melihat lukisan aneh: gambar kota modern tapi dengan masjid-masjid kuno bercampur di antaranya.
"Abdullah, keluar yuk!" seru Riko dari luar. Tapi Abdullah tak mendengar. Dia mendekati mihrab, dan tiba-tiba, lantai bergetar pelan. Sebuah suara samar bergema, seperti azan dari masa lalu. Abdullah mundur, tapi pintu musala tertutup sendiri dengan dentuman.
Kegelapan menyelimuti. Saat mata Abdullah menyesuaikan, ruangan berubah. Dinding menjadi bersih, sajadah baru, dan cahaya matahari masuk melalui jendela kaca patri. Dia berada di musala yang sama, tapi segalanya segar. Di luar jendela, bukan gedung pencakar langit, melainkan pasar tradisional dengan orang-orang berpakaian tempo dulu. Kuda dan gerobak lewat, suara pedagang menjajakan barang.
"Apa ini?" bisik Abdullah. Dia keluar, dan kota Jakarta yang dia kenal hilang. Ini seperti Jakarta tahun 1950-an, dengan bangunan kolonial dan orang-orang bersepeda ontel. Abdullah berjalan bingung, bertanya pada seorang pedagang, "Ini tahun berapa?"
Pedagang itu tertawa, "1955, Mas. Kenapa, baru bangun tidur?"
Abdullah pun panik. Musala itu portal waktu? Dia kembali ke musala, berharap bisa pulang. Di dalam, seorang kakek tua duduk sholat. "Siapa kau?" tanya Abdullah.
Kakek itu menoleh, matanya bijak. "Aku penjaga musala ini. Namaku juga Abdullah, seperti kau. Musala Al-Hikmah ini terbengkalai di masa depanmu, tapi di sini, ia hidup. Ia memilih orang untuk belajar dari masa lalu."
Abdullah duduk, mendengar cerita kakek. Musala dibangun tahun 1940-an oleh pejuang kemerdekaan. Ia menyaksikan perjuangan melawan penjajah, doa-doa untuk kemerdekaan. Tapi di masa depan, orang lupa, kota tumbuh tanpa ruh, musala ditinggal. "Kau dipilih karena hatimu masih ingat," kata kakek. "Lihat apa yang hilang."
Abdullah diajak keluar. Mereka berjalan di kota lama: anak-anak bermain, orang saling sapa, masjid ramai. Tak ada polusi, tak ada kesepian di tengah keramaian modern. "Di masamu, orang sholat di mall, tapi lupa makna," ujar kakek.
Malam tiba, Abdullah ikut sholat berjamaah. Rasa damai menyelimuti, sesuatu yang hilang di kehidupannya yang sibuk. Dia ingat rutinitasnya: bangun pagi, kerja lembur, pulang malam, tanpa waktu untuk refleksi. Di sini, waktu berhenti untuk doa.
Tapi tiba-tiba, gempa kecil mengguncang. Kakek berkata, "Waktumu habis. Kembalilah, dan jangan biarkan musala terbengkalai lagi."
Abdullah terbangun di musala yang gelap, pintu terbuka. Riko berdiri di luar, "Hei, kau lama banget! Cuma lima menit, tapi kayak hilang."
Abdullah keluar, melihat kota modern lagi. Tapi musala masih ada, terbengkalai. "Riko, kita harus perbaiki ini," katanya.
Mulai hari itu, Abdullah berubah. Dia mengajak teman-teman membersihkan musala. Mereka cat ulang dinding, ganti sajadah, dan buka untuk umum. Warga sekitar datang, anak-anak belajar mengaji, pekerja kantor istirahat sholat di sana.
Tapi rahasia musala tak berhenti. Kadang, saat sendirian, Abdullah mendengar bisikan masa lalu. Suatu malam, saat hujan deras, dia kembali ke musala. Pintu tertutup, dan dia terlempar ke masa depan: kota futuristik, gedung melayang, tapi musala tetap ada, kali ini megah, pusat komunitas.
Di sana, seorang wanita muda menyapa, "Kakek Abdullah? Kau kembali?"
Dia sadar, musala bukan hanya bangunan, tapi jembatan waktu. Ia menghubungkan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Orang-orang yang lupa akan akarnya akan terbengkalai, seperti musala itu.
Abdullah kembali ke masanya, lebih yakin. Dia jadi imam sukarela, cerita tentang sejarah musala pada jamaah. Kota tetap sibuk, tapi musala jadi oasis rohani.
Suatu hari, seorang anak bertanya, "Pak, kenapa musala ini spesial?"
Abdullah tersenyum, "Karena ia hidup, Nak. Ia ingatkan kita jangan terbengkalai seperti dirinya dulu."
Cerita musala itu pun menyebar, jadi legenda urban. Orang datang bukan hanya sholat, tapi mencari kedamaian. Abdullah, dari pekerja biasa, jadi penjaga waktu tak resmi.
Akhirnya, di usia tua, Abdullah duduk di mihrab. Musala ramai, tak lagi terbengkalai. Saat mata terpejam, dia mendengar suara kakek dari masa lalu: "Terima kasih, Abdullah. Kau selamatkan kami semua."
Dan musala itu tetap berdiri, unik di tengah kota, berbeda dari cerita manapun.