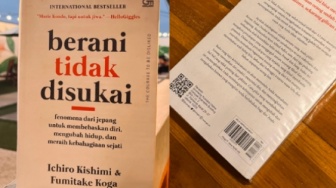Azan Asar menggema pelan dari surau kecil di ujung kampung. Suaranya terseret angin sore yang membawa aroma tanah basah dan debu jalanan. Ramadan telah memasuki hari ke-17, dan panas terasa lebih panjang dari biasanya. Bagi Ardi, anak laki-laki berusia dua belas tahun itu, sore selalu menjadi waktu paling berat: perut kosong, tenggorokan kering, dan kaki yang lelah setelah seharian membantu ibunya.
Ayah Ardi sudah lama sakit. Sejak setahun terakhir, ayahnya hanya bisa berbaring di kamar sempit mereka, menahan nyeri yang tidak sepenuhnya bisa dijelaskan dokter puskesmas. Ibunya, Bu Ratna, berjualan gorengan setiap sore untuk menyambung hidup. Ardi sering membantu mengantar pesanan, membeli minyak, atau sekadar menjaga adiknya.
Sosok Asing di Pinggir Trotoar
Sore itu, Ardi berjalan menyusuri jalan raya kecil yang membelah kampung. Di tangannya ada plastik berisi tempe, telur, dan tahu mentah titipan ibunya. Saat itulah, ia melihat seorang lelaki tua duduk di pinggir trotoar, tepat di bawah pohon ketapang yang daunnya mulai rontok. Bajunya kusam, wajahnya pucat, dan matanya terpejam seperti menahan sakit.
Ardi melambatkan langkah. Dalam hatinya muncul rasa ragu. Ia takut. Ibunya selalu berpesan agar berhati-hati dengan orang asing. Namun, entah mengapa, langkahnya berhenti tepat di depan lelaki itu.
"Pak, Bapak tidak apa-apa?" tanya Ardi pelan.
Lelaki itu membuka mata perlahan. Tatapannya sayu, tetapi hangat. "Tidak apa-apa, Nak. Hanya lelah saja."
Ardi melirik jam dinding di toko sebelah. Masih lima menit lagi menuju magrib. Ia sendiri hampir tidak kuat menahan haus. Namun, melihat tangan lelaki itu yang gemetar, Ardi merasa sesuatu menggerakkan dadanya.
Seteguk Air dan Ketulusan Hati
"Bapak puasa?" tanya Ardi lagi.
Lelaki itu tersenyum tipis. "Iya, puasa, Nak. Aku sedang dalam perjalanan jauh. Namun, tubuh ini tidak sekuat dahulu sehingga terpaksa beristirahat di sini."
Ardi menelan ludah. Ia teringat botol air kecil yang terselip di tasnya. Air itu sebenarnya ia simpan untuk berjaga-jaga jika adik kecilnya rewel. Memberikannya berarti ia dan adiknya tidak punya cadangan. Ia terdiam beberapa detik. Lalu, tanpa banyak berpikir lagi, Ardi membuka tasnya. Tepat di saat azan Magrib berkumandang merdu menandakan waktu berbuka.
"Ini, Pak. Airnya sedikit. Boleh untuk membasahi mulut," katanya sambil menyerahkan botol itu.
Lelaki itu terkejut. "Nak, bukankah kamu juga puasa?"
Ardi mengangguk. "Iya, Pak. Tetapi Bapak kelihatan lebih membutuhkan."
Lelaki itu menerima botol dengan tangan gemetar. Ia tidak langsung minum, hanya menempelkan botol ke keningnya, lalu meneguk sedikit, sangat sedikit. Setelah itu, ia menutup kembali botol tersebut dan mengembalikannya kepada Ardi.
"Terima kasih," katanya lirih. "Kebaikanmu tidak akan hilang."
Keajaiban yang Menghampiri Rumah
Ardi tersenyum canggung. Ia tidak mengharapkan apa pun. Ia hanya merasa lega melihat warna wajah lelaki itu sedikit membaik. Tak lama kemudian, lelaki itu berdiri perlahan. Sebelum pergi, ia menatap Ardi lama-lama seolah ingin menghafal wajahnya.
"Aku tidak punya apa-apa untuk kuberikan," katanya. "Tetapi izinkan aku mendoakanmu."
Di tengah bising kendaraan dan terik senja Ramadan, lelaki itu menengadahkan tangan. Doanya pelan, namun penuh ketulusan. Ia mendoakan agar keluarga Ardi diberi kekuatan, rezeki yang tidak disangka, dan kesembuhan bagi orang yang sedang diuji sakit. Ardi mendengarkan tanpa benar-benar memahami mengapa matanya terasa panas hingga meneteskan air mata. Setelah doa itu selesai, lelaki tersebut pergi menyusuri jalan dan menghilang di tikungan.
Malam itu, Ardi berbuka puasa dengan menu sederhana: nasi, gorengan sisa jualan, dan segelas teh hangat. Ayahnya batuk lebih sering dari biasanya. Ibu Ardi terlihat cemas.
"Besok kita ke puskesmas lagi saja ya, Pak," kata ibunya pelan. "Entah bagaimana biayanya, nanti Ibu yang cari dari hasil jualan."
Ardi hanya mengangguk. Ia teringat doa lelaki asing itu, lalu menepis pikiran tersebut karena tidak ingin berharap terlalu tinggi. Namun, keajaiban Ramadan sering datang dengan cara yang tidak terduga. Dua hari kemudian, seorang pria datang ke rumah mereka. Ia berpakaian rapi dan membawa map cokelat. Ia memperkenalkan diri sebagai relawan dari sebuah yayasan kesehatan.
"Kami mendapat laporan tentang Pak Hasan," katanya menyebut nama ayah Ardi. "Ada donatur yang ingin membantu biaya pengobatan lanjutan Bapak."
Ibu Ardi terdiam. Tangannya gemetar. "Donatur? Tetapi kami tidak pernah mendaftar ke mana pun."
Pria itu tersenyum. "Seseorang merekomendasikan. Ia tidak ingin disebutkan namanya. Katanya, ia hanya meneruskan kebaikan dan sering melihat bapak sakit."
Ardi terpaku. Dalam benaknya, terlintas wajah lelaki tua di bawah pohon ketapang.
Hikmah Memberi di Bulan Suci
Hari-hari berikutnya berubah perlahan. Ayah Ardi mendapatkan perawatan yang lebih baik. Ibunya tidak lagi menangis diam-diam di dapur setiap malam. Senyum mulai sering muncul di rumah kecil itu meskipun hidup mereka masih sederhana.
Pada malam ke-27 Ramadan, Ardi duduk di teras rumah setelah tarawih. Langit gelap, tetapi penuh bintang. Ia menengadahkan tangan, meniru gerakan lelaki asing itu. Dalam doanya, Ardi menyadari sesuatu yang sederhana namun dalam: kebaikan tidak selalu datang dari orang yang kita kenal, dan kebaikan yang kita lakukan tidak selalu kembali dalam bentuk yang sama.
Ramadan mengajarkannya satu hal penting bahwa memberi, bahkan saat kita sendiri kekurangan, adalah bentuk iman yang paling sunyi dan paling jujur. Dan di antara jutaan doa yang terbang di bulan suci itu, ada satu doa dari orang asing yang menemukan jalannya tepat ke rumah kecil di ujung kampung.