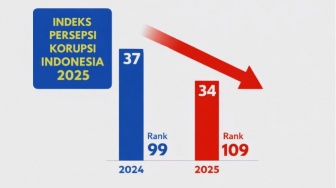Pendidikan menjadi salah satu aspek terpenting yang kerap dijadikan parameter keberhasilan banyak bidang. Krisis moral, pendidikan yang disalahkan. Ketertinggalan dalam teknologi, pendidikan yang disalahkan. Bahkan, sampai dengan kasus sepele seperti guru yang memotong rambut siswa, lagi-lagi pendidikan yang dijadikan kambing hitam.
Memang begitulah realitanya. Walau sebenarnya pendidikan tak bisa mutlak disalahkan, hal itu tak menutup fakta bahwa pendidikan kita memang punya segudang masalah rumit.
Masalah terbesar yang dimiliki oleh dunia pendidikan kita adalah masa jabatan menterinya yang hanya 5 tahun. Durasi ini terbilang sedikit bila kita mengharapkan perubahan pada pendidikan. Dan, umumnya setelah 5 tahun menjabat, kursi menteri akan diisi oleh orang-orang berbeda. Begitu pula dengan tim di baliknya. Imbasnya adalah perubahan kurikulum sering tak terhindarkan.
Pihak yang jadi korban dari semua itu tentu saja adalah guru dan murid. Dalam konteks ini, sektor pendidikan tak dapat disamakan dengan sektor lainnya. Mari kita ambil contoh, kemarin terkuak bahwa ada mafia minyak goreng dalam kementerian perdagangan. Hal itu seketika berbuah digantikannya M. Lutfi oleh Zulkifli Hasan sebagai menteri perdagangan. Kita bisa bayangkan, seandainya hal yang sama terjadi dalam kementerian pendidikan, kita mungkin akan dihadapkan dengan problematika yang jauh lebih kompleks.
Masalah berikutnya yang dihadapi oleh pendidikan adalah orang-orang di DPR. Kadang memang yang terjadi begini, kebijakan dari menteri pendidikan sudah bagus, tapi sayang DPR malah tidak menyetujuinya. Mengapa bisa begitu? Ya..... karena orang-orang di DPR itu bekerja untuk partai. Sebagus apa pun sebuah kebijakan untuk rakyat, bila itu tidak memberi keuntungan pada partai, DPR tidak mungkin menyetujuinya.
Tapi tenang, hal semacam ini hanya terjadi di negeri antah-berantah. Mustahil terjadi di negeri kita tercinta. Pasalnya, orang-orang yang menduduki kursi DPR di negara kita itu semuanya baik-baik. Bahkan, saking baiknya mereka, Gus Dur sampai menyamakannya dengan Taman Kanak-kanak.
Apakah problematika yang dihadapi pendidikan berhenti di situ? Jelas tidak. Mari kita menukik ke bawah lagi. Sekolah kita nyatanya juga tak lepas dari perpolitikan. Perekrutan guru dengan mengedepankan kualitas adalah sebuah prinsip. Namun, ketika ada calon guru yang memiliki hubungan kekerabatan dengan para pejabat sekolah (walau dia memiliki kualitas di bawah rata-rata), prinsip tadi untuk sementara akan dipinggirkan. Padahal, tujuan orang tua menyekolahkan anak itu supaya si anak mendapat peningkatan kualitas pemikiran atau kemampuan.
Semua itu bisa diperoleh asalkan guru yang mengajari mempunyai kompetensi yang bagus pula. Masalahnya, realita memang tak pernah seindah itu. Alih-alih mendapati guru yang berkualitas, siswa justru bertemu dengan guru yang kerap mengedepankan kedekatannya dengan pejabat sekolah. Pertanyaannya sekarang, apakah menjadi guru yang berkualitas hari ini adalah perkara yang sia-sia?
Hal yang serupa juga terjadi dalam seleksi murid. Persaingan untuk bisa menjadi murid di sekolah favorit (atau sekolah dengan akreditasi bagus) itu bukan perkara main-main. Namun, ini berlaku bagi mereka yang lewat jalur biasa. Bagi mereka yang melangkah di jalur “tidak biasa”, tentu tidak akan berlaku hal yang sama.
Dalam konteks ini, selain hubungan kekerabatan, ada pula hubungan bisnis. Ya, bisnis. Wali murid membeli kursi untuk anaknya kepada pejabat sekolah. Ini merupakan hal yang lumrah, bahkan seolah menjadi tradisi tahunan. Akibat hal ini, kadang ada murid yang harus menelan air mata lantaran sengaja “tidak diluluskan” dalam seleksi murid baru. Lantas, apakah (oknum) pejabat sekolah akan peduli dengan air mata siswa tersebut? Tentu saja, tidak. Dia (atau mereka) sudah tidur lelap bersama isi kantongnya yang baru saja menebal.
Tak berhenti di situ. Sekolah juga kerap menjadi lahan subur bagi diskriminasi. Seorang murid dengan orang tua terpandang akan mendapat perhatian lebih daripada murid lain dengan orang tua biasa. Kalau pun dia (murid dengan orang tua terpandang) membuat masalah, mungkin dia tidak akan mendapat ancaman dikeluarkan dari sekolah.
Lain cerita bila si pembuat masalah adalah murid dengan orang tua biasa. Ketidakadilan ini tampaknya memiliki umur yang cukup panjang. Ini dikarenakan saat ada murid yang mau speak up tentang kasus tersebut, kemungkinan besar tak ada guru yang menghiraukannya. Jika pun ada, itu hanya satu-dua orang. Melawan seakan tak ada gunanya. Sikap diskriminasi itu rasanya telah melekat kuat pada banyak (oknum) guru.
Apabila itu yang terjadi dalam hubungan antara guru dan murid, lalu bagaimana dengan hubungan antarsesama murid?. Dalam ranah ini kita kerap mendengar istilah bullying (perundungan). Sayangnya, alih-alih memberi perlindungan/pembelaan, banyak pihak justru menormalisasi bullying. Akibatnya apa? Pelaku bullying semakin merajalela, sementara korban jatuh dalam trauma.
Tak jarang pula bullying justru berujung dengan korban yang enggan bersekolah, bukan pelaku yang dikeluarkan oleh sekolah. Ironis sekali! Sekolah yang mestinya menjadi tempat belajar yang menyenangkan, justru berubah menjadi tempat yang menakutkan. Siapa yang patut disalahkan atas hal ini? Guru? Murid yang menjadi pelaku bullying? Atau malah sekolah itu sendiri?
Masalah yang diderita oleh pendidikan kita nyatanya bukan hanya pada sistemnya. Kita harus membuka mata, sehingga kita melihat bahwa problematikanya jauh lebih kompleks dari sekadar “sistem”.
Memperbaiki sistem pendidikan yang acak-acakan adalah sebuah keharusan. Namun, bukan berarti di sini kita bisa berpaling dari masalah lainnya. Pendidikan digadang-gadang sebagai basis kemajuan peradaban. Saya sangat setuju dengan hal itu.
Nah, pertanyannya sekarang adalah, “Bisakah kemajuan tersebut kita raih jika orang-orang yang “berpendidikan” tidak memiliki integritas dan moralitas?”. Sekolah yang harusnya jadi tempat untuk mencetak orang-orang hebat, malah menjadi sarang dari praktik suap dan penindasan.
Lantas, apa yang sekarang kita harapkan? Keadilan? Hanya diperuntukkan bagi mereka yang memiliki banyak uang. Kejujuran? Di mana-mana ia justru dijadikan topeng, sehingga si pemakai bisa melakukan pemerasan secara halus. Lagi dan lagi, siapa yang mesti disalahkan atas semua perkara ini? Apakah sekolah? Bukankah ia sekadar sebuah tempat atau bangunan?