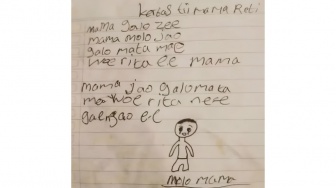Nama Imam Al-Ghazali sudah tak asing lagi di telinga. Banyak literature menyebut bahwa Imam Al-Ghazali merupakan sosok yang menguasai beragam ilmu (keagamaan). Tak heran jika ia mendapat julukan Hujjah Al-Islam. Salah satu quote yang paling saya suka dari al-Ghazali adalah tentang menulis yang kurang lebih begini, “Jika engkau bukan putra raja atau ulama besar, maka menulislah!”.
Apabila kita membaca riwayat hidup Al-Ghazali, rasanya quote tersebut memang didasarkan atas apa yang telah ia lalui. Imam Al-Ghazali bukan merupakan putra raja, bukan pula putra ulama besar. Namanya dapat dikenal oleh seluruh duniasalah satunyalantaran karya-karya yang telah ia tulis.
Imam Al-Ghazali lahir pada tahun 450 H (1058 M) di kota Tus, Iran. Melihat kota lahir Al-Ghazali tersebut, kita pun mafhum bahwa pembesar Islam tak selamanya berasal dari Arab Saudi. Ini selaras dengan apa yang pernah dipaparkan oleh Gus Baha’ yang mengutip pernyataan almarhum KH. Maimoen Zubair, kurang lebih seperti ini, “Allah itu harus memberi jatah orang sholeh dari Indonesia”.
Mengapa demikian? Tentu sisi kemaslahatannya lebih besar. Contoh sederhana, yang lebih memahami kondisi, sejarah, juga budaya Indonesia adalah orang Indonesia sendiri. Oleh sebab itu, fatwa dari orang sholeh Indonesia tentu lebih cocok bagi masyarakat kita ketimbang fatwa dari orang sholeh di negara lain.
Kembali ke Imam Al-Ghazali. Tak banyak privilege yang didapat oleh Al-Ghazali ketika dirinya kecil. Sang ayah bekerja sebagai pengrajin kain shuf (kain yang terbuat dari kulit domba). Di masa hidupnya, Al-Ghazali menyebut bahwa sang ayah selalu menghindari perkara syubhat. Sang ayah hanya akan makan dari hasil pekerjaannya sendiri. Sifat sholeh sang ayah tersebut lantas melekat juga pada Al-Ghazali.
Imam Al-Ghazali memulai perjalanan intelektualnya dengan belajar fiqh, khususnya fiqh Syafi’iyyah. Cabang ilmu lain yang juga dipelajari oleh Imam al-Ghazali di antaranya ushul fiqh, manthiq, dan filsafat. Pada tahun 484 H, saat usia Al-Ghazali kira-kira 30 tahunan, ia diangkat sebagai pengajar di Madrasah al-Nidzamiyyah yang berada di Baghdad.
Selepas 4 tahun mengajar di Madrasah al-Nidzamiyyah, Imam Al-Ghazali lantas menunaikan haji pada tahun 488 H. Sebelum berangkat, Imam al-Ghazali menunjuk Ahmad (yang merupakan saudaranya) untuk menggantikannya sebagai pengajar. Alih-alih kembali ke Baghdad seusai haji, Imam al-Ghazali lebih memilih menetap di Syam dalam jangka waktu yang cukup lama, kira-kira 10 tahun. Ibn Asakir menuturkan bahwa saat di Syam, Imam al-Ghazali tinggal di menara barat masjid Jami’ al-Umawi (sekarang berganti nama menjadi al-Ghazaliyyah).
Beberapa aktivitas yang ditekuni oleh Imam al-Ghazali selama di Syam yakni menyimak kajian kitab Shahih al-Bukhari dari Abu Sahl Muhammad ibn Ubaidillah al-Hafshi dan banyak menulis kitab. Salah satu kitab monumentalnya, yakni Ihya’ Ulumuddin, di tulis di sana.
Sebelum pulang ke tanah kelahirannya, Imam al-Ghazali sempat diminta untuk menjadi pengajar di Naisabur oleh Wazir Fakhr al-Mulk (yang kala itu merupakan penguasa Khurasan). Setelah beberapa tahun, Imam Al-Ghazali pun pulang ke Tus. Saat di tanah kelahirannya kali ini, Imam al-Ghazali mendirikan sebuah madrasah di dekat rumahnya dan membangun asrama sebagai tempat tinggal kaum sufi. Ahmad (saudara Imam al-Ghazali) bercerita bahwa sesaat sebelum meninggal, Imam al-Ghazali meminta untuk mengambilkan kain kafan miliknya. Beliau lantas mencium kain kafan tersebut lalu meletakkannya di kedua mata dan berkata, “Saya patuh dan taat untuk menemui Malaikat Maut”. Selepas itu beliau meluruskan kaki dan menghadap kiblat. Imam Al-Ghazali meninggal menjelang pagi hari pada Senin (14 Jumad al-Akhir 505 H/1111 M) di Tus.
Seperti yang diketahui, Imam Al-Ghazali menekuni banyak bidang keilmuan (agama) hingga mengantarkannya mendapat julukan 'hujjah al-islam'. Jumhur ulama pun sepakat akan fakta tersebut. Namun, ternyata ada beberapa orang yang merasa skeptis akan kapasitas intelektual Imam al-Ghazali. Bahkan, tak sedikit dari mereka yang mengklaim bahwa Imam al-Ghazali adalah penyebab kejumudan berpikir umat Islam.
Dalam pandangan mereka, Imam al-Ghazali telah membunuh nalar kritis umat Islam. Inilah yang menyebabkan umat Islam di masa kini selalu berada dalam ketertinggalan. Agaknya saya kurang setuju dengan pendapat termaktub. Sependek analisis saya, tampaknya tuduhan yang dilayangkan pada Imam Al-Ghazali berangkat dari dua hal berikut ini.
Pertama, kitab Tahafut al-Falasifah. Banyak yang berprasangka bahwa kitab tersebut merupakan wujud penolakan Imam al-Ghazali terhadap filsafat. Bahkan, mungkin ada yang mengklaim bahwa Imam al-Ghazali telah mengharamkan filsafat lantaran kitab tersebut. Benarkah demikian? Oke, mari kita bedah pelan-pelan.
Jika kita melihat judulnya, kita akan tahu bahwa kitab Tahafut al-Falasifah bukan merupakan bentuk penolakan Imam Al-Ghazali terhadap filsafat. Sebab, bila diterjemahkan, judul kitab tersebut akan menjadi “Kerancuan Para Filsuf”, bukan menjadi “Kerancuan Filsafat”. Nggak percaya? Silakan cari sendiri di Google apa terjemah dari Tahafut al-Falasifah. Saya yakin mayoritas serentak menyebut terjemahnya dengan “Kerancuan Para Filsuf”.
Melansir dari laman pku.unida.gontor.ac.id, kitab Tahafut al-Falasifah berisi sanggahan Imam al-Ghazali terhadap proposisi-proposisi para filsuf yang dipandang bermasalah. Satu di antara proposisi-proposisi tersebut misalnya, “Alam semesta bersifat kekal”. Kala itu Imam al-Ghazali melihat bahwa terdapat orang-orang yang merasa dirinya terhormat. Hal itu lantas membuat mereka mengesampingkan agama dan menggantinya dengan pengetahuan-pengetahuan (yang bersifat) prasangka.
Seluruh kerunyaman tersebut kian bertambah saat istilah-istilah milik Aristoteles dan Plato diterjemahkan dalam bahasa Arab secara tidak tepat. Kitab Tahafut al-Falasifah di kemudian hari mendapatkan respons dari Ibn Rusyd yang menulis kitab Tahafut al-Tahafut (kerancuan kitab Tahafut).
Kedua, kitab Ihya’ Ulumuddin. Beberapa pihak menyebut bahwa masterpiece Imam al-Ghazali tersebut mengajarkan fatalisme. Namun, bila ditelaah, garis besar kitab Ihya’ Ulumuddin sebenarnya tentang bagaimana mendekatkan diri kepada Allah swt.
Dalam lingkup pesantren, kitab ini diperuntukkan bagi mereka yang duduk di bangku kelas atas. Maksudnya, mereka yang usianya masih setara siswa SD/SMP/SMA belum akan diberi pelajaran kitab Ihya’ Ulumuddin. Ini seolah menjadi indikasi bahwa sebelum mempelajari kitab termaktub, seseorang harus memiliki fondasi berpikir yang matang terlebih dahulu.
Tujuannya adalah supaya ia dapat menangkap maksud yang sebenarnya dari apa yang tertera dalam kitab Ihya’ Ulumuddin. Saya rasa, mereka yang mengklaim kitab Ihya’ Ulumuddin mengajarkan fatalisme adalah orang-orang yang sekadar membacanya secara tekstual dan menafikan sisi kontekstual. Wallahu A‘lam.