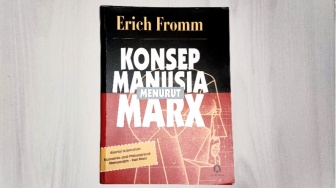Belakangan ini perbincangan konsumsi barang bekas impor sedang merajalela. Hal ini dipicu oleh wacana elit pemerintah kita yang secara tiba-tiba melarang konsumsi produk tersebut. Padahal, barang bekas semacam ini sudah menjadi konsumsi masyarakat Indonesi sejak abad 20.
Dalih pelarangan ini tidak lain karena dapat menurunkan roda ekonomi lokal di negeri kita. Rumus sederhananya, ketika masyarakat lebih memilih produk impor, entah itu legal ataupun tidak, secara otomatis akan menurunkan pasar produk lokal. Ketika permintaan produk lokal menurun, ekonomi dalam negeri akan terhenti, produksi barang berkurang, bahkan lebih ektremnya, banyak tenaga produksi yang harus dirumahkan.
Terlepas dari itu, konsumsi barang bekas atau istilah populernya “thrifting” ini sudah merajalela semenjak produk ini memasuki pasar digital, pemasaran melalui media sosial, dan menyasar kalangan pemuda. Adapun kalangan yang kerap menjadi 'pasar' pakaian bekas adalah anak-anak muda.
Namun, di tengah merajalelanya thrifting di kalangan anak muda hari ini, tidak lebih hanyalah sebuah pemujaan berlebih pada simbol merk pakaian dan sebuah kesadaran palsu dalam simulasi tentang realitas sosial yang mereka alami.
Sebelas dua belas tidak jauh berbeda dengan kita ketika menonton iklan air mineral yang mengatakan airnya ada manis-manisnya, dan kemudian kita membeli merk air mineral tersebut di minimarket terdekat karena kita percaya air itu rasanya manis. Padahal, kenyataannya air tetaplah air, yang tawar dan hambar.
Mengapa saya mengatakan bahwa perilaku konsumsi thrifting ini sebagai pemujaan simbol dan kesadaran semu atas realitas? Sebenarnya saya meminjam pemikirannya dari seorang sosiolog ulung kontemporer asal Perancis, yakni Jean Baudrillard.
Bagi Baudrillard, masyarakat hari ini (yang disebutnya sebagai masyarakat post-modern) itu berprilaku konsumtif bukan karena nilai gunanya, melainkan karena nilai simbolnya yang disebarkan melalui media iklan. Penyembahan pada simbol, atau yang disebut Baudrillard sebagai manipulasi tanda adalah tipikal paling kentara pada masyarakat konsumtif hari ini.
Begitulah yang terjadi pada prilaku konsumsi thrifting. Para pelaku usaha, atau bisa juga disebut sebagai para kapital thrifting hari ini tidak secara sembrono menjual pakaian bekas tanpa menyortirnya terlebih dahulu. Mereka hanya akan menjual pakaian bekas yang bermerk terkenal saja, yang hanya berlabel logo resmi Nike, Uniqlo atau yang lainnya. Pasalnya, hal tersebut menjadi daya tarik lebih pada konsumen dan meningkatkan nilai jualnya.
Harga pakaian bekas di pusatnya seperti di Pasar Gembong Tebasan atau Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya sebenarnya kisaran lima ribu sampai tiga puluhan ribu saja untuk satu item. Namun, ketika pengkulak thrifting membeli pakaian bekas di pusatnya, mereka hanya membeli yang bermerk saja dan kemudian menjualnya kembali dengan harga fantastis, bahkan bisa dua hingga tiga kali lipat harga awalnya. Lagi-lagi karena ia menjual simbol merk pakaian tersebut.
Dan, anehnya, para pemuda konsumen thrifting lebih memilih membeli ke pengkulak atau pihak kedua dari pada bersusah payah mencari pakaian di pusatnya langsung dengan harga yang tentu saja lebih murah. Hal itu karena kita memang merupakan masyarakat bertipe serba instan, begitupun dengan konsumsi yang juga harus instan.
Ini lah yang saya sebut sebagai pemujaan simbol, bahwa masyarakat kita hari ini mengkonsumsi berdasarkan simbol merknya, bukan karena nilai gunanya. Meskipun di rumah kita sudah ada jaket, celana, kaos dan yang lainnya, tapi kita tetap saja nge-thrift lagi hanya karena di media sosial thrifting beriklan ada pakaian baru dengan merk yang terkenal.
Media sosial yang sebagai media pengiklanan di kebanyakan thrifting ini disebut Baudrillard sebagai simulakra. Mereka mengkampanyekan kontruksi pikiran imajiner terhadap suatu realitas tanpa menghadirkan realitas itu sendiri secara esensial. Para kapital thrifting ini sebenarnya hendak mengkampanyekan bahwa dengan menggunakan pakaian bekas asalkan bermerk terkenal secara tidak langsung akan memperlihatkan status dan kelas sosial seseorang yang dianggap kelas atas.
Padahal sebagaimana yang saya sebutkan sebelumnya bahwa mereka yang mengkonsumsi produk thrifting dengan merk terkenal menyertainya itu tidak lebih sebagai kesadaran palsu, atau yang disebut oleh Baudrillard (1981) sebagai hiper-realitas. Mereka si pemuja simbol merk pakaian itu tidak sadar kalau mereka dari golongan kelas apa, tapi mereka berusaha menampilkan diri yang tidak sesuai keadaannya. Mereka kelas menengah ke bawah, tapi karena ingin terlihat seperti kelas atas, maka mereka memaksakan diri untuk berpakaian seperti kelas atas dengan merk terkenal meskipun itu pakaian bekas.
Masyarakat kita memiliki apa yang disebut oleh Baudrillard sebagai “simbolik order”, yakni sebuah sistem tanda yang pasti, terdistribusi kewajiban dan ikatan masing-masing. Misalnya, pakaian dengan merk Gucci, Louis Vuitton, Uniqlo dan lain sebagaainya itu semua adalah tanda atau simbol yang merepresentasikan identitas seseorang bahwa ia merupakan kelas atas.
Dan, masyarakat kelas menengah ke bawah ini sedang mengejar simbolik order dengan mengkonsumsi pakaian bekas dengan merk terkenal untuk dapat menampilkan diri layaknya artis papan atas, meskipun itu semua hanyalah kepalsuan, kebohongan atau hiper-realitas. Mereka hidup dalam sebuah realitas simulasi, jika meminjam istilah dari (Baudrillard, 1983), yang sebenarnya mereka tidak di sana, tapi mereka terpengaruh oleh media iklan dan terjembab untuk hidup di sana.
Simulasi sendiri merupakan pengikisan perbedaan antara yang nyata dengan yang imajiner, yang benar dan yang palsu (Ritzer, 2003, p. 162). Ini lah yang dialami oleh para konsumen thrifting, mereka mengkonsumsi barang bekas dengan simbol merk terkenal hanya untuk mengahadirkan identitas dirinya yang merepresentasikan kelas atas, kekayaan dan lain sebagainya.
Bahkan, simulasi yang dilakukan oleh konsumen thrifting ini lebih nyata dari nyata, lebih cantik dari yang cantik, bahkan lebih benar dari yang benar (Ritzer, 2003, p. 163). Yang pada intinya mereka melampui kenyataan kelas atas. Bahkan bagi Baudrillard (1973, p. 127) permainan simulasi dan simbol-simbol ini tidak memiliki referensi objektif yang jelas.
Mudahnya coba kita lihat orang-orang kelas atas, misalnya seperti Mark Zuckerberg CEO Meta, ia jarang tuh bahkan tidak pernah menggunakan jaket atau pakaian yang berlebihan dengan merk-merk terkenal, ia malah menggunakan kaos oblong polos ketika aktivitas di luar rumah hingga menjadi pembicara. Begitupun dengan Elon Musk, si CEO Tesla ketika bertemu Jokowi dan pimpinan negara kita juga hanya menggunakan kaos, tidak lebih.
Ini yang kemudian dikatakan Baudrillard bahwa masyarakat konsumsi kita itu tidak jelas dalam menggunakan simbol kekayaan, mereka tidak memiliki referensi orang kaya siapa yang mereka rujuk. Bahkan masyarakat kelas menengah ke bawah ini melampaui cara berpakaian yang berlebihan dibandingkan orang-orang kaya di dunia.
Kita patut meratapi ini semua, karena kita hidup dalam sebuah simulasi pemujaan simbol kekayaan yang diproyeksikan oleh simulakra media pengiklanan. Anehnya, kita menikmati itu semua dan merasa bangga atas hidup dalam kepalsuan-kepalsuan.