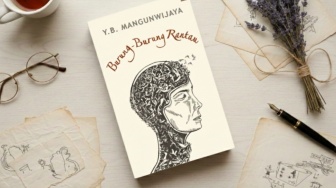Demonstrasi yang berlangsung untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia beberapa waktu lalu menjadi perbincangan hangat di media sosial. Sebuah unggahan dari akun X @padangmenfess yang memperlihatkan seorang bapak-bapak dengan baju bertuliskan "macam-macam kecanduan, ada kokain, alkohol, sabu-sabu, dan kekuasaan," menjadi viral.
Pada baju tersebut, foto Presiden Jokowi dan Gibran terpampang jelas di bawah kata "kekuasaan," menyulut perdebatan sengit di antara warganet dan masyarakat luas. Apakah ini bentuk protes yang sah? Ataukah hanya sekadar provokasi yang tak berdasar?
Jika kita melihat dari perspektif kritik sosial, baju tersebut sebenarnya membawa pesan yang kuat. Di tengah gejolak politik dan ketidakpuasan publik terhadap beberapa kebijakan pemerintah, ungkapan "kekuasaan" disandingkan dengan kecanduan seperti kokain dan sabu-sabu bukanlah tanpa alasan.
Kekuasaan, dalam konteks ini, diperlakukan seperti zat adiktif yang dapat menyebabkan kerusakan besar bagi diri sendiri dan orang lain jika disalahgunakan. Baju ini, dengan cara yang sederhana namun menyengat, mengkritik bagaimana kekuasaan dapat menjadi candu yang berbahaya, mengaburkan moralitas, dan memicu ketidakadilan.
Namun, tidak sedikit yang memandang ini sebagai bentuk penghinaan terhadap figur negara. Mereka berpendapat bahwa membawa nama Jokowi dan Gibran ke dalam kritik semacam itu adalah tindakan tidak hormat dan bisa menimbulkan perpecahan. Ini adalah contoh dari apa yang sering disebut sebagai "budaya penghinaan," di mana kebebasan berpendapat sering kali dipakai untuk menyerang pribadi dan bukan kebijakan.
Mungkin ini saatnya kita bertanya, sejauh mana kritik harus berjalan? Apakah kritik harus dilontarkan dengan nada setajam itu untuk didengar, atau ada cara yang lebih beradab dan konstruktif?
Perdebatan ini juga mencerminkan polarisasi sosial yang semakin tajam di Indonesia. Di satu sisi, ada kelompok yang merasa bahwa kritik pedas adalah satu-satunya cara untuk menyampaikan ketidakpuasan. Di sisi lain, ada mereka yang percaya bahwa kritik harus tetap dalam batas-batas kesopanan dan hukum.
Persoalan ini semakin kompleks ketika kita berbicara tentang figur yang diidolakan oleh sebagian masyarakat dan dicerca oleh sebagian lainnya. Dalam konteks demokrasi, apakah hal ini sehat atau justru menandakan bahwa kita belum matang dalam berdebat dan menyikapi perbedaan?
Lebih jauh lagi, baju tersebut mengundang refleksi mendalam tentang kekuasaan itu sendiri. Apakah kekuasaan selalu berkonotasi negatif? Atau justru, kekuasaan yang baik adalah yang selalu siap menerima kritik, sepedas apapun itu? Sejarah telah menunjukkan bahwa kekuasaan tanpa pengawasan cenderung korup dan menyimpang. Maka, meskipun kritik tersebut terasa menyakitkan, mungkin ini adalah cermin bagi para pemegang kekuasaan untuk melihat ke dalam, mengevaluasi diri, dan membuat perubahan yang lebih baik bagi rakyat.
Lantas, kita harus bertanya pada diri kita sendiri: dalam negara demokrasi, apakah kita lebih takut pada kritik atau pada kekuasaan yang tak terkendali? Ketakutan terhadap kritik hanya akan melahirkan otoritarianisme yang lebih besar, sementara menerima kritik, bahkan yang pahit sekalipun, adalah tanda kedewasaan dalam berdemokrasi. Mungkin, inilah saatnya kita membuka ruang dialog yang lebih luas, di mana kritik seperti baju bapak-bapak ini menjadi pemicu untuk diskusi yang lebih konstruktif dan inklusif.
Kita tidak harus setuju dengan semua kritik yang ada, tapi kita harus setuju bahwa kritik adalah bagian dari demokrasi yang sehat. Kita bisa memilih untuk menanggapinya dengan marah, atau kita bisa memilih untuk mengambilnya sebagai kesempatan untuk belajar dan bertumbuh. Semoga kita semua bisa memilih yang kedua.