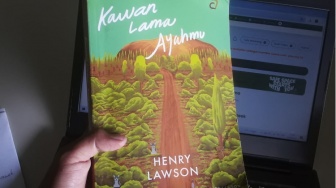Pernah nggak sih kamu ngerasa aneh kalau habis liburan tapi nggak ada satu pun foto yang kamu posting? Seolah-olah kalau nggak muncul di feed, berarti liburannya nggak kejadian gitu?
Di era digital ini, liburan bukan lagi tentang istirahat dari penat, tapi soal bagaimana caranya kita terlihat bahagia di depan publik. Yang penting bukan “aku bahagia,” tapi “aku tampak bahagia”—setidaknya di mata followers.
Padahal, dulu liburan itu sesederhana jalan ke pantai, ngopi di warung kecil, atau nonton langit sore di balkon rumah. Sekarang? Semua harus instagramable. Sudut foto harus pas, pencahayaan harus tepat, outfit harus selaras dengan latar.
Bahkan, kalau perlu, bawa tripod biar nggak ganggu minta tolong orang. Kita sibuk mengatur pose sampai lupa menikmati momen. Ironisnya, demi terlihat santai, justru kita jadi sibuk sendiri.
Budaya ini pelan-pelan mengubah makna rekreasi jadi ajang pembuktian sosial. Banyak orang rela datang ke tempat wisata bukan karena ingin menikmati keindahan alamnya, tapi karena takut ketinggalan tren.
Destinasi yang cantik dijadikan latar estetika, bukan ruang refleksi. Di balik senyum di foto, ada lelah yang nggak pernah diunggah. Di balik caption "healing", ada stres yang belum benar-benar sembuh.
Kita hidup di zaman di mana healing bukan soal menenangkan diri, tapi menenangkan algoritma. Setiap jepretan harus punya nilai tampil. Setiap momen harus punya potensi engagement. Yang dulunya pribadi, kini jadi konsumsi publik.
Dalam diam, kita jadi aktor yang tampil di panggung digital, berusaha tampak sempurna walau kenyataannya nggak selalu begitu. Feed Instagram jadi semacam kanvas pencitraan, bukan cermin kehidupan, tapi katalog versi terbaik dari diri kita.
Lucunya, semakin sering orang bilang "healing dulu", semakin besar kemungkinan dia justru lelah dengan pencitraannya sendiri. Karena begitu liburan berakhir, rasa capeknya bukan cuma dari perjalanan, tapi dari tekanan buat tampil “cukup keren”. Rasanya kayak lagi kerja lembur demi estetika. Kamera jadi saksi mata, tapi hati tetap kosong. Momen yang seharusnya menenangkan malah berubah jadi konten yang memenjarakan.
Namun, bukan berarti berbagi itu salah. Semua orang punya kebutuhan untuk diakui, itu manusiawi. Tapi ketika berbagi berubah jadi beban, di situlah kita perlu berhenti sejenak. Pertanyaannya cukup sederhana, kita posting karena ingin berbagi rasa, atau karena takut dilupakan? Kadang, kita nggak sadar kalau kita sedang mengejar eksistensi, bukan kebahagiaan. Padahal, dua hal itu beda jauh.
Kalau mau jujur, liburan sejati nggak butuh validasi. Liburan itu tentang ruang untuk diam tanpa merasa bersalah. Tentang menikmati udara tanpa mikir aesthetic. Tentang ngobrol sama teman tanpa sibuk cari sinyal.
Kadang, kebahagiaan justru hadir dalam hal-hal yang nggak bisa diabadikan seperti suara ombak, aroma hujan, atau tawa spontan yang nggak sempat direkam. Karena nggak semua hal indah harus diunggah, dan nggak semua momen berarti harus viral.
Ada satu hal yang sering kita lupakan, bahwa kamera nggak bisa menangkap rasa. Ia cuma merekam bentuk, tapi nggak bisa menyimpan kedalaman. Foto senyum bisa kelihatan sempurna, tapi siapa tahu di baliknya ada hati yang rapuh.
Mungkin yang lebih penting bukan seberapa banyak momen kita abadikan, tapi seberapa dalam momen itu kita rasakan. Kalau kamu bisa duduk di tepi pantai tanpa ingin buru-buru merekamnya, itu tandanya kamu benar-benar hadir.
Jadi, mungkin liburan nggak harus selalu terlihat instagramable. Kadang, yang paling berharga justru liburan yang nggak terekam kamera, tapi membekas di hati. Yang nggak punya filter, tapi punya makna. Yang nggak dilihat banyak orang, tapi membuat kita merasa lebih hidup.
Sebab pada akhirnya, bukan jumlah likes yang bikin kita tenang, tapi kemampuan untuk menikmati diri sendiri tanpa perlu disaksikan siapa pun.