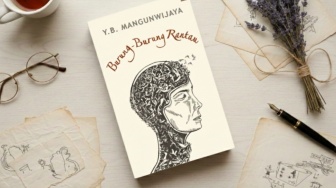Dalam setiap iklan susu formula, kita disuguhkan gambar seorang ibu muda yang tersenyum tenang, menggendong bayi dengan penuh cinta, di ruang tamu yang bersih dan rapi. Namun kehidupan nyata sering kali tak seindah itu. Di balik senyum yang terpaksa dan pelukan yang lelah, tersembunyi cerita tentang tubuh yang masih remuk setelah melahirkan, pikiran yang limbung, dan emosi yang meledak-ledak tanpa tahu kepada siapa harus bersandar.
Sebuah studi eksploratif yang dilakukan oleh Nuraini dan Mulyana (2024) dalam jurnal Psyhmpathic membongkar tabir sunyi itu. Dengan pendekatan kualitatif, mereka mendengarkan langsung suara tiga belas ibu pertama di Indonesia. Suara-suara yang selama ini tenggelam oleh tuntutan budaya, tekanan sosial, dan narasi romantisasi keibuan yang nyaring namun menyesatkan.
Salah satu benang merah yang mencolok dari penelitian ini adalah betapa krusialnya dukungan sosial bagi ibu baru, namun pada saat yang sama betapa rapuh dan timpangnya dukungan itu terdistribusi. Banyak dari para ibu itu yang menghadapi malam-malam tanpa tidur, bukan hanya karena harus menyusui atau mengganti popok, tetapi karena merasa sendiri dalam menjalani peran yang baru dan menakutkan. Mereka tidak hanya menghadapi kelelahan fisik, tetapi juga kebingungan identitas, perasaan gagal, dan tekanan emosional yang terus menghantui sejak hari pertama menjadi ibu.
Yang lebih menyakitkan, dukungan yang seharusnya datang dari orang terdekat justru menjadi sumber luka. Suami yang pasif, bahkan abai. Keluarga besar yang lebih senang mengatur daripada memahami. Mertua yang menanamkan mitos usang daripada memberi pelukan hangat. Tidak sedikit dari mereka yang merasa direndahkan dan diintervensi, seolah kehilangan kendali atas tubuh dan bayinya sendiri. Satu dari mereka berkata, “Saya tidak merasa punya kuasa sebagai ibu. Semua sudah ditentukan orang lain.”
Dalam banyak kasus, relasi dengan pasangan justru memburuk setelah kelahiran anak pertama. Suami merasa tergantikan, sementara istri merasa tidak dipahami. Bukannya tumbuh sebagai tim, mereka terpecah dalam kesalahpahaman yang tidak sempat dibicarakan. Kelelahan fisik bergandengan dengan kehampaan emosional, menciptakan jurang dalam hubungan yang sebelumnya hangat.
Yang lebih menyedihkan, tekanan terhadap ibu pertama tidak hanya hadir di ruang domestik, tetapi juga di ruang publik dan media sosial. Lingkungan sekitar kerap melontarkan komentar yang menyamar sebagai nasihat, tapi sebenarnya menyakitkan. Belum lagi standar ibu “sempurna” yang dipertontonkan di Instagram: ibu langsing pascamelahirkan, rumah rapi, bayi tenang, dan suami romantis. Semua itu menjadi hantu yang menakut-nakuti realitas para ibu di dunia nyata.
Dan di tengah tekanan bertubi-tubi itu, banyak dari mereka yang tidak tahu bahwa mereka sedang menghadapi postpartum depression. Tidak sedikit yang bahkan tidak tahu bahwa kondisi itu ada. Mereka mengira ini hanyalah “fase lelah biasa”. Padahal, kesedihan yang berkepanjangan, rasa tidak berharga, kemarahan pada diri sendiri, dan keinginan untuk menjauh dari bayi adalah alarm yang nyata. Sayangnya, alarm itu tak terdengar di tengah kebisingan tuntutan untuk terus kuat, terus tersenyum, dan terus menjadi ibu yang baik.
Ironisnya, ketika seorang ibu akhirnya mendapatkan bantuan, itu pun sering kali dibumbui oleh niat baik yang keliru. Ada bentuk dukungan yang justru mematikan otonomi: semua diambil alih, semua diputuskan oleh orang lain. Ibu baru malah dijauhkan dari proses belajar mengasuh dan diberi pesan bahwa ia tidak cukup mampu. Dalam studi ini, seorang partisipan justru merasa percaya diri ketika tidak ada orang lain di rumah. "Saya akhirnya bisa mengenal bayi saya, tanpa dihakimi,” katanya.
Ruang-ruang komunitas ibu menjadi salah satu harapan yang tersisa. Di sana, para ibu menemukan solidaritas yang jujur: bahwa tidak apa-apa merasa lelah, tidak apa-apa bingung, dan tidak apa-apa tidak sempurna. Tapi komunitas seperti ini belum merata. Masih banyak ibu di daerah-daerah yang berjuang sendirian, tanpa tempat aman untuk berbagi cerita, apalagi mendapatkan bantuan profesional.
Di titik ini, muncul pertanyaan yang lebih besar: di mana peran negara? Mengapa posyandu hanya fokus pada bayi dan mengabaikan kondisi mental ibu? Mengapa tidak ada kebijakan yang secara khusus melindungi ibu baru dari tekanan sosial dan psikologis? Mengapa konseling pascapersalinan tidak menjadi bagian dari layanan dasar kesehatan ibu?
Menjadi ibu pertama kali di Indonesia adalah proses yang heroik, namun sering kali sunyi dari pengakuan. Kita terlalu sibuk menyanjung ibu sebagai sosok yang mulia, tanpa mau melihat realitas kesehariannya yang penuh luka, darah, dan air mata. Kita terlalu cepat memberi selamat, tapi lamban memberi dukungan. Kita terlalu banyak menuntut, tapi terlalu sedikit mendengar.
Jika kita ingin menciptakan generasi yang sehat dan kuat, maka langkah pertama adalah memastikan bahwa para ibu tidak merasa sendiri dalam perjalanan mereka. Karena ibu yang bahagia dan didukung akan melahirkan anak-anak yang lebih sehat, lebih dicintai, dan lebih siap menghadapi dunia.
Mungkin sudah saatnya kita berhenti meromantisasi keibuan, dan mulai merealisasikan dukungan nyata. Bukan sekadar kado dan ucapan selamat, tapi sistem yang benar-benar peduli: dari rumah, dari masyarakat, dan dari negara.