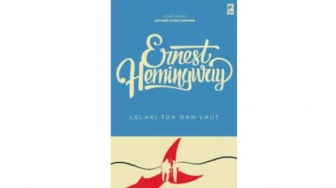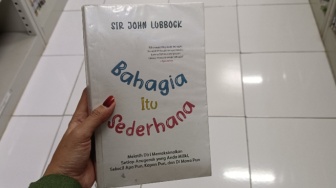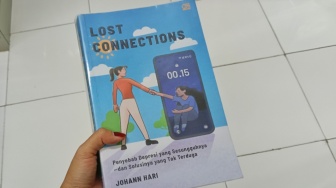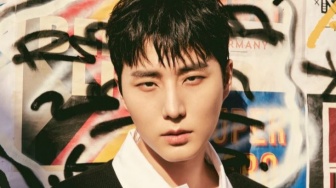Literasi publik merupakan salah satu konsep yang semakin sering digaungkan dalam diskursus akademik maupun ruang kebijakan kontemporer, tetapi seringkali pemaknaannya terjebak pada tafsir yang dangkal dan reduktif.
Banyak orang memahami literasi publik sebatas kemampuan membaca, menulis, dan memahami informasi yang tersedia di ruang publik, tanpa menyadari bahwa literasi publik jauh lebih kompleks. Ia adalah soal kesadaran kritis, soal cara masyarakat mengakses, memaknai, serta mendayagunakan informasi dalam konteks sosial, politik, dan budaya yang membentuk mereka.
Dengan kata lain, literasi publik adalah medan pertemuan antara pengetahuan dan kekuasaan, antara wacana dan tindakan, antara kepentingan individu dan tanggung jawab kolektif.
Dalam masyarakat modern yang dijejali oleh banjir informasi, literasi publik menuntut lebih dari sekadar keterampilan teknis. Informasi yang hadir tidak pernah netral, melainkan selalu dikonstruksi dalam kerangka kepentingan tertentu.
Media, misalnya, kerap disebut sebagai pilar keempat demokrasi karena kemampuannya menyediakan ruang deliberasi publik. Namun, media juga dapat menjadi alat hegemoni yang mendikte wacana, menentukan isu mana yang layak diperbincangkan, dan mana yang layak ditenggelamkan.
Di sinilah letak urgensi literasi publik: bagaimana masyarakat tidak sekadar menjadi konsumen pasif dari arus informasi, tetapi juga menjadi subjek yang kritis, mampu memilah, menilai, bahkan melawan ketika informasi yang hadir mengandung bias atau manipulasi.
Ironisnya, di Indonesia literasi publik kerap dipandang sebagai jargon yang lebih sering dipromosikan ketimbang benar-benar diinternalisasi. Indeks literasi yang rendah sering dijadikan alasan untuk menjelaskan berbagai masalah sosial, mulai dari rendahnya kualitas demokrasi hingga maraknya hoaks.
Namun, persoalan sebenarnya tidak sesederhana “masyarakat malas membaca” atau “masyarakat kurang edukasi.” Ada dimensi struktural yang harus diakui: akses terhadap sumber informasi yang berkualitas tidak merata, kualitas pendidikan yang masih timpang, serta budaya komunikasi publik yang lebih sering berpusat pada otoritas ketimbang dialog. Literasi publik bukanlah persoalan individu semata, melainkan persoalan ekosistem sosial yang mendukung atau justru menghambat terciptanya masyarakat yang kritis.
Kritik terhadap konsep literasi publik juga perlu diarahkan pada kecenderungan untuk mereduksi literasi sebagai sekadar proyek teknokratis. Program-program literasi yang digagas pemerintah, misalnya, sering berwujud kampanye membaca buku, lomba menulis, atau penyediaan akses perpustakaan digital.
Semua itu tentu penting, tetapi tanpa bingkai kritis, literasi publik hanya akan berhenti pada aktivitas simbolik. Literasi seharusnya tidak berhenti pada kemampuan mengakses teks, melainkan juga mengaitkannya dengan realitas kehidupan sehari-hari.
Membaca berita, misalnya, seharusnya disertai dengan kemampuan bertanya: siapa yang menulis, apa agenda yang tersembunyi, siapa yang diuntungkan dari narasi ini, dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat luas? Tanpa pertanyaan-pertanyaan semacam itu, literasi publik berisiko menjadi instrumen yang jinak, bukan alat pembebasan.
Sejarah mencatat bahwa literasi publik memiliki hubungan erat dengan proyek demokratisasi. Di banyak negara, kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam percakapan publik yang sehat menentukan kualitas demokrasi itu sendiri.
Habermas, dalam gagasannya tentang ruang publik, menekankan pentingnya rasionalitas komunikatif sebagai dasar deliberasi. Namun, ia juga mengingatkan bahwa ruang publik bisa dikolonisasi oleh kepentingan pasar dan kekuasaan politik.
Dalam konteks ini, literasi publik menjadi benteng pertahanan terakhir: ketika warga memiliki kesadaran kritis, mereka dapat menolak manipulasi, melawan propaganda, dan membangun wacana alternatif. Namun ketika literasi publik lemah, ruang publik akan dengan mudah dikooptasi oleh elit, korporasi, maupun aparat negara.
Di era digital, literasi publik menghadapi tantangan baru yang lebih kompleks. Informasi tidak lagi dimonopoli oleh media arus utama, melainkan menyebar melalui platform digital yang dikuasai algoritma.
Media sosial, misalnya, menyediakan ruang bagi siapa pun untuk bersuara, tetapi sekaligus memperlihatkan wajah gelap berupa disinformasi, ujaran kebencian, dan polarisasi. Algoritma bekerja bukan untuk kepentingan publik, melainkan untuk kepentingan ekonomi perusahaan teknologi yang beroperasi berdasarkan logika atensi.
Akibatnya, masyarakat kerap terjebak dalam echo chamber, di mana mereka hanya mengonsumsi informasi yang sesuai dengan keyakinan mereka, sementara pandangan yang berbeda dianggap sebagai ancaman. Literasi publik di era digital tidak hanya menuntut kemampuan kritis membaca teks, tetapi juga pemahaman terhadap ekologi digital itu sendiri: bagaimana algoritma bekerja, bagaimana data digunakan, dan bagaimana kuasa ekonomi-politik beroperasi di balik layar.
Di tengah kondisi tersebut, muncul pula paradoks literasi publik. Di satu sisi, akses informasi semakin terbuka, bahkan tanpa batas. Namun di sisi lain, keterbukaan itu justru menimbulkan kebingungan, membuat masyarakat sulit membedakan antara fakta dan opini, antara pengetahuan dan propaganda.
Fenomena post-truth menjadi bukti nyata bagaimana emosi dan identitas seringkali lebih dominan daripada data dan argumentasi rasional. Ketika masyarakat lebih percaya pada informasi yang sesuai dengan afiliasi politik atau agamanya, maka literasi publik tidak lagi menjadi soal kemampuan membaca, melainkan soal keberanian melampaui batas identitas dan kepentingan kelompok.
Di sinilah tantangan terbesar: bagaimana literasi publik mampu menumbuhkan kesadaran kolektif yang tidak terjebak pada kepentingan sempit, melainkan pada tanggung jawab terhadap kebenaran dan keadilan sosial.
Lebih jauh, literasi publik juga perlu dikaitkan dengan dimensi etika. Informasi bukan hanya soal kebenaran, tetapi juga soal dampak sosialnya. Masyarakat yang literat seharusnya bukan hanya mampu mengidentifikasi hoaks, tetapi juga memahami konsekuensi etis dari menyebarkan atau membiarkan informasi tertentu beredar.
Misalnya, bagaimana informasi terkait isu kesehatan publik dapat menyelamatkan atau justru membahayakan nyawa; bagaimana narasi tentang kelompok minoritas dapat memperkuat solidaritas atau justru melanggengkan diskriminasi. Literasi publik, dalam arti ini, bukan sekadar keterampilan teknis, tetapi juga refleksi moral: bagaimana setiap individu bertanggung jawab atas informasi yang ia konsumsi, bagikan, dan wariskan.
Namun, berbicara tentang literasi publik tanpa menyinggung persoalan kekuasaan akan membuat konsep ini kehilangan daya kritisnya. Literasi selalu terkait dengan siapa yang memproduksi pengetahuan, siapa yang mengontrol distribusi informasi, dan siapa yang menentukan standar kebenaran.
Dalam sejarah, rezim otoriter kerap mengendalikan akses informasi untuk menjaga stabilitas kekuasaan. Buku-buku dilarang, media dibungkam, dan suara kritis dibungkam. Literasi publik dalam konteks itu menjadi bentuk perlawanan: membaca teks terlarang, menulis narasi tandingan, atau mendistribusikan pamflet menjadi praktik politik yang menantang dominasi.
Di era demokrasi sekalipun, relasi kuasa tidak hilang. Media dimiliki oleh segelintir konglomerat, platform digital dikendalikan oleh korporasi global, dan bahkan negara sering menggunakan regulasi untuk mengatur arus informasi. Literasi publik, oleh karena itu, tidak hanya tentang bagaimana masyarakat belajar membaca, tetapi juga tentang bagaimana mereka menyadari relasi kuasa yang melingkupi mereka.
Kritik lebih jauh dapat diarahkan pada bagaimana literasi publik sering dikomodifikasi. Ia diperlakukan sebagai proyek pembangunan yang diukur dengan angka-angka indeks, bukan sebagai praktik sosial yang hidup.
Lembaga internasional maupun pemerintah sering menekankan pentingnya meningkatkan “angka melek huruf” atau “indeks literasi,” tetapi jarang menyinggung apakah masyarakat benar-benar mampu menggunakan pengetahuan itu untuk memperjuangkan hak-haknya.
Literasi publik, dengan demikian, berisiko direduksi menjadi statistik yang menggembirakan, tanpa menyentuh akar persoalan ketidakadilan sosial. Padahal, literasi publik sejatinya adalah soal pemberdayaan: bagaimana masyarakat yang terpinggirkan memiliki akses pada informasi yang relevan, bagaimana suara mereka didengar dalam ruang publik, dan bagaimana mereka dapat mempengaruhi kebijakan yang menyangkut hidup mereka.
Pertanyaan mendasar yang perlu diajukan adalah: literasi publik untuk siapa? Apakah ia dimaksudkan untuk memperkuat kontrol negara terhadap warganya, ataukah untuk membebaskan warga dari hegemoni kekuasaan?
Apakah ia sekadar proyek teknokratis yang berhenti pada pembangunan perpustakaan dan penyediaan buku, ataukah sebuah gerakan sosial yang mengakar pada kebutuhan masyarakat?
Pertanyaan-pertanyaan ini penting agar literasi publik tidak berhenti menjadi retorika, melainkan benar-benar menjadi praksis transformasi sosial. Dalam kerangka kritis, literasi publik adalah alat emansipasi: ia memberi masyarakat kemampuan untuk melihat dunia secara lebih jernih, untuk menyuarakan kebenaran, dan untuk menuntut keadilan.
Di Indonesia, literasi publik masih menghadapi tantangan besar. Maraknya hoaks politik, polarisasi sosial, rendahnya budaya membaca, hingga dominasi wacana oleh elit memperlihatkan bahwa literasi publik belum menjadi kesadaran kolektif. Program literasi seringkali tidak menyentuh aspek kritis, melainkan lebih menekankan pada seremonial dan formalitas.
Namun, di balik tantangan tersebut, ada pula tanda-tanda harapan. Komunitas literasi tumbuh di berbagai daerah, gerakan jurnalisme warga bermunculan, dan kesadaran terhadap pentingnya verifikasi informasi mulai meningkat. Semua ini menunjukkan bahwa literasi publik bukanlah konsep yang mati, melainkan terus diperjuangkan, meskipun jalannya berliku.
Pada akhirnya, literasi publik harus dipahami sebagai proses yang tidak pernah selesai. Ia bukan tujuan akhir, melainkan perjuangan terus-menerus untuk menjaga ruang publik tetap sehat, kritis, dan inklusif. Literasi publik menuntut setiap individu untuk melampaui dirinya sendiri, untuk melihat keterhubungan antara informasi yang ia konsumsi dengan struktur sosial yang lebih luas.
Ia menuntut masyarakat untuk tidak sekadar tahu, tetapi juga peduli, tidak sekadar cerdas, tetapi juga bijak. Literasi publik adalah soal keberanian untuk berpikir kritis di tengah banjir informasi, soal keteguhan untuk mencari kebenaran di tengah kabut propaganda, dan soal komitmen untuk menjaga martabat kemanusiaan di tengah arus kepentingan yang saling berbenturan.