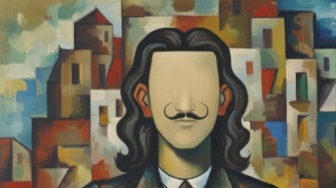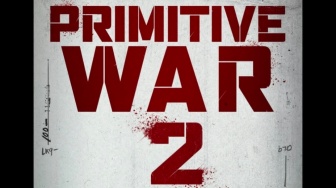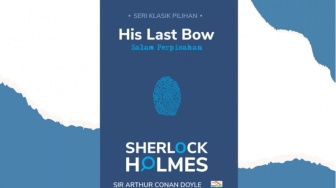- Komunikasi massa punya kuasa besar membentuk opini, tapi rawan bias dan manipulasi.
- Era digital bikin informasi lebih interaktif, tapi juga melahirkan hoaks, polarisasi, dan krisis kepercayaan.
- Literasi publik jadi kunci agar media bisa kembali sehat dan demokrasi tetap terjaga
Komunikasi massa merupakan salah satu fenomena paling menentukan dalam sejarah modern, sebuah arena di mana suara-suara bersaing untuk memengaruhi, membentuk opini, dan mengarahkan perilaku kolektif. Di balik layar kaca televisi, halaman surat kabar, frekuensi radio, hingga algoritma media sosial, komunikasi massa bekerja bukan sekadar sebagai penyampai pesan, tetapi sebagai pengatur makna. Melalui mekanisme seleksi berita, framing isu, dan repetisi narasi, komunikasi massa membentuk bagaimana masyarakat memahami realitas, bahkan sebelum mereka sempat mengalaminya secara langsung. Ironinya, kekuatan besar ini tidak selalu diiringi dengan tanggung jawab etis yang memadai.
Sejak awal perkembangannya, komunikasi massa telah menghadirkan paradoks. Di satu sisi, ia menjadi alat pencerahan yang memungkinkan informasi penting tersebar luas: penemuan ilmiah, peringatan bencana, kebijakan publik, hingga aspirasi demokrasi. Namun di sisi lain, media massa kerap menjadi corong kepentingan politik, ekonomi, atau ideologi tertentu. Edward S. Herman dan Noam Chomsky pernah mengungkap dalam Manufacturing Consent bahwa media bukanlah sekadar jendela realitas, melainkan mesin propaganda yang sering kali menguntungkan pihak-pihak berkuasa. Kritik ini semakin relevan ketika kita melihat bagaimana isu tertentu diperbesar sementara isu lain direduksi, seakan-akan publik tidak berhak melihat keseluruhan gambar.
Masalah mendasar dalam komunikasi massa terletak pada relasi asimetris antara pengirim pesan dan penerima pesan. Publik kerap berada di posisi pasif, dijejali informasi yang sudah dikemas sedemikian rupa. Bahkan ketika media mengklaim dirinya independen, selalu ada bias—baik karena ideologi redaksi, tekanan pasar, maupun agenda tersembunyi. Inilah yang membuat komunikasi massa sering dianggap sebagai ruang perebutan hegemoni. Antonio Gramsci pernah menyinggung bahwa dominasi tidak hanya bekerja melalui kekuatan fisik, tetapi juga melalui persetujuan yang dibangun lewat wacana. Media massa menjadi alat ampuh untuk membangun persetujuan itu, membuat masyarakat menerima status quo sebagai sesuatu yang wajar dan tidak perlu dipertanyakan.
Namun perkembangan teknologi digital membawa babak baru dalam komunikasi massa. Media sosial menggeser pola komunikasi satu arah menjadi lebih interaktif, memberi ruang bagi individu untuk juga menjadi produsen pesan. Publik tidak lagi hanya konsumen berita, melainkan juga pencipta konten. Secara teoretis, ini membuka peluang demokratisasi informasi. Tetapi kenyataan menunjukkan hal yang lebih kompleks. Alih-alih melahirkan ruang publik yang sehat, media sosial sering kali berubah menjadi arena kebisingan, disinformasi, dan polarisasi. Algoritma bekerja dengan logika komersial, bukan logika kebenaran. Pesan yang viral bukanlah yang paling faktual, melainkan yang paling memicu emosi. Dalam situasi ini, komunikasi massa justru menjerumuskan masyarakat pada krisis kepercayaan: orang sulit membedakan mana berita benar, mana yang sekadar sensasi, dan mana yang sengaja direkayasa.
Krisis kepercayaan ini semakin kentara ketika institusi media arus utama ikut terseret arus kecepatan. Tekanan untuk segera menyajikan berita membuat verifikasi sering kali dikorbankan. Wartawan dikejar klik, redaksi mengejar trafik, dan dalam proses itu, akurasi kehilangan tempat. Publik pun semakin sinis: jika media arus utama bisa salah, lalu apa bedanya dengan kabar dari akun anonim di media sosial? Kecurigaan semacam ini berbahaya karena bisa melemahkan fungsi media sebagai penyeimbang kekuasaan. Jika semua media dianggap bias atau tidak kredibel, masyarakat rentan jatuh ke dalam jebakan informasi yang hanya memperkuat keyakinan mereka sendiri, fenomena yang dikenal sebagai echo chamber.
Di sinilah letak krisis mendalam komunikasi massa kontemporer: ia masih memegang kuasa besar untuk membentuk kesadaran kolektif, tetapi kuasa itu kini dicurigai, ditantang, bahkan ditolak. Publik tidak lagi hanya mengonsumsi informasi; mereka juga menuntut transparansi dan partisipasi. Fenomena citizen journalism misalnya, memperlihatkan bagaimana warga biasa bisa melaporkan peristiwa lebih cepat daripada media besar. Tetapi di sisi lain, tanpa standar etika jurnalistik, laporan warga juga rawan menjadi sumber hoaks. Pergeseran ini membuat batas antara jurnalisme dan opini pribadi semakin kabur.
Lebih jauh lagi, komunikasi massa di era digital tidak hanya soal penyebaran informasi, tetapi juga soal penyebaran emosi. Media sosial bekerja dengan logika engagement yang membuat konten marah, sedih, atau lucu lebih disukai dibanding konten yang netral. Hasilnya, komunikasi massa bukan lagi sarana pencerdasan, melainkan sarana mobilisasi emosi kolektif. Kita bisa melihat bagaimana kampanye politik sekarang lebih banyak menekankan pada citra dan narasi emosional ketimbang substansi kebijakan. Dalam konteks ini, publik sering diperlakukan bukan sebagai warga negara rasional, melainkan sebagai massa emosional yang bisa digerakkan dengan simbol-simbol sederhana.
Namun, meski penuh masalah, komunikasi massa tetaplah ruang yang tak tergantikan. Ia menyediakan arena di mana gagasan bersaing, di mana informasi dibagikan, dan di mana masyarakat bisa menyusun identitas kolektif. Pertanyaannya kemudian, bagaimana kita bisa mengembalikan komunikasi massa ke jalur yang lebih sehat? Jawaban kritisnya bukan sekadar dengan memperbaiki media, tetapi juga dengan meningkatkan literasi publik. Masyarakat harus diajak untuk tidak hanya mengonsumsi informasi, tetapi juga mengkritisinya. Tanpa kesadaran kritis, publik akan selalu berada di bawah kendali narasi yang dibangun pihak lain.
Komunikasi massa pada akhirnya adalah cermin peradaban. Ketika media penuh hoaks, itu berarti masyarakat sedang haus sensasi. Ketika media dipenuhi kekerasan, itu berarti ada trauma kolektif yang belum terselesaikan. Ketika media hanya menyajikan hiburan dangkal, itu menunjukkan adanya kecenderungan melupakan hal-hal penting demi kesenangan sesaat. Dengan kata lain, kualitas komunikasi massa merefleksikan kualitas kesadaran kolektif masyarakat itu sendiri.
Oleh karena itu, kritik terhadap komunikasi massa seharusnya tidak hanya diarahkan kepada industri media, tetapi juga kepada diri kita sebagai khalayak. Kita yang mengklik, membagikan, dan memperbincangkan konten tertentu, turut menentukan arus besar informasi. Jika publik terus-menerus memberi ruang pada sensasi murahan, maka media pun akan terus memproduksinya. Tetapi jika publik mulai menghargai jurnalisme yang mendalam, analisis yang kritis, dan liputan yang berintegritas, maka media pun akan terdorong untuk berubah.
Dalam konteks Indonesia, tantangan komunikasi massa semakin rumit karena bercampur dengan politik identitas, kepentingan oligarki, dan ketimpangan akses informasi. Media besar sering kali dimiliki oleh kelompok bisnis yang juga memiliki kepentingan politik. Akibatnya, berita yang seharusnya objektif bisa berubah menjadi alat kampanye terselubung. Situasi ini membuat publik semakin skeptis dan pada akhirnya mencari alternatif di luar media arus utama, meski risiko disinformasi semakin besar.
Tetapi di balik semua kritik ini, komunikasi massa masih menyimpan potensi besar untuk menjadi kekuatan transformatif. Dengan komunikasi massa yang sehat, masyarakat bisa lebih sadar terhadap isu-isu lingkungan, keadilan sosial, hak asasi manusia, dan pembangunan berkelanjutan. Media bisa menjadi ruang dialog yang mempertemukan berbagai perspektif, bukan sekadar arena konflik. Untuk mencapai itu, dibutuhkan keberanian dari para pelaku media untuk menolak tekanan komersial sesaat dan kembali pada idealisme jurnalisme. Tetapi yang lebih penting, dibutuhkan kesadaran dari publik bahwa kualitas media tidak bisa dipisahkan dari kualitas konsumsi mereka sendiri.
Komunikasi massa, pada akhirnya, adalah medan pertempuran antara ilusi dan kebenaran, antara kuasa dan perlawanan, antara kebisingan dan kejelasan. Ia bisa menjadi alat penindasan, tetapi juga bisa menjadi sarana pembebasan. Ia bisa memicu kebencian, tetapi juga bisa menumbuhkan empati. Semua tergantung pada bagaimana kita, baik sebagai produsen maupun konsumen, menempatkan diri di dalamnya.
Di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, komunikasi massa justru menuntut kita untuk lebih kritis, lebih waspada, dan lebih sadar akan kuasa informasi. Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya sekadar opini sesaat, melainkan arah masa depan masyarakat. Jika komunikasi massa terus dibiarkan menjadi ladang manipulasi, maka demokrasi akan kehilangan makna sejatinya. Tetapi jika komunikasi massa berhasil dikelola dengan tanggung jawab, ia bisa menjadi fondasi bagi masyarakat yang lebih cerdas, lebih adil, dan lebih manusiawi.