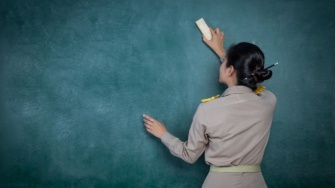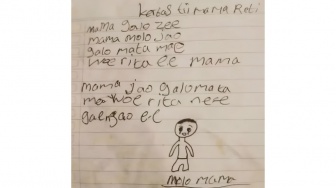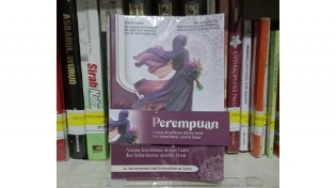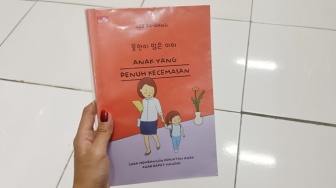Di sebuah sudut ruang tamu yang sempit, seorang nenek duduk termenung, menatap jam dinding yang seakan bergerak lebih lambat dari biasanya. Suaminya sudah lama tiada, anak-anaknya sibuk dengan dunia mereka masing-masing, dan hari-harinya kini lebih banyak diisi dengan keheningan yang panjang. Sesekali terdengar suara keras dari kamar cucunya, entah marah, entah frustrasi. Ia diam saja. Tak ingin merepotkan, tak ingin dianggap beban.
Potret ini bukanlah kisah fiktif yang asing. Ia hadir di banyak rumah, di banyak kampung, di banyak kota. Lansia di negeri ini, setelah puluhan tahun berjuang membesarkan generasi penerus, kerap harus menghadapi senja kehidupan dalam kesunyian, ketergantungan, bahkan kekerasan. Tak hanya secara fisik, tetapi lebih sering secara emosional—yang diam, tak kasat mata, tapi sangat menyakitkan.
Dalam masyarakat yang kian terobsesi pada produktivitas dan kecepatan, keberadaan lansia sering kali diposisikan di luar pusat perhatian. Mereka tidak lagi dianggap relevan dalam arus utama kehidupan, padahal justru di usia tuanya itulah mereka paling membutuhkan perhatian, perlindungan, dan kasih sayang.
Ketergantungan Fungsional dan Kekerasan yang Tak Terlihat
Di tengah gegap gempita pembangunan nasional dan narasi bonus demografi, satu kelompok sering luput dari percakapan publik: para lansia. Mereka yang pernah menjadi tulang punggung keluarga dan bangsa kini justru berada di garis rapuh kehidupan, terancam oleh ketergantungan fungsional yang tak hanya bersifat fisik, tetapi juga sosial dan emosional.
Ketergantungan fungsional ini, menurut kajian Dias dkk. (2020), berkaitan erat dengan usia lanjut, keterbatasan dalam kemampuan membaca dan menulis, serta minimnya pelibatan dalam aktivitas bermakna. Ironisnya, ketergantungan ini kerap menjadi pintu masuk bagi kekerasan—baik yang kasat mata maupun yang samar—di ruang yang seharusnya aman: rumah.
Salah satu bentuk kekerasan yang paling sering menimpa lansia adalah kekerasan psikologis. Wettstein (2020) menyebutkan bahwa setidaknya 20% lansia yang bergantung pada bantuan rutin mengalami kekerasan jenis ini. Angkanya tidak kecil dan mengindikasikan adanya kegagalan sistemik dalam memperlakukan lansia sebagai manusia utuh. Terlebih bagi mereka yang mengalami demensia, gangguan kognitif ini kerap mengundang sikap tidak sabar dari lingkungan, yang pada akhirnya menjelma menjadi kekerasan emosional atau pengabaian.
Dari Ketidakberdayaan Menuju Kekerasan—Siapa yang Bertanggung Jawab?
Faktor-faktor yang memperparah risiko kekerasan terhadap lansia sesungguhnya tidak berdiri sendiri. Dias dkk. (2020) mengidentifikasi beberapa faktor risiko yang memperburuk situasi ini, di antaranya kondisi ekonomi yang lemah, latar belakang etnis minoritas, dan gangguan kognitif. Dalam banyak kasus, kemiskinan bukan hanya membuat lansia tak mampu memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga menempatkan mereka pada posisi tawar yang rendah dalam struktur keluarga.
Dalam lanskap sosial kita yang masih menempatkan produktivitas sebagai tolok ukur nilai seseorang, lansia dianggap tidak lagi relevan. Mereka menjadi “beban” dalam narasi ekonomi rumah tangga. Ketika beban itu dirasakan terlalu berat, kekerasan—baik dalam bentuk hard violence maupun pengabaian struktural—menjadi konsekuensi yang nyaris tak terhindarkan.
Namun pertanyaannya: siapa yang bertanggung jawab atas situasi ini? Apakah hanya keluarga? Ataukah negara turut abai? Tidak adil jika beban sepenuhnya diletakkan di pundak keluarga, tanpa adanya dukungan nyata dari negara dan komunitas. Negara seharusnya hadir dalam bentuk kebijakan perlindungan sosial, sistem layanan kesehatan lansia yang layak, serta dukungan komunitas yang mendorong inklusi dan pemberdayaan.
Merawat Lansia, Merawat Kemanusiaan
Meski realitasnya suram, ada harapan. Masih menurut Dias dan kolega (2020), sejumlah faktor pelindung dapat menekan risiko kekerasan terhadap lansia, seperti dukungan sosial, perilaku aktif mencari bantuan, dan keberadaan layanan komunitas. Ini menunjukkan bahwa lansia tidak harus menjadi korban pasif dari sistem yang abai. Ketika mereka didampingi dengan empati dan diberi akses pada jaringan sosial yang kuat, risiko kekerasan dapat ditekan secara signifikan.
Perlu ada gerakan kolektif untuk membangun budaya baru: budaya menghargai usia lanjut. Menurut Gerino dan kolega (2018) hal ini bisa dimulai dari hal sederhana—pelatihan keluarga tentang perawatan lansia, kelompok dukungan bagi caregiver, hingga forum diskusi antar generasi. Sekolah dan tempat ibadah pun dapat berperan dalam membangun narasi yang menempatkan lansia sebagai bagian penting dalam komunitas, bukan beban.
Oleh karenanya, pendekatan ini mesti dilakukan secara sistematis. Lansia bukan sekadar penerima bantuan, tetapi juga kontributor dalam kehidupan sosial. Mereka seharusnya diberdayakan, didengarkan, dan dirawat dalam sistem yang manusiawi. Ini bukan utopia. Kita pun bisa ke arah sana jika ada kemauan politik dan kesadaran sosial yang menyertainya.
Masa Tua adalah Wajah Bangsa
Cara suatu bangsa memperlakukan lansianya adalah cermin kematangan moral dan sosial masyarakat itu sendiri. Apakah kita bangsa yang memuliakan pengalaman hidup? Ataukah kita bangsa yang menomorduakan mereka yang tak lagi produktif?
Menjaga senja yang ramah bukan semata tugas negara atau lembaga sosial. Ia adalah tugas kita semua, sebagai bagian dari rantai generasi yang saling terhubung. Karena pada akhirnya, kita semua—cepat atau lambat—akan sampai di sana.