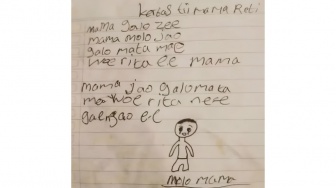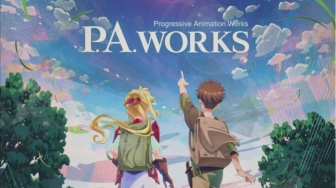Pemerintah baru saja mengetok palu UU BUMN yang salah satu poinnya bikin publik terheran-heran: direksi BUMN tak lagi dianggap sebagai penyelenggara negara.
Kedengarannya teknis, ya? Tapi efeknya bukan main. Ini bukan cuma soal jabatan, ini soal siapa yang boleh disentuh hukum—dan siapa yang jadi ‘hantu’ hukum.
KPK, lembaga antikorupsi yang dulu ditakuti para maling uang rakyat, kini bisa kehilangan wewenang untuk menyentuh para petinggi BUMN. Padahal, mereka ini lho yang duduk di kursi pengelola duit negara—bukan cuma duit kecil-kecilan, tapi triliunan rupiah.
BUMN (Badan Usaha Milik Negara) itu entitas bisnis yang, ya jelas banget, dimiliki negara. Menurut data Kementerian BUMN, total aset BUMN setiap tahun mencapai hampir Rp10 ribu triliun. Sementara direksi adalah orang-orang yang mengelola semua itu.
Tapi dengan UU baru, status mereka sebagai penyelenggara negara dihapus. Artinya, KPK nggak bisa lagi sembarangan masuk kalau ada dugaan korupsi. Harus lewat lembaga lain dulu. Kayak kalau kamu nemu maling di rumah, tapi harus lapor ke RT dulu, terus RW, baru boleh panggil polisi. Bisa-bisa malingnya udah kabur ke Bali duluan.
Alasan yang beredar adalah untuk “memperkuat profesionalisme”. Supaya direksi BUMN bisa bekerja lebih fleksibel dan nggak dibayangi ketakutan berlebihan. Tapi ya, masa iya kita bikin aturan hukum berdasarkan rasa nyaman? Kalau semua orang yang kerja pakai uang negara minta "kenyamanan", ya hukum bisa tumpul dong.
Logikanya gini: kamu dikasih kepercayaan untuk megang uang kas kelas. Tapi karena kamu “bukan pengurus resmi”, kamu bilang nggak usah diawasi. Aneh banget, kan?
Ini bukan paranoia. Dalam beberapa tahun terakhir, KPK justru berulang kali membongkar kasus besar di lingkungan BUMN. Kalau sekarang akses KPK dibatasi, kita harus tanya: siapa yang akan menjaga pintu, kalau penjaganya malah disuruh minggir?
Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), banyak kasus korupsi justru terjadi di lembaga yang mengelola uang besar dan pengawasan minim. BUMN masuk ke dalam daftar itu.
Mungkin ada yang bilang, "Tenang, masih ada polisi dan jaksa kok." Iya, secara teori masih. Tapi yuk realistis: KPK dibentuk karena dulu masyarakat nggak percaya penuh pada penegak hukum lain. Karena itulah KPK dikasih taring. Nah sekarang, taring itu pelan-pelan dicabut.
Ini bukan lagi soal siapa yang berwenang, tapi soal arah moral bangsa: kita sedang bergerak ke arah mana? Apakah kita masih menganggap transparansi dan akuntabilitas itu penting, atau kita sudah mulai kompromi demi “kenyamanan pejabat”?
Sederhana aja: kalau kamu kerja pakai uang negara, gajimu dari APBN, kantormu dibangun dari pajak rakyat, maka kamu harus siap diaudit negara.
Kalau direksi BUMN merasa terlalu “profesional” untuk diawasi, mungkin mereka lebih cocok kerja di sektor swasta. Jangan di tempat yang uangnya dari rakyat.
Jangan salah, ini bukan sekadar masalah hukum. Ini juga masalah kepercayaan publik.
Kalau kita, sebagai rakyat, merasa pengelola uang kita kebal hukum, maka kepercayaan itu pelan-pelan runtuh. Dari ketidakpercayaan, lahirlah apatisme. Kalau apatisme jadi budaya, tamatlah demokrasi.
Beberapa pakar hukum menyarankan agar pasal-pasal kontroversial ini ditinjau ulang. Tapi bola sekarang ada di tangan publik juga. Kalau kita diam, ya bisa jadi ini akan jadi preseden. Besok-besok, makin banyak pejabat yang minta status “bebas sentuh” dengan dalih “profesionalisme”.
Jangan salah, sekali satu pintu dibuka untuk kekebalan hukum, pintu-pintu lain biasanya menyusul. Hari ini direksi BUMN, besok siapa?
Jadi, pertanyaannya sekarang: kamu mau jadi generasi yang cuma scroll medsos dan nonton podcast selebritas, atau yang ikut bersuara soal siapa yang kelola uang publik?
Karena demokrasi nggak akan hancur karena satu UU buruk. Tapi bisa hancur kalau generasi mudanya diam dan menganggap itu “bukan urusan gue”.
Kalau kamu nggak bisa ngubah UU, kamu tetap bisa ngubah suara. Suara kamu penting. Kadang, satu suara kritis bisa jadi awal gelombang yang lebih besar. Mau tetap cuek, atau ikut jaga dompet bangsa?
Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS