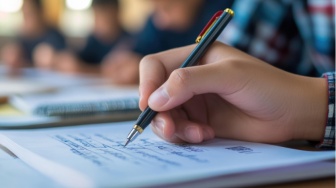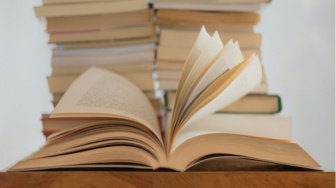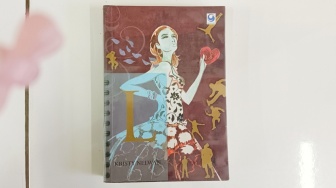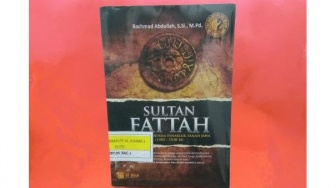Ketika seorang ibu menyusui anaknya, ia sedang menjalankan hak asasi yang tak hanya dijamin oleh naluri biologis, tetapi juga oleh hukum internasional. Namun, di tengah tuntutan ekonomi dan sosial, serta komodifikasi industri susu formula, praktik menyusui kini tak lagi sesederhana kasih sayang ibu kepada bayinya.
Di sinilah letak urgensi negara untuk hadir lebih tegas dan berpihak, bukan semata melalui regulasi yang tertulis, tetapi dalam implementasi yang nyata. Di tahun 2025 ini mengingatkan kembali pentingnya memperkuat kebijakan dan regulasi terkait pemberian ASI eksklusif.
Peringatan ini datang bukan karena stagnasi, melainkan karena keberhasilan yang mulai tampak, namun rawan runtuh jika negara tak memberi perlindungan berkelanjutan.
Meningkat, Tapi Belum Merata: Potret Capaian ASI Eksklusif di Indonesia
Statistik menunjukkan peningkatan signifikan dalam praktik pemberian ASI eksklusif. Pada 2007, hanya 32 persen bayi berusia di bawah enam bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.
Kini, berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, angka ini melonjak menjadi 68,6 persen, bahkan menurut BPS 2024 mencapai 74,73 persen. Secara angka, ini adalah kemajuan besar. Namun, angka-angka ini menyembunyikan ketimpangan yang masih menganga.
Pemberian ASI eksklusif tidak merata di semua kelompok masyarakat. Tingkat ekonomi dan pendidikan ibu menjadi penentu penting. Ibu dengan latar belakang pendidikan tinggi dan pendapatan lebih baik cenderung memiliki pengetahuan dan dukungan yang memadai untuk menyusui.
Sebaliknya, ibu dari kelompok sosial ekonomi rendah kerap kali menghadapi tantangan seperti kurangnya informasi, tekanan pekerjaan informal tanpa cuti melahirkan, hingga kuatnya pengaruh promosi susu formula.
Temuan ini mengonfirmasi riset Koirala & Paudel (2023), yang menyatakan bahwa perilaku menyusui sangat dipengaruhi faktor sosio-demografis seperti pekerjaan, usia, pendidikan, dan budaya.
Dalam konteks Indonesia, di mana ketimpangan sosial dan informasi masih menjadi tantangan besar, peran negara dalam memberikan jaminan dan penyetaraan informasi menjadi krusial.
Kebijakan Sudah Ada, tapi Masih Lemah dalam Implementasi
Di atas kertas, Indonesia sudah memiliki pijakan regulatif yang relatif kuat. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 menetapkan tentang pemberian ASI eksklusif. Disusul Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang memperkuat pengawasan terhadap pemasaran susu formula dan produk pengganti ASI.
Puncaknya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak menegaskan hak menyusui sebagai bagian dari hak dasar anak dan ibu, termasuk hak pendonor ASI dan kewajiban penyediaan ruang laktasi di tempat umum dan kerja.
Namun, seperti disampaikan AIMI, regulasi ini belum menyentuh tataran implementasi secara merata. Cuti melahirkan masih menjadi kemewahan bagi banyak perempuan pekerja informal.
Ruang laktasi di tempat kerja atau ruang publik sering kali hanya hadir sebagai formalitas, tanpa dukungan psikososial yang memadai. Masih ada pula promosi susu formula secara terselubung lewat media sosial yang menyasar langsung para ibu muda melalui influencer.
Padahal, menurut Windayani (2023), undang-undang yang mengatur ASI seharusnya mampu menjamin hak otonomi ibu secara utuh, termasuk mendapatkan informasi lengkap dan bebas dari tekanan ekonomi atau sosial untuk memilih memberikan ASI. Bila tidak, yang terjadi bukanlah perlindungan, melainkan justru pengekangan yang tidak berpihak pada ibu.
Menyusui sebagai Hak Asasi dan Investasi Bangsa
Dalam diskursus internasional, menyusui telah diakui sebagai hak asasi manusia. Ebrahimi (2021) menekankan bahwa menyusui bukan hanya hak anak untuk mendapatkan nutrisi terbaik, tetapi juga hak ibu untuk menjalankan fungsinya secara alami dan sosial tanpa diskriminasi.
Lebih dari itu, menyusui bukan hanya persoalan domestik atau pribadi, melainkan investasi strategis negara dalam membangun generasi sehat dan kuat.
Penelitian Kishore & Junapudi (2018) menyebut bahwa menyusui bukan hanya memberikan dampak kesehatan jangka pendek bagi bayi, tapi juga mempererat ikatan ibu-anak serta meningkatkan peluang keberhasilan tumbuh kembang hingga masa dewasa.
Gribble et al. (2023) bahkan menyebutkan bahwa intervensi kebijakan untuk mendukung ASI merupakan intervensi kesehatan masyarakat yang paling cost-effective untuk mencegah stunting, kematian bayi, dan penyakit tidak menular di kemudian hari.
Namun, saat ini praktik menyusui menghadapi dua tantangan besar. Pertama, industrialisasi pangan bayi yang agresif, terutama oleh perusahaan susu formula.
Kedua, absennya perlindungan negara yang setara bagi semua ibu. Keduanya menciptakan kondisi di mana menyusui dianggap beban individual, bukan hak kolektif yang harus difasilitasi.
Negara Harus Lebih Proaktif, Bukan Sekadar Reaktif
Menyusui tidak bisa dilihat sebagai pilihan yang sepenuhnya individual. Ini adalah aktivitas reproduktif yang dibentuk oleh sistem sosial, ekonomi, dan budaya. Maka dari itu, tanggung jawab negara tidak hanya berhenti pada pengesahan peraturan, tetapi pada bagaimana kebijakan tersebut menyentuh akar rumput.
Negara harus hadir dalam bentuk 1) Pendidikan publik yang berkelanjutan soal manfaat ASI, yang menjangkau semua lapisan, termasuk ibu-ibu muda di pedesaan dan pekerja informal. 2) Pengawasan ketat terhadap promosi susu formula, terutama di ranah digital yang saat ini menjadi medan perang paling baru dan paling berbahaya. 3) Pemenuhan hak cuti melahirkan dan ruang laktasi secara menyeluruh, tidak hanya di instansi pemerintah, tetapi juga swasta dan sektor informal. 4) Penyediaan konselor laktasi profesional di fasilitas kesehatan tingkat dasar, agar ibu tidak hanya diminta menyusui, tapi juga didampingi secara empatik dan profesional.
Masyarakat sipil, seperti AIMI, telah memainkan peran penting dalam advokasi menyusui. Namun, mereka tidak bisa bekerja sendirian. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus mengarusutamakan isu ini dalam kebijakan pembangunan manusia. Sebab menyusui bukan hanya urusan ibu dan anak, tetapi urusan keberlangsungan bangsa.
Jika negara ingin menekan angka stunting, memperkuat ketahanan keluarga, dan menciptakan sumber daya manusia unggul, maka tidak ada jalan pintas: kebijakan menyusui harus jadi prioritas, bukan pelengkap.
Hak untuk menyusui adalah hak untuk hidup sehat. Dan setiap hak, sejatinya, membutuhkan negara yang benar-benar hadir. Bukan dalam slogan, tapi dalam tindakan nyata.
Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS