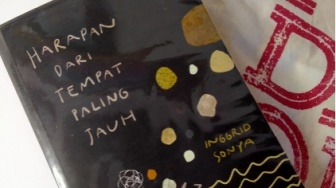Wapres Gibran dengan yakin menyebut AI sebagai alat peningkat produktivitas, bukan ancaman. Optimismenya jelas: AI dapat membantu dalam pendidikan, prediksi bencana, pelayanan kesehatan, hingga solusi kemacetan. Visi ini tak keliru. AI memang potensial.
Namun, seperti kata pepatah kekinian: “setinggi-tinggi AI terbang, koneksi sekolah tetap menentukan nasibnya.”
Setali tiga uang, data Badan Pusat Statistik (2023) menyebutkan bahwa pengguna internet di perkotaan mencapai 76,3%, sementara di pedesaan hanya 59,3%. Itu belum bicara soal kecepatan, apalagi ketersediaan perangkat di sekolah. Banyak sekolah di daerah belum memiliki laboratorium komputer, apalagi jaringan yang stabil.
Bagaimana mungkin mengajarkan machine learning di tempat di mana Wi-Fi saja dianggap barang mewah?
Masalah infrastruktur digital di Indonesia adalah gajah di tengah ruang kelas. Kita bisa bicara soal Python dan prompt engineering, tapi bagaimana nasib siswa yang harus berbagi satu komputer untuk sepuluh orang? Di mana satu-satunya “AI” yang mereka kenal hanyalah auto-correct di ponsel milik guru?
Dari Coding ke Caring: Memanusiakan AI
Meskipun kurikulum AI tampak teknokratis, banyak ahli mengingatkan bahwa AI bukan sekadar logika, tapi juga etika dan emosi.
Psikolog anak menekankan bahwa pendekatan pengenalan AI harus memperhatikan sisi emosional dan sosial anak. Tanpa pendekatan yang tepat, anak bisa merasa terasing oleh teknologi yang dingin, preskriptif, dan tak menyapa sisi manusiawinya.
Ada usulan konkret tentang tahapan pengenalan AI yang sesuai usia: 1) SD: diperkenalkan lewat permainan logika dan coding unplugged—tanpa perangkat, tapi tetap berpikir algoritmis. 2) SMP: bisa mulai mengenal Scratch atau visual programming, yang menyenangkan dan interaktif. 3) SMA/SMK: belajar Python dasar, eksplorasi AI vision, natural language processing (NLP), dan aplikasi nyata yang bisa mereka bangun sendiri.
Namun, sekadar mengajarkan tools bukan solusi jangka panjang. Kurikulum AI perlu menyentuh dimensi etika: bagaimana algoritma bisa bias? Apa implikasinya jika semua keputusan diserahkan pada mesin? Bagaimana menjaga privasi digital siswa?
Tanpa diskusi seperti ini, pendidikan AI bisa menghasilkan anak-anak cerdas secara teknis, tapi kosong secara reflektif.
Guru dan Beban Baru di Era Robotik
Masalah besar yang belum disentuh secara serius adalah kesiapan guru. Sebagian besar guru di Indonesia belum mendapatkan pelatihan dasar AI. Di tengah tugas administratif yang menumpuk dan beban mengajar yang berat, kini mereka dituntut pula untuk jadi “AI coach”.
Bahkan di sekolah favorit di kota besar, banyak guru mengaku belum memahami perbedaan antara AI generatif dan chatbot biasa. Apalagi di pelosok yang akses pelatihannya masih mimpi.
Ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kurikulum AI hanya akan "nyangkut" di sekolah yang sudah mapan—dengan guru berpengalaman, pelatihan rutin, dan dana BOS yang cukup. Sementara sekolah lain hanya akan meng-copy silabus tanpa mampu mengimplementasikan substansi.
Ubaid Matraji, aktivis pendidikan, menyebut: “Kurikulum AI bisa gagal kalau pondasi dasar pendidikan masih rapuh.”
Ia benar. Kemampuan dasar siswa dalam literasi dan numerasi—yang menurut hasil Asesmen Nasional 2023 masih rendah—membuat tantangan makin pelik. Bagaimana mau bicara model AI prediktif jika pemahaman bacaan anak kelas 6 SD saja belum mencapai 50%?
Menuju Teknologi yang Sadar Sosial
Jargon “inovasi” telah lama jadi mantra pendidikan. Tapi, seperti pisau, inovasi bisa bermanfaat atau membahayakan tergantung pada siapa yang memegangnya.
Yang dibutuhkan Indonesia bukan sekadar inovasi, tapi mindful innovation—yakni pemanfaatan teknologi dengan kesadaran sosial.
Alih-alih berdiri sendiri sebagai mata pelajaran yang eksklusif, AI sebaiknya diintegrasikan ke lintas mata pelajaran: PPKn bisa membahas etika digital, IPS menyentuh dampak otomasi pada tenaga kerja, Bahasa mengulas bias dalam teks AI, dan Seni Budaya mengeksplorasi bagaimana AI bisa melestarikan budaya lokal.
Proyek siswa bisa diarahkan ke topik yang membumi: membangun chatbot berbahasa daerah, mendesain sistem prediksi panen untuk desa mereka, atau membuat AI sederhana untuk mengarsipkan cerita rakyat.
AI tak harus berwajah Silicon Valley. Ia bisa berwajah Wamena, Brebes, atau Nunukan—asal diberi kesempatan untuk hadir dalam konteks lokal.
Sejumlah kajian (Vieriu & Petrea, 2025) menyebutkan bahwa integrasi AI dalam pendidikan perlu disertai pengawasan etis yang ketat, sebab risikonya mencakup: 1) Ketergantungan berlebih pada mesin. 2) Menurunnya daya nalar dan kreativitas. 3) Privasi data siswa yang tak terlindungi. 4) Kecenderungan menyeragamkan solusi pendidikan.
Yang lebih berbahaya adalah ketimpangan digital makin menganga: mereka yang bisa mengakses AI akan semakin jauh melesat, sementara yang tertinggal akan makin terbenam dalam ketidaksetaraan.
Anak, AI, dan Arah Pendidikan
Kurikulum AI adalah gagasan besar. Ia bisa jadi revolusi, bisa juga jadi distraksi. Semua tergantung pada bagaimana, oleh siapa, dan untuk siapa ia dijalankan.
Jika dilakukan dengan gegabah, ia hanya akan menambah ketimpangan: murid elite akan bercakap dengan ChatGPT, murid marginal masih bertanya di papan tulis reyot.
Jika dilaksanakan dengan hati-hati dan berbasis pemerataan, ia bisa jadi alat pembebasan: membuka wawasan anak desa, memperkuat budaya lokal dengan teknologi, dan membuat anak-anak kita bukan hanya pengguna, tapi pencipta.
AI seharusnya bukan tujuan, tapi alat.
Ia bukan pengganti guru, bukan substitusi kurikulum dasar, tapi pelengkap untuk membawa pendidikan Indonesia ke masa depan yang tak hanya canggih, tapi juga adil.
Kuncinya ada pada pelatihan guru, perbaikan infrastruktur, pengawasan etis, dan keterlibatan masyarakat dalam menentukan bentuk teknologi yang sesuai dengan kebutuhan lokal.
Dan yang paling penting: kita tak boleh membiarkan anak-anak belajar dengan algoritma, tapi tumbuh tanpa empati.