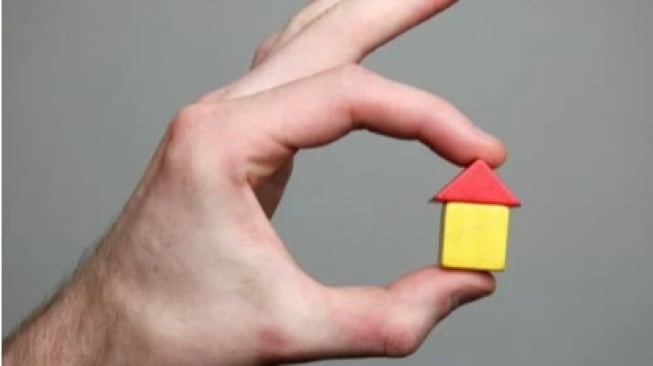Di tengah panasnya persaingan hidup di kota-kota besar, wacana rumah subsidi 18 meter persegi muncul bak iklan diskon tengah malam: menggiurkan di permukaan, memicu kebingungan saat dibuka detailnya.
Sebuah ide yang katanya muncul dari kepedulian negara terhadap keterbatasan lahan dan melonjaknya harga tanah. Tapi benarkah ini wujud kepedulian, atau hanya bentuk lain dari kompromi terhadap kenyataan?
Sebuah riset dari Rumah123 yang dilakukan selama Januari hingga Mei 2025 menyampaikan fakta yang mencubit logika: dari ribuan responden di wilayah Jabodetabek, hanya 0,8% yang tertarik pada rumah tapak berukuran di bawah 20 meter persegi.
Mayoritas menolaknya mentah-mentah—bukan karena tak butuh rumah, tetapi karena tak ingin hidup seperti ikan cupang dalam stoples.
Wacana rumah 18 meter persegi memang terdengar efisien dalam presentasi PowerPoint birokrat. Namun, begitu dibawa ke realitas, konsep ini seperti mencoba menyimpan lemari pakaian keluarga di laci meja kerja: tak masuk akal dan membuat frustrasi.
Alih-alih menyelesaikan persoalan hunian, rumah sebesar kotak kardus justru berisiko membuka babak baru kemiskinan yang dipermanenkan oleh kebijakan.
Rumah atau Ruang Tahan Nafas?
Mereka yang pernah merasakan tinggal di hunian sempit tahu persis: tidak ada yang benar-benar nyaman di ruang dengan batas dinding sejengkal dari kasur.
Rumah bukan hanya tempat berteduh, tetapi tempat tumbuh. Bukan cuma soal atap dan lantai, tapi tentang bagaimana jiwa manusia bisa bernafas, berinteraksi, dan bermimpi.
Gagasan rumah 18 meter persegi terdengar seperti eksperimen sosial yang diambil dari catatan kaki dokumen darurat. Ukuran itu bahkan tak cukup luas untuk menyelenggarakan ulang tahun balita tanpa menendang dispenser. Di kota yang sudah sumpek, solusi hunian tidak semestinya menyempitkan hidup.
Studi dari Chan (2023) tentang hunian superpadat di Hong Kong menunjukkan bahwa tinggal di ruang yang sangat terbatas berdampak signifikan terhadap kesehatan mental penghuninya. Bukan hanya stres dan gangguan tidur, tetapi juga munculnya perasaan terkekang yang berkepanjangan—seolah ruang pribadi menjadi barang mewah yang tak lagi terjangkau.
Yang lebih mengkhawatirkan, hunian seperti ini dapat melanggengkan kemiskinan antargenerasi. Anak-anak yang tumbuh di ruang sesempit itu akan terbiasa dengan batas yang sempit—baik secara fisik maupun aspirasi. Sebuah rumah sempit bisa jadi awal dari mentalitas sempit, dan dari situlah rantai keterbatasan mulai mengunci nasib.
Apartemen Mini: Nyaman karena Terpaksa?
Berbeda dengan rumah tapak superkecil, apartemen mini ternyata justru memiliki peminat lebih tinggi. Berdasarkan riset yang sama, minat terhadap apartemen berukuran di bawah 20 meter persegi cukup signifikan: 23% di Depok, 11,6% di Bogor, hingga 9,2% di Bekasi.
Fenomena ini mencerminkan perubahan selera generasi urban—yang bukan hanya soal gaya hidup minimalis, tetapi lebih pada keterpaksaan sistemik.
Apartemen mini dianggap lebih rasional karena biasanya berada di lokasi strategis, dekat transportasi umum, dan memiliki fasilitas umum seperti keamanan dan akses listrik yang stabil—dua hal yang sering kali absen dalam rumah subsidi di pinggiran kota. Meski kecil, apartemen menawarkan sentuhan modernitas dan janji efisiensi.
Namun di balik kemasan estetisnya, risiko kesehatan mental dan ketidaknyamanan tetap mengintai. Morganti et al. (2022) menyebutkan bahwa kualitas udara dalam ruangan dan kepadatan ruang memiliki korelasi kuat dengan gejala depresi sedang hingga berat. Apartemen mungil, tanpa pencahayaan alami atau ventilasi layak, mudah berubah dari tempat tinggal menjadi ruang tekanan.
Gaya hidup efisien seharusnya tidak berarti mengorbankan kelayakan hidup. Jika apartemen mini hanyalah bungkus cantik dari realitas sempit, maka minat yang tampak hanyalah bentuk lain dari toleransi terhadap nasib, bukan penerimaan terhadap solusi.
Rumah Tapak dan Ruang yang Tak Sekadar Fisik
Meski harga tanah terus melambung dan urbanisasi tak bisa dibendung, keinginan masyarakat terhadap rumah tapak tak pernah benar-benar surut.
Ada alasan mendalam mengapa rumah tapak tetap diidam-idamkan: fleksibilitas, privasi, dan ruang bertumbuh. Rumah tapak memungkinkan ekspansi fisik dan emosional. Di dalamnya, keluarga bisa tumbuh bukan hanya dalam jumlah, tapi juga dalam nilai.
Sayangnya, dalam narasi pembangunan saat ini, rumah tapak perlahan digeser dari kebutuhan menjadi kemewahan. Wacana rumah 18 meter justru menampilkan sebuah kemunduran yang dibalut dalih efisiensi. Di tengah kemajuan teknologi dan janji kota pintar, negara justru menawarkan hunian sempit seolah itu jawaban modern atas urbanisasi.
Menurut Hubbard (2024), salah satu krisis perkotaan terbesar adalah mengecilnya ruang sosial dalam hunian modern. Ketika rumah tidak lagi menyediakan ruang untuk berinteraksi, belajar, dan merenung, maka yang terjadi adalah alienasi domestik: hidup bersama tapi merasa asing. Apa gunanya rumah jika tak bisa menjadi tempat pulang secara emosional?
Menawarkan rumah sekecil itu bukan hanya soal ukuran fisik, melainkan soal ukuran empati negara terhadap warganya. Jika satu-satunya solusi adalah menyempitkan hidup, maka negara kehilangan imajinasi sosialnya.
Jakarta Utara: Percontohan atau Peringatan?
Dari seluruh wilayah Jabodetabek, hanya Jakarta Utara yang mencatat sedikit lonjakan minat terhadap rumah tapak kecil: 2,7%. Angka ini masih rendah, tetapi lebih tinggi dari kota-kota lainnya. Fenomena ini bukan tanpa sebab. Jakarta Utara selama ini dikenal sebagai wilayah padat dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi dan banyak permukiman informal.
Warga yang hidup dalam kondisi serba terbatas tentu akan memandang rumah 18 meter sebagai peningkatan—bukan karena layak, tetapi karena sebelumnya lebih buruk. Di sinilah bahaya konsep “cukup” menjadi nyata: ketika standar terlalu rendah, maka semua hal di bawahnya bisa dianggap sebagai kemajuan.
Rencana rumah subsidi 18 meter pun sebenarnya masih sebatas wacana. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Maruarar Sirait, menyatakan bahwa ini baru gagasan, bukan keputusan final. Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, pun menggarisbawahi perlunya pembahasan lebih lanjut dengan pihak seperti BTN.
Namun sejarah pembangunan menunjukkan, wacana yang tidak dibantah akan berubah menjadi program. Dan program yang tidak diawasi akan berubah menjadi bencana. Jika rumah 18 meter benar-benar direalisasikan tanpa perencanaan matang, maka kota-kota besar akan disesaki kubikel hunian yang lebih mirip ruang tunggu permanen daripada rumah tinggal.
Rumah Harus Lebih Besar dari Sekadar Dinding
Setiap warga negara layak mendapatkan tempat tinggal yang tidak hanya bisa dipakai untuk tidur, tapi juga untuk hidup. Bukan hanya tempat menaruh tubuh, tapi tempat menumbuhkan jiwa. Rumah bukan soal jumlah meter persegi, tapi soal keberadaan ruang untuk tumbuh bersama, bermimpi bersama, dan menua bersama.
Jika keterbatasan lahan adalah tantangan, maka solusinya adalah pembenahan tata ruang, bukan pengerdilan hak dasar. Jika harga tanah menjadi alasan, maka kontrol dan distribusi tanah perlu dibenahi. Menyodorkan rumah 18 meter sebagai solusi adalah seperti menyodorkan perahu bocor sebagai jawaban atas banjir.
Bangsa ini telah membuktikan mampu membangun jalan tol di laut dan bandara di bukit. Maka tak masuk akal jika tak mampu membangun perumahan rakyat yang layak dan manusiawi. Rumah 18 meter hanyalah jawaban teknis atas masalah struktural yang lebih besar. Dan jawaban teknis tak akan pernah cukup jika kehilangan nilai sosial di baliknya.