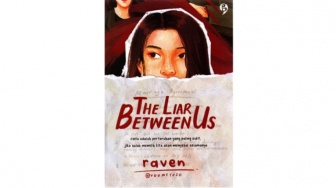Fenomena belanja daring kini menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup masyarakat urban, khususnya generasi muda. Kemudahan bertransaksi hanya dengan satu "swipe" di layar ponsel, diikuti fitur checkout instan, menyebabkan konsumsi lebih cepat dan sering impulsif.
Bahkan tidak jarang, keputusan finansial dibuat tanpa perhitungan matang, hanya karena tergoda promo, diskon, atau tren media sosial. Akibatnya, banyak yang berujung pada penyesalan, dan saat sadar bahwa saldo menipis, tagihan menumpuk, dan barang yang dibeli ternyata tidak terlalu dibutuhkan.
Masalah ini mengangkat pertanyaan penting mengenai seberapa paham sebenarnya kita tentang keuangan pribadi? Di tengah derasnya arus konsumsi digital, masyarakat, terutama anak muda, justru menghadapi tantangan besar dalam mengelola uang.
Literasi keuangan tak lagi sebatas tahu menabung, tetapi menyangkut kesadaran penuh akan cara mengatur pemasukan, pengeluaran, investasi, dan utang. Maka, penting untuk membuka ruang diskusi mengenai bagaimana budaya konsumtif digital dapat diimbangi dengan pemahaman finansial yang sehat.
Budaya Konsumtif dan Gaya Hidup Digital
Media sosial memainkan peran besar dalam membentuk pola konsumsi masyarakat. Influencer, selebritas, dan iklan bertarget mendorong audiens untuk membeli barang-barang tertentu demi memenuhi standar gaya hidup tertentu.
Akibatnya, banyak orang merasa harus selalu "ikut tren" agar tidak tertinggal atau merasa kurang dari yang lain. Ini dikenal sebagai fenomena FOMO (Fear of Missing Out) yang kerap memicu keputusan belanja impulsif.
Tak hanya itu, keberadaan aplikasi belanja online yang dilengkapi fitur "wishlist", "flash sale", hingga metode pembayaran instan, menciptakan pengalaman belanja yang adiktif. Konsumsi pun tidak lagi rasional, tetapi emosional. Ketika kepuasan instan lebih diutamakan ketimbang kebutuhan riil, keuangan pribadi pun menjadi taruhannya.
Minimnya Literasi Keuangan: Masalah yang Nyata
Di Indonesia, indeks literasi keuangan masih tergolong rendah. Berdasarkan data OJK tahun 2022, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia baru mencapai sekitar 49,68%.
Artinya, lebih dari separuh populasi belum memahami dasar-dasar pengelolaan uang yang sehat. Ini menjadi celah besar yang membuat masyarakat rentan terhadap jebakan utang konsumtif, investasi bodong, hingga kegagalan merencanakan masa depan finansial.
Kondisi ini diperparah dengan absennya pendidikan keuangan yang sistematis di lingkungan sekolah maupun keluarga. Banyak remaja dan mahasiswa tumbuh tanpa pemahaman bagaimana menyusun anggaran, menabung untuk tujuan jangka panjang, atau menghindari jebakan kredit. Akhirnya, mereka belajar dari pengalaman buruk, bukan dari bekal pengetahuan.
Paylater dan Kredit Instan: Kemudahan yang Menyesatkan?
Salah satu tren paling mengkhawatirkan dalam konsumsi digital adalah penggunaan fitur paylater atau kredit instan tanpa kartu. Fitur ini memang memberikan kenyamanan, tetapi sering kali menjebak pengguna dalam pola belanja yang lebih besar dari kemampuan mereka.
Dengan bunga tersembunyi dan jatuh tempo yang tidak disadari, banyak pengguna akhirnya kesulitan melunasi utang yang menumpuk dari transaksi kecil-kecilan.
Ketiadaan kontrol diri dan kurangnya pemahaman mengenai mekanisme kredit menjadi pemicu utama. Banyak orang tidak menyadari bahwa kemudahan ini bukanlah "uang gratis", melainkan utang yang harus dibayar dengan konsekuensi finansial jangka panjang.
Jika tidak dibarengi dengan literasi keuangan yang baik, paylater justru bisa jadi pintu masuk menuju krisis finansial pribadi.
Membangun Kesadaran Finansial Sejak Dini
Solusi dari masalah ini bukan sekadar membatasi akses terhadap belanja digital, tetapi membekali masyarakat dengan literasi keuangan yang kuat.
Pendidikan finansial seharusnya diberikan sejak usia sekolah, agar anak-anak terbiasa dengan konsep nilai uang, menabung, dan membuat pilihan bijak dalam pengeluaran. Kesadaran ini perlu diperkuat juga di level keluarga, dengan orang tua sebagai teladan pengelolaan keuangan yang sehat.
Selain itu, platform digital juga bisa berperan aktif. Alih-alih hanya mendorong konsumsi, perusahaan teknologi bisa menyisipkan fitur edukatif seperti peringatan pengeluaran berlebih, simulasi anggaran, atau konten literasi keuangan yang mudah diakses. Inovasi semacam ini mampu mengubah pola pikir masyarakat, dari konsumtif menjadi reflektif.
Di era digital yang serba cepat dan penuh godaan konsumsi, literasi keuangan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Budaya "swipe, checkout, nyesel" bisa dikendalikan jika masyarakat memiliki kesadaran dan kemampuan untuk mengelola uang dengan bijak.
Daripada terus terjebak dalam siklus belanja impulsif dan penyesalan, saatnya membangun relasi yang lebih sehat dengan uang.