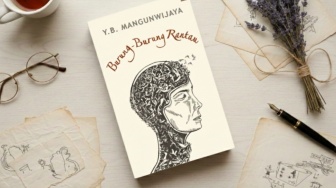Dalam kehidupan sosial yang dibentuk oleh tuntutan untuk selalu “baik-baik saja”, muncul sebuah fenomena psikologis yang merayap secara perlahan namun sangat merusak: toxic positivity. Istilah ini mungkin terdengar paradoksal bagi sebagian orang bagaimana mungkin sesuatu yang positif justru menjadi racun? Namun, jika ditelusuri lebih jauh, toxic positivity bukan sekadar tentang bersikap optimis, tetapi tentang pemaksaan terhadap emosi positif secara mutlak, bahkan ketika realitas tidak mendukung. Ia adalah bentuk penyangkalan emosi manusia yang kompleks, dibungkus dengan senyum palsu dan kutipan motivasi yang menggugah tetapi kosong makna.
Dalam masyarakat kontemporer, terutama yang hidup dalam tekanan performa, produktivitas, dan ekspektasi sosial, kebahagiaan telah menjadi tujuan utama yang harus dicapai, apa pun keadaannya. Seseorang yang sedang berduka justru sering dinasihati untuk “bersyukur karena masih diberi kesempatan hidup”. Mereka yang mengeluh soal pekerjaan dinilai kurang ikhlas, dan mereka yang menangis dianggap lemah karena “tidak bisa berpikir positif”. Akibatnya, emosi-emosi yang dianggap negatif seperti marah, kecewa, sedih, frustasi, dan takut menjadi terlarang, padahal semuanya adalah bagian dari pengalaman manusia yang sah dan sehat.
Fenomena toxic positivity ini mendapatkan momentumnya dalam budaya digital, di mana citra dan narasi menjadi komoditas utama. Media sosial dipenuhi oleh konten-konten yang mendorong orang untuk selalu tersenyum, bersyukur, bangkit, dan “tidak menyerah”. Di satu sisi, ini bisa menjadi penyemangat. Namun di sisi lain, ketika pesan-pesan tersebut tidak memperhitungkan konteks emosional dan kompleksitas pengalaman personal seseorang, ia berubah menjadi tekanan psikologis. Orang-orang merasa bersalah karena merasa sedih. Mereka merasa tidak cukup kuat karena tidak bisa segera pulih dari luka. Dalam keheningan, mereka menjadi tahanan dari standar kebahagiaan yang ditetapkan oleh algoritma.
Toxic positivity lahir dari niat yang tampaknya baik: menyemangati, menghibur, dan menenangkan. Tetapi di balik niat tersebut, terdapat penyangkalan terhadap kenyataan emosional yang sedang dihadapi. Alih-alih mendengarkan dengan empati, seseorang yang terjebak dalam toxic positivity akan menyodorkan solusi instan dalam bentuk kalimat seperti “everything happens for a reason”, “kamu pasti bisa”, atau “lihat sisi baiknya saja”. Respons-respons semacam ini tampaknya menyejukkan, tetapi sering kali justru menutup ruang ekspresi emosional yang dibutuhkan seseorang untuk memproses rasa sakitnya.
Secara psikologis, ekspresi emosi negatif adalah bagian penting dari proses penyembuhan dan adaptasi. Menangis ketika terluka, marah ketika dikhianati, atau takut saat menghadapi ketidakpastian adalah reaksi normal yang justru menandakan kesehatan emosional. Menekan emosi ini demi terlihat kuat atau positif hanya akan menciptakan tekanan internal yang lebih besar. Lama-kelamaan, emosi yang ditekan itu bisa muncul dalam bentuk gangguan psikosomatis, kecemasan kronis, bahkan depresi. Maka, toxic positivity bukan sekadar masalah sosial, melainkan persoalan kesehatan mental yang serius.
Yang menjadikan toxic positivity lebih berbahaya adalah karena ia kerap disamarkan sebagai kepedulian. Dalam hubungan antarpribadi, kita sering kali tanpa sadar melukai orang lain dengan maksud menghibur. Ketika seseorang mencurahkan perasaan tentang kesedihan mendalam yang ia alami, respons kita bisa berupa “jangan dipikirkan terus, nanti tambah stres”. Padahal, yang dibutuhkan bukanlah penyelesaian, melainkan pendampingan. Sikap ingin segera menyelesaikan atau membungkam emosi orang lain sering kali berasal dari ketidaknyamanan kita sendiri dalam menghadapi rasa sakit orang lain. Kita tidak tahu harus berkata apa, maka kita mengandalkan frasa-frasa umum yang tampak positif, padahal tidak menyentuh akar masalah.
Dalam konteks pekerjaan, toxic positivity sering dijadikan alat untuk menekan pekerja agar tetap produktif meskipun dalam kondisi tidak sehat secara fisik maupun emosional. Budaya korporat yang memuja optimisme dan semangat kerja tanpa henti menciptakan ruang kerja yang tidak ramah terhadap kesehatan mental. Ungkapan seperti “we are family here” sering kali digunakan untuk menutupi ekspektasi kerja yang berlebihan dan kurangnya dukungan struktural. Ketika karyawan menyuarakan kelelahan, mereka justru disuruh self-healing atau “ambil cuti saja” tanpa mengubah beban kerja yang tidak manusiawi. Di sini, positivity menjadi alat kontrol, bukan bentuk kepedulian.
Dalam konteks keluarga, toxic positivity dapat menimbulkan luka emosional jangka panjang. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang menuntut mereka untuk selalu bahagia dan bersyukur, cenderung tidak terbiasa mengekspresikan emosi secara sehat. Mereka belajar untuk menyembunyikan tangis, mengabaikan rasa kecewa, dan berpura-pura kuat demi memenuhi harapan orang tua. Pada akhirnya, ketika dewasa, mereka membawa pola ini ke dalam kehidupan sosial mereka menjadi pribadi yang penuh senyum di luar, tetapi rapuh dan kosong di dalam. Trauma yang dibentuk oleh tekanan untuk selalu positif ini sangat nyata, meskipun sering kali tidak disadari.
Budaya spiritualitas populer juga turut berperan dalam memperkuat toxic positivity. Banyak narasi religius yang disalahpahami atau digunakan secara keliru untuk membungkam emosi negatif. Seseorang yang bersedih disebut kurang bersyukur. Orang yang merasa gagal dinilai kurang tawakal. Padahal, dalam banyak tradisi spiritual dan keagamaan yang otentik, kesedihan dan keterpurukan justru dilihat sebagai bagian penting dari perjalanan batin dan pertumbuhan rohani. Mengubah agama menjadi alat untuk menekan emosi justru menodai makna spiritualitas yang sejati.
Masalah dari toxic positivity bukan pada optimisme itu sendiri, melainkan pada pengabaian realitas. Optimisme yang sehat adalah ketika seseorang tetap melihat harapan, tetapi tidak menyangkal rasa sakit. Ia mampu mengakui bahwa hidup bisa sulit, namun tetap memilih untuk melangkah. Sebaliknya, toxic positivity memaksa seseorang untuk menutup mata terhadap kesulitan, dan hanya menerima narasi kebahagiaan sebagai satu-satunya pilihan yang sah. Di sinilah letak bahayanya: ia bukan tentang melihat sisi terang, tetapi tentang menolak adanya kegelapan.
Dalam jangka panjang, budaya toxic positivity menciptakan generasi yang secara emosional tidak autentik. Mereka tidak mengenal diri mereka yang sebenarnya karena terlalu sibuk menjadi “positif” sesuai ekspektasi sosial. Mereka takut dicap lemah jika jujur tentang perasaannya. Mereka kehilangan kemampuan untuk hadir secara utuh dalam kesedihan maupun kebahagiaan. Hidup mereka menjadi permukaan yang dipoles, bukan kedalaman yang dijelajahi. Dalam masyarakat semacam ini, empati kehilangan maknanya, karena rasa sakit bukan lagi sesuatu yang layak didengarkan, tetapi harus segera dihapus.
Menghadapi toxic positivity tidak berarti kita harus menolak semua bentuk optimisme. Justru, kita perlu memulihkan makna sejati dari sikap positif yang berbasis empati, kejujuran, dan penerimaan terhadap kenyataan. Kita perlu menciptakan ruang-ruang sosial di mana orang merasa aman untuk mengatakan, “aku tidak baik-baik saja hari ini,” tanpa dihakimi atau disuruh tersenyum. Kita perlu belajar untuk hadir dalam kesedihan orang lain, bukan mengalihkannya dengan kata-kata kosong. Kita juga perlu berdamai dengan emosi kita sendiri belajar merangkul amarah, kesedihan, dan ketakutan sebagai bagian dari kemanusiaan kita.
Dalam dunia yang terus mendorong kita untuk tampil bahagia, memilih untuk jujur terhadap rasa sakit adalah tindakan keberanian. Melawan toxic positivity bukan berarti menyerah pada penderitaan, melainkan menghargai proses pemulihan secara utuh dan manusiawi. Karena pada akhirnya, kekuatan bukan terletak pada senyuman yang dipaksakan, melainkan pada keberanian untuk merasakan apa pun yang memang layak dirasakan.