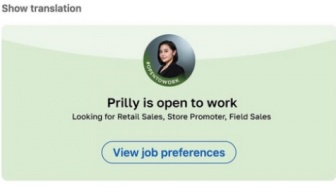Setiap hari, anak-anak generasi kini membuka dunia dari layar 6 inci. Mereka menyerap jutaan fragmen informasi yang tak terkurasi, dari video lucu absurd hingga meme surealis yang membuat batas antara realitas dan imajinasi mengabur. Di balik tawa singkat dari video “Tung Tung Sahur” atau karakter “Balerina Cappucina” yang viral di TikTok, terselip bahaya senyap: brain rot sejenis kemerosotan fungsi kognitif akibat paparan konten digital receh yang terus-menerus.
Oxford Word of the Year 2024 menetapkan brain rot sebagai istilah penting tahun ini. Tapi jauh sebelum itu, pada 1854, filsuf Henry David Thoreau sudah menyindir kemerosotan nalar akibat ketertarikan manusia terhadap hal remeh-temeh. Kini, lewat sentuhan algoritma media sosial, gejala itu menjelma epidemi digital.
Survei menyebutkan, anak-anak menghabiskan lebih dari 4,5 jam per hari menatap layar ponsel, sementara hanya 40 menit yang digunakan untuk bermain di luar. Artinya, lebih dari sepertiga waktu aktif mereka digunakan untuk aktivitas yang cenderung pasif dan repetitif. Sementara orang tua, dalam banyak kasus, memilih menyerah pada layar daripada terlibat langsung dalam pola asuh digital anak.
Profesor Kathryn J. Saunders dari Universitas Ulster menyebut ini sebagai dilema pengasuhan zaman sekarang: bagaimana menjaga anak tetap melek digital, tanpa kehilangan daya pikir kritis mereka?
Antara Imajinasi dan Ilusi
Konten viral tak datang sendirian. Ia dikemas dengan visual surealis dan humor ganjil—sekilas menghibur, tapi kerap tak masuk akal. Ini bagian dari tren Italian Brain Rot, subgenre digital yang merebut atensi anak-anak Gen Alpha dengan cara yang tidak biasa. Karakter aneh yang melompat-lompat tanpa narasi jelas bukan hanya memancing tawa, tapi juga melemahkan batas antara logika dan fiksi.
Dalam kacamata psikologi perkembangan, ini bukan masalah sepele. Anak-anak usia dini masih berada di fase pra-operasional, sebagaimana dijelaskan Jean Piaget, di mana nalar mereka belum bisa membedakan secara tegas antara kenyataan dan khayalan. Ketika mereka terlalu sering terpapar konten absurd yang tidak masuk akal, kemampuan kognitifnya bisa tumpul. Realitas pun tampak seperti mainan yang bisa diputar ulang dengan efek lucu.
Perempuan di Titik Terdepan
Di tengah kegaduhan digital itu, ada satu aktor penting yang kerap luput disebut: perempuan. Dalam struktur keluarga Indonesia, perempuan—terutama ibu—masih menjadi pusat gravitasi pengasuhan. Di ruang tamu, kamar tidur, hingga meja makan, merekalah yang pertama kali mengenalkan nilai, batas, dan pemahaman soal dunia kepada anak.
Perempuan bukan sekadar penjaga waktu layar (screen time) anak, tapi juga arsitek budaya digital di rumah. Mereka menetapkan aturan, memilih konten yang layak, dan—yang lebih penting—mengajak anak berdialog tentang apa yang mereka lihat. Tanpa percakapan, gawai menjadi ruang sunyi tempat anak menelan informasi tanpa filter.
Masalahnya, sebagian orang tua masih menjadikan gadget sebagai alat penenang. Anak rewel? Buka YouTube. Susah tidur? Serahkan ponsel. Strategi instan semacam ini justru memperpanjang durasi paparan digital tanpa arah.
Melawan Brain Rot dari Rumah
Ada sejumlah langkah sederhana tapi penting yang bisa diambil. Batasi waktu layar. Anak di atas dua tahun tak disarankan menatap layar lebih dari dua jam per hari. Anak di bawah dua tahun sebaiknya tidak terpapar sama sekali. Hindari penggunaan gawai menjelang tidur, karena dapat mengganggu pola tidur dan menurunkan kualitas istirahat.
Kurangi aplikasi hiburan yang tidak mendidik. Isi waktu dengan kegiatan nyata: berkebun, memasak, menggambar, atau sekadar berbincang ringan. Yang tak kalah penting, bangun komunikasi yang terbuka di dalam keluarga. Obrolan santai sore di teras rumah bisa menjadi terapi kecil yang jauh lebih berharga daripada ratusan video TikTok.
Namun rumah bukan satu-satunya medan. Sekolah, komunitas, dan negara juga harus hadir sebagai mitra. Pendidikan digital bukan tugas individu semata, melainkan kerja kolaboratif. Literasi digital harus menyatu dalam kurikulum sekolah, program komunitas, hingga kebijakan negara yang melindungi anak dari ekosistem digital yang toksik.
Bukan Sekadar Akses, Tapi Arah
Teknologi adalah alat, bukan tujuan. Tujuan kita adalah melahirkan generasi yang kritis, sehat mental, dan bijak memilih informasi. Untuk itu, fondasi literasi digital mesti dimulai dari rumah. Jika keluarga gagal menanamkan nalar dan etika digital, jangan berharap sekolah atau negara mampu menambalnya.
Dan di titik ini, perempuan bisa menjadi motor perubahan. Di antara tugas domestik dan peran publik, mereka punya posisi strategis untuk mengarahkan ulang arah konsumsi digital anak. Teknologi boleh terus berubah setiap detik. Tapi prinsip pengasuhan yang sadar, reflektif, dan manusiawi harus tetap menjadi jangkar.
Jika tidak, maka brain rot akan menjelma sebagai norma baru. Anak-anak tumbuh sebagai generasi pelayar tanpa kompas, menatap layar tanpa tahu ke mana harus menuju.