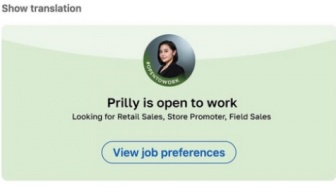Dinamika sosiologis di kota-kota besar Indonesia tengah mengalami pergeseran paradigma yang sangat mendasar.
Jika dahulu status sosial kerap ditandai oleh banyaknya waktu luang, kesanggupan seseorang untuk menikmati hidup tanpa beban kerja, kini tolok ukur tersebut telah berbalik arah secara drastis.
Dalam karyanya, sosiolog Thorstein Veblen menyebut kelompok elite dengan waktu luang melimpah sebagai leisure class, kelas santai yang menunjukkan kemewahan melalui ketidakharusan bekerja keras.
Namun, di era kapitalisme lanjut dan ekonomi digital saat ini, narasi tersebut runtuh. Kesibukan ekstrem dan jadwal yang padat justru menjadi simbol martabat baru, terutama di kalangan profesional muda perkotaan.
Fenomena ini dikenal sebagai fetisisme kesibukan, sebuah cara pandang yang mengultuskan kerja tanpa henti dan menganggap kelelahan sebagai bukti nilai diri. Dalam kerangka ini, manusia tidak lagi memaknai lelah sebagai sinyal biologis untuk berhenti dan beristirahat, melainkan sebagai lencana kehormatan. Semakin sibuk seseorang terlihat, semakin tinggi pula nilai simbolik yang dilekatkan padanya di ruang sosial.
Riset yang dilakukan Silvia Bellezza dan tim dari Universitas Columbia menunjukkan bahwa gaya hidup sibuk telah berubah menjadi simbol status aspiratif. Kesibukan memberi sinyal bahwa seseorang memiliki modal manusia yang langka, dibutuhkan, dan bernilai tinggi di pasar tenaga kerja.
Individu yang selalu terlihat tidak memiliki waktu dipersepsikan sebagai sosok yang kompeten, cerdas, dan ambisius. Dalam logika ini, kalender kerja yang penuh sesak bukan lagi sekadar alat manajemen waktu, melainkan bentuk konsumsi mencolok terhadap waktu itu sendiri.
Media Sosial dan Normalisasi Kelelahan
Media sosial memainkan peran krusial dalam menormalisasi budaya kelelahan ini. Platform seperti LinkedIn dan Instagram menjelma menjadi panggung teatrikal tempat individu memamerkan citra produktivitas tanpa henti.
Pekerjaan lembur, rapat bertubi-tubi, dan jam tidur yang minim dikemas sebagai konten inspiratif. Berdasarkan berbagai penelitian tentang identitas sosial generasi Z, media sosial memiliki pengaruh signifikan dalam pembentukan citra diri melalui tren yang viral dan algoritmis.
Tanpa disadari, individu terjebak dalam praktik manajemen merek pribadi yang menuntut pamer kerja keras secara konstan. Nilai diri diukur dari seberapa “laku” seseorang di mata pasar dan audiens digital, bukan dari makna hidup yang dijalani secara personal.
Pada titik ini, kerja keras berubah menjadi bentuk eksploitasi diri yang dilakukan secara sukarela demi validasi digital yang semu.
Sejumlah pemikir filsafat kontemporer mencatat bahwa individu modern merasa bebas karena mengejar target yang mereka tetapkan sendiri. Namun, kebebasan ini sejatinya bersifat ilusif. Target-target tersebut merupakan hasil internalisasi tuntutan pasar neoliberal yang sering kali tidak manusiawi. Manusia akhirnya menjadi budak atas nama kebebasannya sendiri. Kelelahan eksistensial pun muncul dalam bentuk gangguan mental dan fisik yang serius.
Rasa bersalah muncul ketika seseorang tidak terlihat sibuk. Diam dianggap sebagai tanda ketertinggalan dalam kompetisi sosial. Tekanan ini memaksa individu untuk terus bergerak, bekerja, dan membuktikan diri demi pengakuan sosial yang sifatnya sementara. Dalam kondisi seperti ini, istirahat menjadi sesuatu yang mencurigakan, bahkan memalukan.
Dampak Nyata pada Kesehatan Mental Anak Muda
Budaya kerja ekstrem ini berdampak langsung dan nyata pada kesehatan mental anak muda Indonesia. Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan bahwa kelompok usia 15–24 tahun memiliki prevalensi depresi tertinggi, yakni sebesar 2,0 persen. Ironisnya, kelompok usia ini juga menjadi yang paling sedikit mengakses bantuan profesional. Hanya sekitar 10,4 persen yang mencari pengobatan atau konseling di institusi kesehatan resmi.
Masalah kesehatan jiwa pada kelompok usia muda bahkan menempati posisi tertinggi kedua secara nasional. Data dari Dinas Kesehatan Yogyakarta menunjukkan bahwa 0,39 persen penduduk usia muda pernah memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup. Angka ini menjadi sinyal kuat bahwa tekanan mental yang dihadapi generasi muda bukanlah persoalan sepele, melainkan krisis yang sistemik.
Budaya kerja tanpa jeda berkorelasi erat dengan munculnya kondisi burnout. Tekanan untuk selalu relevan di media sosial memicu kecemasan kronis yang perlahan menggerogoti kesejahteraan psikologis. Banyak individu merasa gagal ketika tidak mampu menyamai pencapaian orang lain yang mereka lihat di layar ponsel. Akibatnya, lahirlah generasi yang sangat rentan mengalami gangguan kesehatan mental pada usia yang relatif dini.
Masalah Struktural, Bukan Sekadar Personal
Krisis kesehatan mental ini kerap direduksi sebagai masalah disiplin pribadi atau lemahnya manajemen waktu. Padahal, akar persoalannya jauh lebih dalam. Ini adalah cermin kegagalan sistemik dalam kebijakan ketenagakerjaan dan perlindungan sosial.
Budaya hustle tumbuh subur karena minimnya jaring pengaman sosial yang kuat. Ketimpangan lapangan kerja memaksa individu bersaing secara brutal dalam sistem ekonomi yang keras dan tidak ramah manusia.
Tekanan ekonomi global membuat banyak orang sulit menolak ritme kerja yang tidak manusiawi. Prinsip yang berlaku adalah siapa yang paling cepat dan paling keras bekerja, dialah yang bertahan.
Dukungan institusional untuk menjaga kesejahteraan psikologis pekerja masih sangat terbatas. Akibatnya, persoalan struktural dialihkan menjadi beban personal yang harus ditanggung individu secara mandiri.
Budaya ini menormalisasi stres sebagai bagian dari perjuangan hidup yang dianggap mulia. Kelelahan ekstrem diterima sebagai harga yang wajar demi bertahan hidup di tengah ketidakpastian ekonomi. Tanpa perlindungan yang memadai, pekerja muda terus terjebak dalam siklus eksploitasi yang merusak masa depan. Sistem ekonomi menempatkan efisiensi di atas nilai kemanusiaan yang paling mendasar.
FOMO, Konsumsi, dan Kerentanan Finansial
Fetisisme kesibukan juga berkelindan dengan budaya Fear of Missing Out (FOMO) yang berdampak buruk pada kondisi finansial anak muda. Ketakutan tertinggal dari tren gaya hidup mendorong perilaku konsumtif yang sering kali irasional. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa FOMO berpengaruh signifikan terhadap penurunan kesehatan finansial generasi muda.
Setiap peningkatan kecemasan sosial berbanding lurus dengan memburuknya stabilitas keuangan. Banyak individu menggunakan utang atau pinjaman daring demi mempertahankan citra di media sosial. Komodifikasi atensi telah mengubah kerentanan psikologis menjadi ladang keuntungan bagi platform digital global. Sementara itu, pengguna membayar harga mahal berupa kegelisahan, ketidakamanan ekonomi, dan rendahnya harga diri.
Fetisisme kesibukan membentuk lingkaran setan: tekanan untuk produktif mendorong konsumsi status, konsumsi memicu kecemasan finansial, dan kecemasan itu kembali memaksa individu bekerja lebih keras. Pada akhirnya, generasi muda kehilangan ketenangan batin sekaligus kemandirian ekonomi secara perlahan.
Underemployment dan Krisis Makna Kerja
Fenomena underemployment atau pengangguran terselubung semakin memperparah kondisi ini. Banyak lulusan perguruan tinggi terpaksa menerima pekerjaan yang tidak sesuai kualifikasi dengan upah rendah. Ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan pasar kerja menciptakan krisis makna kerja. Pekerjaan tidak lagi dipandang sebagai ruang aktualisasi, melainkan beban yang menguras energi.
Situasi ini memicu munculnya tren quiet quitting, yakni bekerja sekadar memenuhi kewajiban minimum untuk menghindari stres berlebih. Namun, di sisi lain, tekanan untuk memiliki banyak sumber pendapatan terus menghantui. Ijazah pendidikan tinggi tidak lagi menjamin kehidupan yang layak. Ketidakpastian ekonomi inilah yang terus menyuburkan fetisisme kesibukan.
Memanusiakan Kembali Waktu dan Kehidupan
Menolak fetisisme kesibukan adalah langkah krusial untuk memanusiakan kembali diri di era digital. Kita perlu meredefinisi kesuksesan yang selama ini didikte oleh algoritma. Istirahat bukan tanda kemunduran atau kegagalan moral. Sebaliknya, memiliki waktu untuk berhenti adalah hak dasar setiap manusia.
Produktivitas sejati tidak seharusnya mengorbankan kesehatan fisik dan mental. Kita perlu berhenti merayakan kelelahan sebagai simbol status. Hidup yang bermakna tidak semata diukur dari jumlah tugas yang diselesaikan, melainkan dari kemampuan menemukan ketenangan batin dan keseimbangan hidup.
Eksistensi manusia tidak boleh direduksi menjadi instrumen produksi semata. Budaya kerja yang sehat adalah sistem yang memberi ruang bagi kesejahteraan dan kebahagiaan. Hanya dengan menghargai jeda dan menolak glorifikasi kesibukan ekstrem, kita dapat keluar dari jeratan fetisisme kesibukan yang menipu.
Masa depan generasi muda Indonesia tidak boleh dikorbankan demi simbol status yang palsu. Kesuksesan sejati adalah hidup dengan kendali atas waktu, tubuh, dan pikiran sendiri. Kelelahan tidak layak dirayakan, dan istirahat tidak perlu disembunyikan. Hidup yang bermakna adalah hidup yang dijalani dengan kesadaran dan keseimbangan demi kesejahteraan bersama.