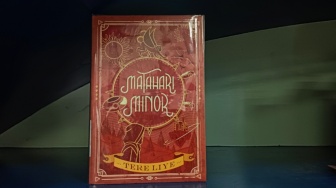Demonstrasi menuntut kenaikan gaji guru—terutama guru honorer—terus bergema. Mereka yang berdiri di barisan terdepan protes itu paham benar satu hal: guru yang dibayar tak layak tetap berusaha mengajar dengan kesungguhan.
Namun, di tengah teriakan keadilan itu, media sosial kita dipenuhi berita yang membuat hati teriris. Kasus pencabulan murid oleh guru, kasus ibu guru Salsa, pakaian guru yang ketat berlekuk, siswa SMP yang masih belum bisa membaca, hingga fenomena “inflasi nilai” di mana rapor penuh angka manis tapi kemampuan jauh dari standar.
Dulu, profesi guru identik dengan orang-orang cerdas, berwawasan, dan dihormati. Kini, tidak sedikit ruang kelas diisi oleh guru yang sekadar memutar video, menayangkan PPT seadanya, atau memberi tugas tanpa membimbing. Jam kosong menjadi pemandangan biasa. Kompetensi yang seharusnya menjadi fondasi profesi ini justru sering diabaikan. Pahitnya, dengan kualitas seperti itu, gaji pas-pasan memang terasa “sepadan”.
Rakyat Tetap Ngotot Menuntut Kenaikan Gaji Guru. Mengapa?
Karena manusia cenderung mengukur nilai sesuatu dengan uang. Barang atau jasa dianggap penting ketika dihargai mahal. Pendidikan pun begitu—tidak akan pernah naik kelas jika para pengajarnya tidak dihargai setara dengan profesi bergengsi lain.
Kenaikan gaji bukan sekadar soal kesejahteraan, tapi strategi untuk mengubah standar. Bayangkan jika gaji guru setara dokter, insinyur, atau ahli hukum. Profesi ini akan memiliki prestise yang memikat para lulusan terbaik. Persaingan menjadi guru akan ketat. Hanya mereka yang benar-benar berkualitas—lulusan universitas ternama, pemenang olimpiade, atau praktisi berpengalaman—yang bisa lolos. Barrier of entry yang tinggi ini akan memastikan anak-anak belajar dari otak-otak terbaik bangsa.
Mengajar bukan pekerjaan sambilan. Ia membutuhkan keterampilan profesional: kemampuan menguasai materi, memahami psikologi anak, mengelola kelas, dan terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Saat gaji guru rendah, kita membuka pintu lebar-lebar bagi orang malas atau tak kompeten untuk masuk demi sekadar bertahan hidup. Namun, jika gaji tinggi, standar pun otomatis ikut naik.
Jika Guru Adalah Pilar Pendidikan Bangsa, Mengapa Kualitasnya Terasa Rapuh?
Mari jujur melihat kondisi sekarang. Lulusan terbaik, anak-anak cerdas dari keluarga berpendidikan, enggan menjadi guru. Bukan karena tak cinta ilmu, tetapi karena hitungan realistis: gaji guru tidak cukup untuk hidup layak, apalagi berkembang. Banyak sarjana pendidikan yang mumpuni justru memilih profesi lain, meninggalkan dunia pendidikan yang akhirnya diisi oleh mereka yang bertahan karena tidak ada pilihan pekerjaan lebih baik.
Ini adalah lingkaran setan. Gaji rendah membuat profesi guru tidak menarik bagi talenta terbaik. Talenta rendah melahirkan pendidikan berkualitas rendah. Pendidikan buruk mencetak generasi yang lemah, dan generasi lemah akan mengelola negara dengan standar rendah pula.
Murid Butuh Guru yang Berkualitas Bukan yang Hanya Datang Memberi Tugas
Jika kita ingin memutus rantai itu, kita harus berani mengambil langkah ekstrem: naikkan gaji guru secara signifikan, lalu pasang standar kompetensi setinggi mungkin. Lakukan seleksi ketat, evaluasi berkala, dan tindak tegas yang tidak memenuhi syarat. Dengan begitu, profesi guru kembali menjadi simbol intelektualitas dan integritas, bukan sekadar pilihan terakhir.
Mungkin terdengar keras, tapi faktanya memang tak semua orang pantas jadi guru. Anak-anak kita berhak belajar dari mereka yang benar-benar ahli, berkarakter, dan berdedikasi. Jika kita terus menutup mata, kita sedang membiarkan generasi masa depan dibentuk oleh tangan-tangan yang belum tentu layak membentuknya.
Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Dan seperti semua investasi berharga, ia membutuhkan modal besar, bukan setengah hati. Membayar guru dengan layak bukanlah kemewahan—itu adalah kewajiban jika kita ingin bangsa ini berdiri dengan kepala tegak di masa depan.