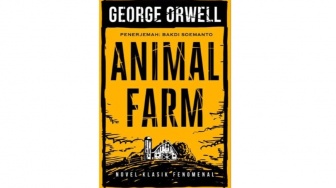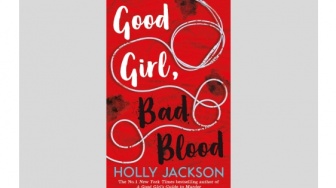Jika kita diperhatikan, banyak buku atau novel yang mengisahkan perempuan hampir selalu dipenuhi dengan luka, entah itu patah hati, kekerasan, kehilangan, atau bentuk pedih lain yang mengiringi perjalanan hidup tokoh utamanya.
Seolah-olah perempuan dalam sebuah cerita baik fiksi atau berdasarkan kisah nyata hanya bisa dihadirkan sebagai sosok yang rapuh, penuh air mata, dan harus selalu menanggung penderitaan selama hidupnya.
Fenomena ini tentu tidak lepas dari cara dunia bekerja, khususnya masyarakat patriarkis yang memandang perempuan. Sejarah panjang diskriminasi, hingga batasan peran yang dipaksakan kepada mereka, akhirnya menjadi bahan baku yang subur untuk karya sastra.
Luka-luka yang dialami perempuan kemudian dituangkan ke dalam novel, cerpen, hingga memoar. Membacanya, seakan sedang menelusuri ingatan sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Namun, ada juga alasan lain yang melatarbelakanginya, luka adalah pintu masuk yang kuat untuk membangun empati pembaca.
Banyak penulis karya sastra menuliskan kisah pedih bukan semata untuk mengulang-ulang narasi penderitaan, melainkan untuk menegaskan bahwa pengalaman perempuan layak didengar.
Sebagai contoh pada Novel Re: dan Perempuan karya Maman Suherman, yang mengurai luka seorang pelacur lesbian melalui kisah nyata yang dibingkai naratif menjadi sebuah novel.
Maman Suherman menuliskan bagaimana Re: kerap menjadi korban sistem patriarki, kekerasan, hingga diskriminasi sosial baik dari masyarakat maupun dari keluarga terdekatnya sendiri.
Setiap cerita adalah potret luka yang bukan hanya individual, melainkan struktural, dirasakan hingga ke generasi berikutnya dalam hal ini adalah Melur sebagai anak dari Re:.
Lewat kisah Re dan Perempuan, pembaca diajak untuk tidak sekadar berempati, tapi juga memahami bahwa pedihnya perempuan bukan hanya urusan pribadi, melainkan cerminan masalah sosial yang lebih luas.
Contoh lainnya adalah Perempuan di Titik Nol Karya Nawal El Saadawi, Buku klasik dari Mesir ini menyajikan kisah Firdaus, seorang perempuan yang menjalani hidup penuh penindasan, mulai dari pelecehan, eksploitasi, hingga sistem sosial yang mengekang.
Namun, di balik luka-luka itu, ada perlawanan yang keras dan lantang. Nawal El Saadawi menunjukkan bahwa meskipun luka perempuan begitu dalam, kisahnya bukan sekadar tentang penderitaan, tapi juga tentang keberanian untuk bersuara dan menolak tunduk pada sistem yang menindas.
Dalam kesedihan tokoh fiksi, banyak pembaca, khususnya perempuan menemukan cermin atas luka mereka sendiri, dan dari sana lahir perasaan divalidasi.
Masalahnya, jika narasi perempuan hanya disajikan dalam bentuk luka, potensi lain dari perjalanan hidup mereka bisa tereduksi. Perempuan tidak hanya tentang penderitaan.
Ada juga kisah tentang keberanian, kegembiraan, penemuan jati diri, dan kemenangan yang sering kali terpinggirkan. Inilah tuhas besar bagi dunia literasi, bagaimana menghadirkan perempuan bukan sekadar sebagai korban, melainkan juga sebagai sosok yang berdaya.
Namun, kisah-kisah perempuan yang penuh luka tetap penting karena mereka berbicara tentang kenyataan yang memang dialami banyak orang.
Sehingga banyak dari pembaca yang lebih berempati dan saling menghargai atas dinamika kehidupan manusia khususnya perempuan yang mungkin awalnya tidak mereka kira ada dikehidupan yang begitu luas ini.
Hal ini juga bukan semata untuk membuka lagi luka lama bagi perempuan, tetapi sebagai bentuk pembelajaran dan pengetahuan bagi masyarakat.
Semoga ke depan, akan lebih kaya jika literatur juga memberi ruang bagi narasi lain seperti perempuan yang lebih berdaya, bermimpi, berjuang, dan bahagia tanpa harus diawali atau diwarnai oleh kepedihan.